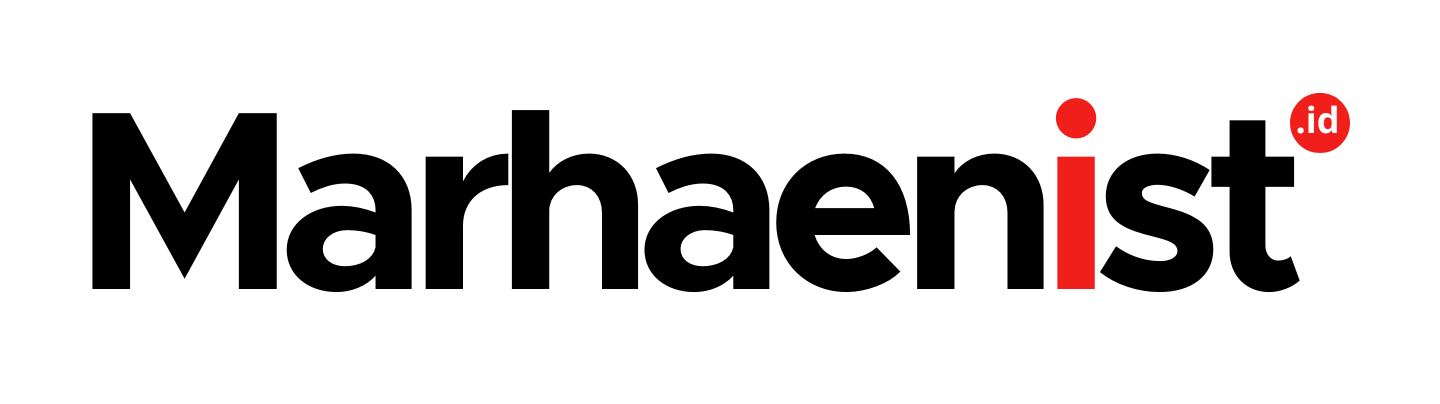Marhaenist.id – Diskursus mengenai konsepsi negara hukum Pancasila telah lama menjadi wacana dalam berbagai forum akademis dan ilmiah yang tak kunjung usai dibicarakan dan diperdebatkan. Semuanya sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rechtsstaat maupun rule of law. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia, yakni Pancasila. Meskipun identifikasi dan perumusan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis, terstruktur, dan massive3 untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembentukan hukum nasional.
Munculah kemudian pertanyaan bagaimana hendaknya hukum Indonesia itu dibangun sebagai sarana atau wahana yang dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia, yakni terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur. Secara historis dapat dilihat bahwa muncul berbagai aliran atau pandangan berbeda-beda dan mendasarkan pada perspektif serta sudut pandang yang pada intinya mengikuti diskursus yang terjadi pada awal abad ke-20 (pada masa Hindia Belanda) antara Nederburgh dan Nollst Trenite dan Cornelis Van Vollenhoven. Di satu pihak Nederburgh dan NollstTrenite menghendaki adanya unifikasi dan kodifikasi hukum di wilayah Hindia Belanda yang konkordan dengan hukum Belanda, sedangkan Van Vollenhoven menghendaki adanya pluralisme hukum di Hindia Belanda dengan diberlakukannya “Adat Rechtsbringen”.
Di alam kemerdekaan hingga saat ini polemik itu pun masih terjadi, tokoh yang menghendaki hukum adat dijadikan bahan utama pembentukan hukum nasional adalah Prof. Djojodigoeno, Prof. Koesnoe, dan Prof. Malikoel Saleh. Sedangkan Prof. Bustanil Arifin dan Prof. Hazairin adalah eksponen yang berpendapat bahwa hukum Islam hendaknya menjadi hukum nasional atau setidak-tidaknya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.
Sedangkan tokoh-tokoh yang menghendaki unifikasi dan kodifikasi hukum nasional adalah Prof. Djoko Soetono, Prof. Sudiman Kartohadi Prodjo, Prof. Soenaryo, dan Prof. Subekti. Sedangkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat agak berbeda dengan hal tersebut.
Usulannya berkenaan dengan apa yang disebutnya sebagai unifikasi dan kodifikasi parsial untuk bidang-bidang hukum yang tidak sensitif yang diunifikasi dan dikodifikasi, sedangkan bidang hukum yang sensitif dibiarkan tumbuh dulu sampai kelak menjadi yurisprudensi atau dijadikan undang-undang, jadi sudah menjadi bagian hukum nasional.
Konsepsi Negara Hukum Pancasila
Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), yang dalam Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Perubahan UUD 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep Rechtsstaat namun lebih diterjemahkan kedalam konsep negara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsep negara hukum yang sesungguhnya dianut oleh Indonesia pasca Perubahan UUD 1945, apakah itu Rechtsstaat ataukah the Rule of Law (?) Pertanyaan yang muncul dan tidak kalah penting juga adalah apakah sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 negara Indonesia memang benar-benar sepenuhnya menganut konsep Rechtsstaat (?).
Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.
Dengan melihat pada dua parameter tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep Rechtsstaat dan bukan pula konsep the Rule of Law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat didalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “staatsfundamentalnorm” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan
membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.
Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:
Pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan
sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupunthe Rule of Law yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan,serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Ketiga, merupakan religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara
negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan.
Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatik ini adalah bahwa atheisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya kurang setuju dengan berlakunya prinsip pluralisme/multikulturalisme diterapkan di Indonesia. Pandangan Saya semestinya di Indonesia menganut asas/prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun sistem hukum nasional. Sehingga meskipun kita perlu menganut prinsip unifikasi hukum, namun unifikasi hukum yang kita anut dan kita bangun mestilah memperhatikan sisi-sisi universal dari setiap perbedaan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.
Membumikan Konsep Negara Hukum
Pancasila Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (certificate of birth) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (rechtsidee) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi staatsfundamentalnorms atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945.
Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia
berdasarkan konsep negara hukum Pancasila, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia.
Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila).
Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia (Pancasila), yakni:
1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.
Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:
1. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis
maupun secara teritorial;
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnua dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan rechtsidee;
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.
Pembangunan sistem hukum nasional tersebut, bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari
(1) hukum adat asli, sebagai suatu living law yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; (2) hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; (4) hukum Jepang. Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukumdalam civil law system; (3) perkembangan hukum dalam common law system.
Pada tahap selanjutnya dari dua sumber hukum materiil pra dan pasca kemerdekaan ini dibangunlah suatu sistem hukum nasional yang ditujukan untuk melakukan perubahan sistem hukum nasional dan pembaharuan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional ini dilakukan dengan didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik dimulainya pembangunan sistem hukum nasional dan didasarkan pada UUD Tahun 1945 (atau UUD NRI Tahun 1945, pasca perubahan UUD) dimana didalam pembukaan dan pasal-pasal dalam undang-undang dasar memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari pembangunan sistem hukum nasional.
Dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat prismatik inilah maka diharapkan lahir sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang seutuhnya sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Adapun dalam pembangunan sistem hukum nasional dewasa ini (pasca reformasi) tidak terlepas dari berbagai hambatan baik itu yang berasal dari dalam (intern) maupun luar (ekstern). Hambatan yang berasal dari dalam antara lain pertama, budaya masyarakat yang cenderung feodalistik dan paternalistik menyebabkan hukum menjadi elitis dan korup Kedua, tidak adanya kesadaran politik kebangsaan dan kenegaraan (politik nasional) para
penyelenggara negara, sehingga hukum yang notabene merupakan suatu hasil dari proses politik tidak mendasarkan dirinya pada kepentingan nasional namun hanya pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Sedangkan hambatan yang berasal dari luar adalah pertama, pengaruh globalisasi yang membawa ideologi-ideologi lain diluar Pancasila sehingga mempengaruhi pemahaman yang utuh terhadap Pancasila serta mempengaruhi pola pikir (mind set) masyarakat. Kedua, adanya tekanan politik luar negeri negara adikuasa, sehingga terjadi pertentangan antara kepentingan nasional dan kepentingan asing yang sangat mempengaruhi proses pembangunan sistem hukum nasional. Dengan begitu maka diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum nasional yang (1) dapat menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial; (2) berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan rechtsidee; (3) dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; (4) dapat mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan
tertentu. Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee). Dengan demikian, Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembentukan hukum nasional.
Peran dan Fungsi MK dalam Membangun Sistem Hukum Pancasila
Menurut Hamid Attamimi, Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) memiliki dua fungsi yaitu fungsi konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus menerus. Konsekuensinya Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental dalam sistem norma hukum yang menentukan agar norma-norma hukum yang berada di bawahnya dibentuk sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila.
Namun dalam sistem hukum kita tidak ada suatu mekanisme manakala UUD yang diubah dan telah disahkan ternyata terdapat inkoherensi, inkonsistensi, inkorespondensi bahkan muncul pertentangan antara pasal-pasal yang berada dalam batang tubuh dengan ruh UUD, yakni dengan pembukaan UUD 1945 yang di dalam alinea IV termaktub Pancasila, kecuali dengan perubahan UUD melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah adalah MPR.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), sejak awal pendiriannya, tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land), tetapi juga mengawal Pancasila sebagai ideologi negara (the guardian of ideology). Hal ini dapat terlihat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik. Dalam Pasal 68 UU MK, disebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena Pancasila merupakan ruh dari UUD 1945 yang termuat dalam bagian Pembukaan, maka adalah suatu keniscayaan bahwa Pancasila juga merupakan batu uji dalam perkara pembubaran partai politik. Bahkan lebih jauh lagi, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi, maka selain mendasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, juga harus mendasarkan pada Pancasila sebagai batu uji dalam setiap perkara konstitusi. Nilai-nilai luhur Pancasila yang abstrak telah dijadikan standar evaluasi konstitusionalitas norma hukum, dalam hal ini undang-undang, kemudian diejawantahkan dan tercerminkan dalam setiap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tak sampai disitu, sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi melihat adanya kepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang sekaligus menjadi jiwa dari UUD 1945.
Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yakni tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial dan adil. Pada konteks inilah tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa di samping sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal ideologi negara (the guardian of state’s ideology). Oleh karena itu, di luar fungsi sebagai peradilan konstitusi, MK turut aktif mengambil peran dan tanggung jawab membumikan kembali Pancasila dan konstitusi dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil pertemuan para pimpinan lembaga negara pada 24 Mei 2011 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi yang diantaranya menyepakati perlunya upaya untuk merevitalisasi, mereaktualisasi, dan mereinternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui gerakan bersama secara sistematis, terstruktur dan massive dengannmelibatkan seluruh elemen bangsa sehingga ruh Pancasila merasuk ke dalam sumsum dan nadi setiap penyelenggaraan negara dan masyarakat serta menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi.
Dalam pertemuan itu pula disepakati bahwa upaya membumikan Pancasila bukanlah monopoli satu lembaga, meskipun saat ini telah terbentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang di nakhkodai oleh Yudi Latif, namun seluruh lembaga negara dapat berperan membumikan Pancasila sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
Diakhir tulisan ini saya ingin mengatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam pohon ilmu hukum diibaratkan sebagai dasar dan fondasinya; Serat-serat pokok ilmu seperti Sosiologi, Politik, Budaya, Antropologi, Ekonomi dan Psikologi sebagai batangnya serta dapat digunakan relasi ilmu bantu untuk membahas/mengkaji hukum dan ini berguna untuk memperkaya dan melengkapi pengkajian terhadap hukum (muncul cabang studi hukum baru yang diberi nomenklatur sosiologi hukum, politik hukum, bahasa hukum,dst); Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan sebagainya sebagai cabang dan rantingnya; serta kebijakan dan implementasi sebagai daunnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai staatsfundamentalnorms atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan hanya dalam cita. Tidak hanya retorika atau verbalisme tetapi dalam setiap aksi dan tindakan dan juga mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, berkorespondensi dengan realitas sosial, dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, serta komitmen bersama sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan, tetapi juga sebagai falsafah bangsa.
Namun yang perlu diingat adalah bahwa Pancasila bukanlah dasar yang statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis sehingga Pancasila dioperasionalkan dan diaktualisasikan supaya responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Artinya Pancasila senantiasa terbuka bagi proses dan penafsiran baru dengan syarat memerhatikan semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta keterkaitan antarsila.
Dengan demikian Pancasila harus menjadi ruh yang melandasi pembentukan hukum nasional dan setiap tindakan penyelenggaraan negara dan masyarakat sehingga prinsip ketuhanan yang sarat nuansa moral menjadi pondasi inti yang menyinari sila kemanusiaan, sila persatuan, sila Kerakyatan, dan sila keadilan sosial sehingga terwujud negara kesejahteraan yang relijius (religious welfare state) sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara (the founding fathers).***
Penulis: Arief Hidayat, Ketua Umum DPP PA GMNI.