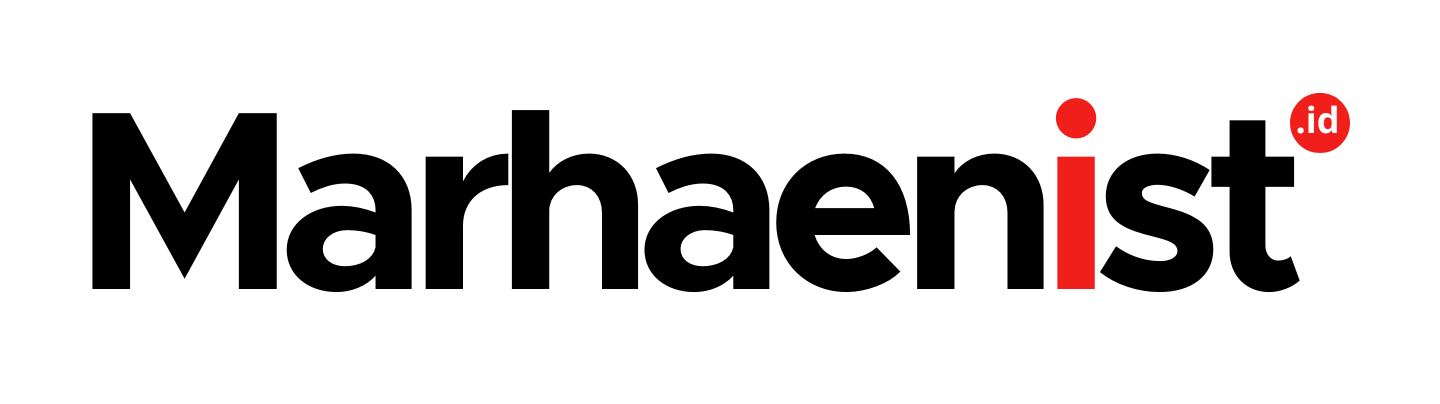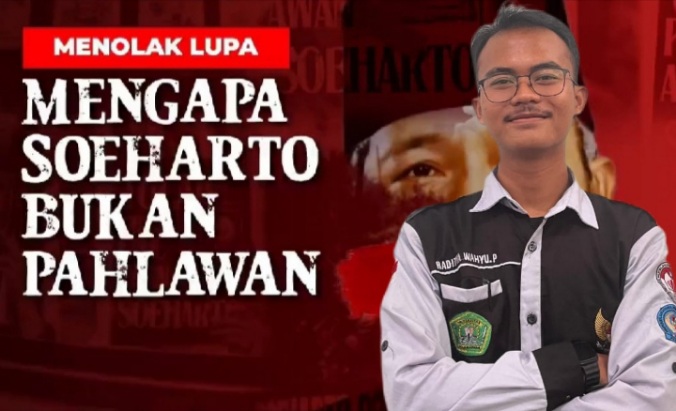Marhaenist.id – Soeharto, nama yang sudah menjadi sebuah monumen yang terbuat dari kontradiksi, berdiri tegak di cakrawala sejarah Indonesia. Senja panjang yang membentang tiga puluh dua tahun, dimana janji kemakmuran dan stabilitas menjadi madu manis, tetapi dibalik tabir, keheningan dipenuhi bisikan ketakutan. pancasila di tunggangi sebagai alat pelenggang kekuasaan. Betapa bengisnya Soeharto dibalik tameng penegakan ideologi Pancasila sebagai alat untuk menggenosida.
Bukankah ia yang menanam benih-benih luka tapi masuk nominasi orang berjasa. Kebutaan sejarah bangsa dimanfaatkan sebagai alat pencuci nama. Ketika derai tangis keluarga korban hanya dianggap sebagai gemuruh hujan. Ironi nya marsinah disandingkan dengan pembunuhnya. Mahkota kekuasaan yang terpasang tiga puluh dua tahun itu juga meninggalkan noda: noda darah yang belum kering dari tangan korban, dan karat korupsi, kolusi, nepotisme yang menggerogoti tiang integritas bangsa. Ia adalah jenderal yang membawa luka dan bayangan yang menyembunyikan kebenaran di balik jeruji besi.
Kini kita dipaksa melihat diktator memakai mahkota pahlawan diatas kepala yang sarat pujian dan celaan. Apakah gelar kehormatan ini akan menjadi penghargaan ataukah ia justru menjadi penghinaan yang mengkhianati air mata para pencari keadilan? Sejarah menanti, dan hati nurani bangsa menjadi juri.
Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Suharto mencerminkan upaya pemerintah untuk mengukuhkan warisan politik dan kekuasaan rezim Orde Baru, namun keputusan ini justru memicu kontroversi karena mengabaikan rekam jejak pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan yang terjadi selama masa pemerintahannya, sehingga perlu dikaji ulang dari perspektif keadilan sejarah dan etika publik.
Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto resmi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan 2025. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan program swasembada beras yang sangat diingat oleh masyarakat.
Namun, langkah ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, terutama yang menganggap pemberian gelar tersebut mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan represi yang jadi pada masa rezim Orde Baru. Hal ini menyebabkan perdebatan mendalam dalam memori kolektif bangsa mengenai makna sesungguhnya dari gelar pahlawan nasional yang seharusnya mewakili keberanian, pengorbanan, dan integritas moral tinggi.
Selama masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung sekitar 32 tahun di era Orde Baru, terdapat catatan panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan kekejaman yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dan temuan Komisi Nasional HAM dan organisasi seperti KontraS, Soeharto bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat seperti:
1. Tragedi 1965-1966, dengan pembunuhan, penangkapan massal, penahanan tanpa pengadilan, dan pengusiran terhadap ribuan orang yang diduga terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.
2. Penembakan misterius pada tahun 1981-1985 yang menewaskan sekitar 5.000 orang di berbagai wilayah Jawa.
3. Insiden Talangsari di Lampung tahun 1989 yang menimbulkan sekitar 130 orang tewas, pengusiran paksa, penyiksaan, dan penganiayaan.
4. Kebijakan represif Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 yang menyebabkan ribuan tindakan teror seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan seksual, serta pembunuhan.
5. Peristiwa Tanjung Priok 1984 yang menandakan tindakan keras aparat terhadap warga sipil.
6. Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II di akhir era Orde Baru yang memakan korban mahasiswa dan aktivis.
Penghilangan orang secara paksa, pembunuhan aktivis buruh dan wartawan, serta pembredelan media massa yang mengindikasikan represi politik dan pembungkaman kebebasan.
Selain itu, laporan berbagai lembaga HAM mengungkap bahwa kekerasan berat termasuk terhadap perempuan dan anak-anak juga terjadi dalam berbagai konflik sosial di masa Soeharto. Penyelidikan resmi pernah memutuskan terdapat 9 kasus pelanggaran HAM berat di bawah rezimnya, termasuk genosida politik dan pelanggaran sistematis lainnya.
Dengan latar belakang itu, kritik terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto muncul dari sejumlah organisasi dan korban yang menilai gelar tersebut mengabaikan luka dan penderitaan yang diakibatkan oleh kekuasaannya.
Para ahli memberikan pandangan beragam terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Akademisi Dr. Arwan M. Said dari IAIN Ternate mengajak bangsa untuk melihat sejarah Soeharto secara utuh, menghargai jasanya dalam stabilitas dan pembangunan tanpa menutup luka sejarah, mengedepankan kedewasaan bangsa dalam memaafkan dan belajar dari sejarah.
Di sisi lain, Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid dan aktivis HAM seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menolak pemberian gelar tersebut karena nilai kepahlawanan harus mencakup karakter moral dan pengorbanan untuk kemaslahatan rakyat, sedangkan Soeharto punya rekam jejak pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan selama masa Orde Baru, seperti pembantaian 1965-1966, represi mahasiswa dan kelompok tertentu, serta pelanggaran HAM di Talangsari dan lainnya.
Pandangan ini menunjukkan ketegangan antara penghargaan atas jasa pembangunan dan kritik terhadap pelanggaran HAM serta aspek moral kepemimpinan Soeharto, mencerminkan kompleksitas dan kontroversi yang melekat dalam pemberian gelar pahlawan nasional kepadanya.
Kesalahan penilaian dalam pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sering dikritik dengan menyandingkan nasibnya dengan korban pelanggaran HAM seperti Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada masa Orde Baru.
Kritik utama menyebut bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan pada sosok yang memiliki integritas moral dan perjuangan demi kemaslahatan rakyat, bukan sebaliknya menjadi simbol kekuasaan otoriter yang menyebabkan penderitaan dan kematian banyak orang.
lembaga kajian Public Virtue Research Institute (PVRI) yang menilai keputusan ini cacat logika karena hanya mempertimbangkan kelayakan administratif tanpa menghitung dosa-dosa besar pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi selama rezim.
PVRI melihat gelar tersebut sebagai skandal politik terbesar era Reformasi yang meremehkan luka sejarah dan mengabaikan nilai keadilan bagi korban seperti Marsinah dan kelompok yang dirugikan rezim Soeharto.
Mengenakan gelar pahlawan kepada figur yang kontroversial ini tanpa penyelesaian dan pengakuan atas kesalahan masa lalu bisa menjadi bentuk pengabaian nilai keadilan dan moralitas dalam konsep kepahlawanan.
Gelar pahlawan seharusnya tidak hanya mencerminkan pencapaian pembangunan, tetapi juga integritas moral, keberanian, dan pengorbanan untuk kemaslahatan rakyat tanpa menimbulkan ketakutan dan penderitaan. Penghormatan ini harus berdasar pada kejujuran sejarah, bukan sekadar legitimasi politik atau nostalgia kekuasaan.
Dengan demikian, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah keputusan yang sangat kontroversial dan memerlukan dialog terbuka dan keadilan sejarah, agar bangsa ini tidak melupakan korban dan pelajaran sejarah agar tidak terulang. Ini menjadi pengingat penting bahwa kepahlawanan sejati mencakup tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang utuh, bukan hanya pencapaian materi atau pengaruh politik semata.***
Penulis: Raditya Wahyu Pramuji, Kader GMNI Univesitas Mulawarman.