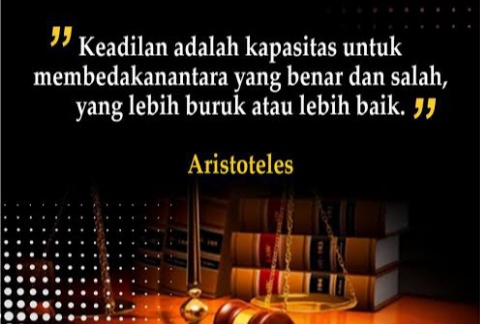Marhaenist.id – Krisis hukum di Indonesia bukanlah takdir. Ia adalah hasil kelalaian kolektif bangsa yang membiarkan hukum kehilangan arah moralnya. Dari perkara sandal jepit yang divonis bersalah hingga kasus korupsi triliunan rupiah yang berakhir dengan senyum dan koper uang, rakyat terus dipaksa menyaksikan hukum berjalan pincang: tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Dua puluh tahun lebih reformasi hukum berlalu, namun wajah keadilan tak banyak berubah. Kita menumpuk regulasi, menambah lembaga, dan membentuk mekanisme pengawasan baru, tetapi gagal menumbuhkan etika hukum yang hidup. Karena itu, yang dibutuhkan bukan lagi reformasi prosedural, melainkan revolusi etika hukum—keberanian mengembalikan hukum kepada jantung kemanusiaannya: alat keadilan, bukan komoditas kekuasaan.
Hukum yang Kehilangan Nurani
Filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch pernah mengingatkan, ketika jarak antara hukum dan ketidakadilan mencapai puncaknya, maka “hukum yang paling tidak adil sekalipun kehilangan sifatnya sebagai hukum.”
Pandangan ini menolak legalitas tanpa moralitas. Sebab, hukum tanpa keadilan hanyalah bentuk tirani yang disahkan.
Pemikir hukum Indonesia Satjipto Rahardjo pun menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan pada teks. Dalam konsep hukum progresif, ia menempatkan manusia sebagai pusat nilai hukum. Hukum seharusnya hidup dan berjiwa, bukan membatu di balik formalitas pasal.
Kenyataannya kini, banyak keputusan hukum yang tidak lagi berpijak pada nurani. Ketika keadilan dikorbankan demi kepentingan politik dan ekonomi, maka hukum telah kehilangan jiwa yang mestinya ia lindungi.
Agenda Progresif: Dari Reformasi ke Revolusi
Reformasi hukum selama ini terjebak dalam kosmetika struktural—mengganti undang-undang tanpa mengubah cara berpikir. Padahal, akar krisis hukum Indonesia bukan hanya pada institusi, tetapi pada mentalitas. Kita membutuhkan revolusi hukum yang menyentuh fondasi moral dan kultural bangsa.
Empat agenda progresif berikut menjadi arah langkah nyata:
Kesatu. Dekonstruksi Sistem Peradilan Elitis
Peradilan harus bebas dari dominasi politik dan ekonomi. Proses rekrutmen hakim, jaksa, dan aparat hukum harus berbasis integritas dan meritokrasi, bukan patronase.
Komisi Yudisial perlu diperkuat sebagai “pengadilan atas hakim” dengan kewenangan dan akses publik untuk mengawasi moralitas serta independensi hakim. Transparansi adalah syarat dasar keadilan.
Kedua. Revitalisasi KPK sebagai Garda Revolusi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikembalikan ke posisinya semula sebagai lembaga extraordinary power. Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang 2019 merupakan kemunduran moral dan pengkhianatan terhadap semangat konstitusional.
Pemberantasan korupsi bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan moral bangsa. Tanpa KPK yang kuat dan independen, hukum akan terus dikendalikan oleh kekuasaan uang.
Ketiga. Desakralisasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus keluar dari bayang-bayang kompromi politik. Seleksi hakim agung dan konstitusi tidak boleh ditentukan oleh transaksi kekuasaan, tetapi melalui proses transparan dan partisipatif.
Kasus dugaan suap di MK pada 2023 seharusnya menjadi peringatan keras bahwa integritas lembaga hukum tertinggi tidak boleh diasumsikan, tetapi harus diuji secara terbuka. Setiap putusan pengadilan perlu diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada “harga di balik vonis.”
Keempat. Membangun Kultur Hukum Rakyat
Revolusi hukum sejati harus dimulai dari rakyat. Hukum harus menjadi sarana pembebasan, bukan penindasan.
Pendidikan hukum perlu diarahkan pada pembentukan karakter dan etika keadilan.
Mahasiswa hukum tidak boleh hanya dilatih menghafal pasal, tetapi juga dididik untuk berpikir empatik dan reflektif terhadap penderitaan sosial. Tanpa kesadaran moral, lulusan hukum hanya akan menjadi birokrat legalitas, bukan penjaga nurani keadilan.
Keberanian Politik dan Kebangkitan Nurani
Revolusi hukum tidak mungkin lahir tanpa keberanian politik. Diperlukan pemimpin yang berani memutus mata rantai korupsi, menolak kooptasi oligarki, dan menegakkan hukum di atas kepentingan kekuasaan.
Kita tidak butuh lebih banyak undang-undang, melainkan jiwa hukum yang berani hidup dalam kebenaran. Sebab tanpa nurani, hukum hanyalah mesin dingin yang bekerja atas nama legalitas, tetapi menindas manusia atas nama prosedur.
Republik Tanpa Nurani
Kita hidup di tengah “black market on justice,” pasar gelap hukum di mana vonis, jabatan, dan perkara bisa dinegosiasikan. Rakyat menjadi penonton dalam sandiwara keadilan yang dimainkan oleh elite.
Selama hukum tunduk pada oligarki dan kapital, keadilan hanya akan menjadi mitos. Indonesia akan terus menjadi republik tanpa nurani—negara yang menegakkan hukum tanpa keadilan dan menulis keadilan tanpa keberpihakan.
Karena itu, revolusi etika hukum bukan pilihan ekstrem, melainkan satu-satunya jalan untuk memulihkan martabat bangsa. Revolusi ini menuntut keberanian kolektif—dari pemimpin hingga rakyat biasa—untuk menjadikan hukum bukan sekadar teks, melainkan cermin nurani bangsa.
Tulisan ini merupakan refleksi atas krisis moralitas hukum dan pentingnya etika keadilan dalam kehidupan bernegara.***
Penulis: Firman Tendry Masengi, Alumni GMNI/Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute.