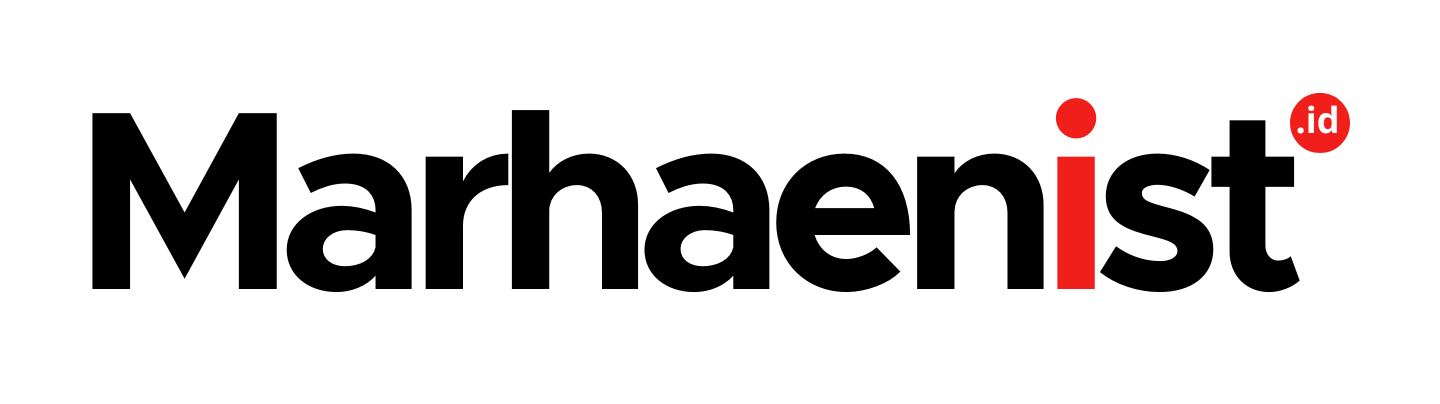Marhaenist.id – Pada tahun 1969, 800-an tahanan politik yang dituduh terlibat dalam kudeta ’65 diasingkan ke Pulau Buru menggunakan kapal ADRI dan dibawa menuju kamp konsentrasi terbesar yang pernah diciptakan rezim pasca kemerdekaan Indonesia.
Bersama ratusan orang itu, disusul oleh kedatangan-kedatangan selanjutnya hingga 11.000 tapol, yang dibagi dalam 21 unit, dipaksa berjuang hanya agar tetap hidup di sebuah pulau yang dikepung savanah dan hutan-hutan, dengan luas 9.100 km2 atau 910.000 Ha. Ratusan tapol tiba di dermaga Namlea dan disambut oleh prajurit Pattimura dengan senapan serta pukulan, dan sebagai persona non grata, mereka bisa diperlakukan secara sewenang-wenang oleh negara.
Dipilihnya Pulau Buru sebagai lokasi pembuangan, bertujuan untuk membatasi akses informasi dan aktivitas tapol yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh negara, dan meringangkan beban keuangan pemerintah demi terwujudnya program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)—dan oleh sebab itu para tapol harus mampu mencukupi kebutuhan hidup secara subsisten tanpa menggunakan anggaran negara dengan bertitik-tolak pada gagasan transmigrasi.
Mereka diwajibkan untuk membuka lahan pertanian; sawah; membuat jalan; membangun bendungan dan saluran irigasi; mendirikan barak juga rumah peribadatan; poliklinik dan sederet fasilitas publik di lokasi Pemanfaatan (Tefaat). Belum lagi tak tersedianya alat produksi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Membuka jalan yang dipenuhi alang-alang, rumput beruas terpaksa dilakukan dengan tangan telanjang sepanjang berkilo-kilo meter. Tak ada waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga, sebaliknya mereka dipaksa untuk terus bekerja demi mewujudkan target pembangunan di Tefaat Buru tak penting mereka sekarat atau bahkan mati dalam kerja yang lebih pantas disebut perbudakan.
Dalam perspektif ekonomi-politik, aktivitas produksi para tapol yang mendekam di pembuangan Pulau Buru bukanlah perkembangan yang terpisah dari deindustrialisasi dan kemerosotan regional, gentrifikasi dan pertumbuhan ekstra-metropolitan, industrialisasi dunia ketiga dan nasionalisme politik yang intensif dan perang geopolitik baru, demikian merupakan gejala dari transformasi geografi kapitalisme yang jauh lebih dalam. Untuk itu, akumulasi kapital harus didorong melalui produksi ruang dan penciptaan tenaga kerja murah melalui proteksi kebijakan negara. Itu sebabnya penciptaan ruang untuk menjamin produksi komoditas, pasar untuk akumulasi kapital, harus bersamaan dengan pengarahan tenaga kerja. Sebab akumulasi kapital—lewat pertukaran pasar—akan berkembang paling baik ketika dipayungi oleh struktur institusional hukum di bawah komando negara.
Orde Baru sebagai a strong goverment memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan, bisa menjamin terciptanya kerangka institusional semacam itu dan mendukung keberadaan semua itu dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Karena itulah, formasi negara, dibarengi dengan keberadaan instrumen yang berwatak borjuis, merupakan fitur-fitur krusial di dalam geografi historis yang panjang dari kapitalisme.
Oleh sebab itu, pembuangan tapol di Pulau Buru mestinya tidak hanya dilihat berdasarkan perspektif moralnya yang sekadar bertumpu pada tidak adanya keadilan bagi mereka yang tak pernah terbukti bersalah dalam putusan pengadilan untuk membuktikan keterlibatan mereka, melainkan harus dilihat dari bagaimana para tapol yang menjalani aktivitas produksi, sebenarnya berorientasi pada penetrasi kapital, mekanisme-mekanisme politik yang berlangsung dan tentunya aktivitas sosial-produksi di tengah kehidupan pembuangan. Hal ini disebabkan pasca peristiwa 65, penetrasi kapital telah mendorong restrukturisasi ruang geografis, pengarahan tenaga kerja dan penciptaan kontrol komoditas yang sesuai dengan program Repelita yang bertumpu pada kerja produksi pertanian.
Dengan kata lain, fenomena politik dan ekses yang menimpa para tapol dari tahun 1969-1979 di Pulau Buru tidak sekadar impact dan peristiwa politik 1965 yang bertujuan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan seluruh gerakan rakyat yang mendukung kekuasaan lama. Lebih jauh, kita harus melihatnya sebagai periode komando tertinggi ekonomi dunia kapitalis pasca runtuhnya gagasan Sosialisme Indonesia di bawah kekuasaan Soekarno. Inilah fase ketika Indonesia memasuki periode liberalisasi ekonomi yang dipandu langsung melalui instrumen negara.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah kerja dan hasil produksi para tapol, kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pembesar yang bertugas di pembuangan. Pram, dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, mengaku bahwa ketika panen pertama di Tefaat, tapol menghasilkan 84 ton beras dan 730 kubik kayu papan, namun oleh Kapten Sudjoso Hadisiswojo diperintahkan untuk dibawa ke Namlea dengan pertanggungjawaban yang kurang jelas sementara mereka hanya mendapatkan jatah sebanyak 150 gram beras.
Hal yang sama juga berlaku untuk ayam dan telur yang dihilirkan ke Namlea untuk membiayai perselingkuhan dan membangun rumah papan yang cukup besar untuk kekasih Kapten Sudjoso dan semuanya harus ditanggung oleh tapol.
Dalam proses ini, penderitaan bertalu-talu, kelaparan, penganiayaan, pelbagai penyakit mengepung dan mengambil banyak nyawa manusia. Banyak juga di antara para tapol ini memupus nyawanya sendiri untuk mengakhiri penderitaan mereka. Belasan ribu manusia tersebut merupakan kelas pekerja tanpa upah layak, jaminan hidup dan waktu kerja yang manusiawi, dan menjadi bagian dalam kategori tentara cadangan pekerja (reserve army of labor) yang tidak bekerja untuk upah, tetapi sewaktu-waktu bisa ditarik menjadi pekerja upahan jika memang dibutuhkan.
Sebab itu, dibutuhkan intimidasi dan kekerasan yang nyata untuk mendorong produktifitas dan mempercepat proses akumulasi, seperti yang diungkapkan Marx—bahwa dalam sejarah yang sebenarnya, ada fakta yang sangat buruk bahwa penaklukkan, perbudakan, perampokan, pembunuhan, dan pemaksaan, memainkan bagian yang paling besar (Capital 1: 873). Tetapi nyawa manusia yang mati dalam periode tersebut hanya laporan dalam angka yang tidak pernah diakui negara.
Apa yang terjadi dalam tahun-tahun panjang di Pulau Buru adalah sesuatu yang lekat dengan ciri umum eksploitasi tenaga kerja pada masyarakat perbudakan yang terjadi dalam fase prakapitalis dan dengan itu menjalani transisi menuju kapitalisme. Corak produksi yang dipandu negara di Pulau Buru, mirip dengan apa yang disampaikan Bernstein dalam menjelaskan terkait kolonialisme dan perubahan agraria di mana “proyek kolonial bergantung pada bagaimana wilayah-wilayah koloni ‘membiayai diri’ dan menghasilkan keuntungan bagi kekuasaan kolonial” (Bernstein 2019: 59). Sebab itu, eksploitasi terhadap tapol sebagai tenaga kerja, adalah suatu kondisi yang didorong oleh kebutuhan untuk memperluas skala produksi dan kehendak untuk mengontrol apa yang mesti diproduksi.
Para tapol menjadi alat Orde Baru yang dapat diatur untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari mereka (subsisten), demikian pula untuk memproduksi komoditas-komoditas pertanian dengan nilai baru di mana selisih antara keduanya itu melahirkan nilai lebih ketika surplus tenaga kerja (tapol) menjadi sumber laba, tanpa harus mengeluarkan biaya besar yang nantinya menjadi babak pembuka dari politik transmigran yang menjadi salah-satu program utama untuk mendorong pembangunan di masa Orde Baru.
Di penghujung Nyanyi Sunyi, Pram menulis dengan lirih: ” “Selama sepuluh tahun tapol diisolasi di Pulau Buru, telah dicetak sawah dan ladang seluas 3. 532, 5881 Ha., dibangun jalan-lingkungan dan arteri sepanjang 175 km, berikut bendungan dan irigasi.
Kesemuanya dikerjakan oleh modal tenaga tapol sendiri, tanpa pembiayaan dari luar atau Repelita kesekian. Belum terhitung barak-barak, masjid, gereja, sekolah, pasar, dermaga, dsb. Betul, tapol Indonesia telah membiayai penahanannya sendiri. Di mana di dunia beradab hal seperti ini terjadi? Tidak ada ganti-rugi atau imbalan kepada yang telah mengerjakan semua itu ketika diteruskan oleh Departemen Transmigrasi.”***
Penulis: Muhammad Iqbal Tarafannur, Institut Marhaenisme 27.