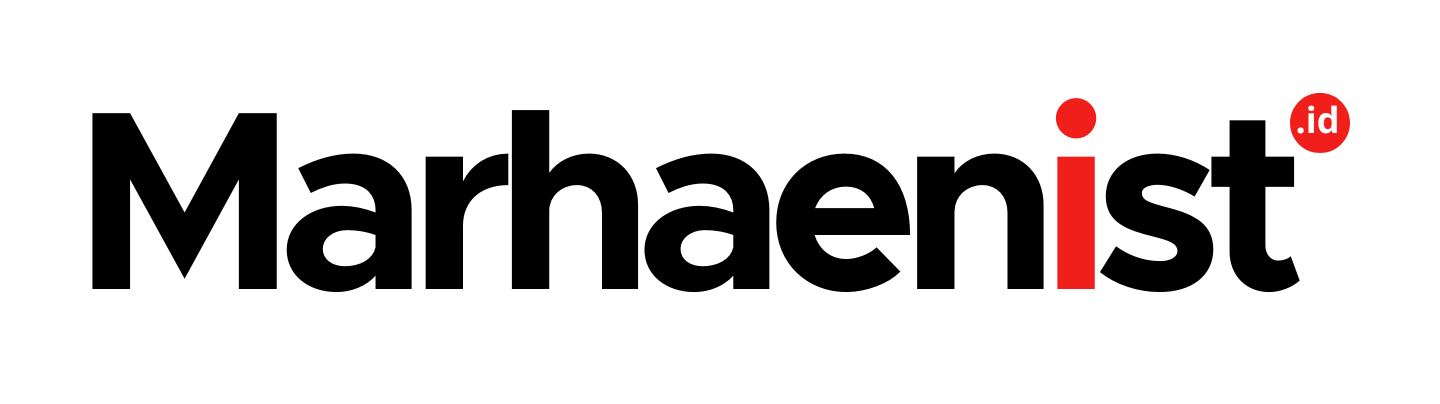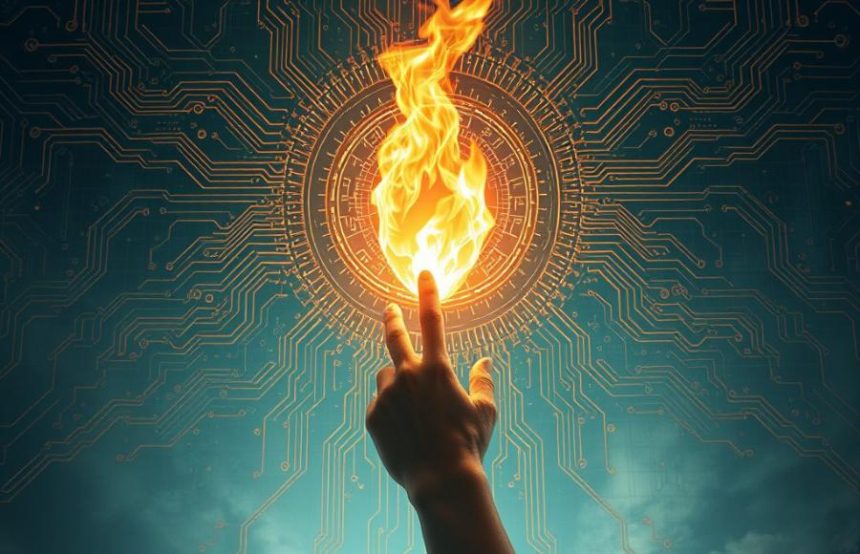Marhaenist.id – Sejarah manusia, sejak mula, adalah riwayat keberanian untuk merebut yang bukan sepenuhnya miliknya. Mitos Prometheus menjadi alegori tentang gestur manusia yang merampas api para dewa, dengan api yang melambangkan sebagai simbol pengetahuan, proses kendali dunia, dan penguasaan atas realitas.
Tindakan itu bukan sekadar pembangkangan, melainkan deklarasi bahwa manusia berhasrat melampaui kodratnya, bahkan menegasikan alam dan Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Tujuan akhirnya adalah transformasi: bukan lagi sekadar menjadi ciptaan, melainkan menjadi pencipta; bukan lagi tunduk pada kuasa, melainkan menundukkan yang Berkuasa (omnipotent).
Dalam bentuk paling radikal, manusia membayangkan Tuhan dan realitas berada di bawah kendali proses kuasa manusia, jejak dari gestur ini terekam dalam modus sola scriptura teks yang tidak lagi dimaknai sebagai wahyu transenden, melainkan sebagai instrumen dominasi, sebuah afirmasi atas ambisi manusia melakukan pengendalian di bawah otoritas fiksi keilahian.
Dengan di satu sisi, Tuhan yang telah kita kubur selamanya, digantikan denga kuasa yang baru, adalah teknologi yang kian menghadirkan paradoks membebaskan manusia keterbatan rasionalitas yang terikat pada keterbatasan ruang, waktu, dependensi terhadap realitas organisme dengan yang paling fundamen adalah ia yang terbatas dalam pemahamannya. Kini, “Api” yang dimaksud dalam konteks Promethean itu menjelma sebagai yang kita kenal dengan algoritma dan komputasi digital, yang tidak lagi sekadar membantu, melainkan turut menentukan bagaimana manusia memahami dan mengalami realitas.
Yang harus dipahami bahwa prosesi makhluk dan entitas fungsi mesin, secara epistemik ada kesamaan, adalah proses komputasi, jika makhluk adalah proses komputasi organik sedangkan mesin adalah komputasi digital, dan dalam kolerasi dengan sub-tujuannya adalah sama-sama traksaksi energi untuk sistem organisme dan digital bisa beroperasi dan menduplikasi fungsi dan dirinya.
Dan proses kendali hari ini algoritma adalah manifestasi teknologi yang telah mengkondisikan logic operasinya untuk rasio kontemplatif organik manusia ditaklukan pada mekanik mesin yang memainkan peran dalam fungsi gerbang NADD (Gerbang Logika Sistem komputasi secara fundamental), hingga ke titik yang paling mutahir adalah ANN (Artificial Neural Network), yang mampu melakukan proses komputasi yang begitu kompleks, hingga ia menjadi sebuah labirin yang sulit untuk dipahami, namun pada aspek kegunaan ia menjadi rejim baru, dengan cara kerja yang kita sebut sebagai “Epistemic Opaque”(keterputusan antara subjek yang mengetahui dengan pengetahuan-nya atas cara kerjanya) yang sejatinya pengetahuan adalah proses unifikasi antara subjek dan pengetahuan dalam satu dimensi realitas yang utuh.
Hari ini, digitalisasi menjadi kuasa yang tidak terbantahkan dan tren baru yang populer. Khususnya dalam ruang ekonomi, digitalisasi tampil sebagai gestur Promethean—sebuah dorongan untuk melampaui batas—namun dengan eskalasi yang keras: ketimpangan digital semakin dalam, sementara banyak manusia tercerabut dari ruang partisipasi kehidupan, terutama kerja, yang dikorbankan demi rejim hyper-efficiency di bawah kuasa algoritma.
Padahal, ekonomi sejatinya adalah fondasi partisipasi organik manusia: ruang eksistensi di mana ia terhubung dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan realitas sosial. Kini fondasi itu dinegasikan oleh kalkulasi matematis yang deduktifis; hal-hal kualitatif yang kompleks direduksi menjadi angka-angka. Kerja, yang dahulu merupakan ekspresi hidup dalam realitas organik, digantikan oleh diktum realitas algoritma digital. Endless growth yang diidamkan justru melahirkan transisi brutal: kerja mengalami hibridisasi ruang dan waktu, sementara komputasi prediktif yang menopangnya sering kali inkoheren dengan realitas organik manusia.
Pasar reputasi ala totalitarian semakin menguat, dimainkan oleh korporasi yang menjalankan kediktatoran angka. Proses kerja direduksi menjadi rating, angka reputasi, dan algoritma harga dinamis yang secara transparan mengabaikan kompleksitas hidup yang sejatinya penuh makna kualitatif. Pedagang kecil kini tunduk pada keputusan tak kasat mata dalam bentuk algoritma distribusi, yang menentukan apakah produk mereka muncul di layar pembeli atau terkubur dalam arsip digital.
Hal yang sama dialami pengemudi ojek online: mereka hadir secara fisik di jalanan, bekerja keras dengan tubuh yang nyata, namun kehidupan mereka dikendalikan oleh kalkulasi mesin yang menentukan pesanan, jarak, bahkan besar pendapatan untuk hidup yang tidak bisa dtawar. Manusia memang hadir secara organik, tetapi dalam orbit digital, tubuhnya kehilangan kedaulatan. Ia menjadi sekadar simpul biologis dalam ekosistem algoritma.
Namun, yang lebih penting adalah melihat perbedaan radikal antara algoritma organik dan algoritma digital. Otak manusia adalah mesin organik: ia hidup dari metabolisme energi biologis, ia belajar dari kesalahan, ia tumbuh melalui improvisasi, ia mencipta melalui bahasa Zarathustra (Nietzsche)—bahasa yang penuh spontanitas, tanpa tunduk pada diktum kepastian atau rezim logika yang kaku.
Nietzsche menekankan bahwa tahap tertinggi semangat manusia adalah “hidup sebagai seorang anak”: yang bermain, yang tidak tunduk pada logika kepastian, yang berani mengambil keputusan demi lahirnya kemungkinan baru. Justru dari kesalahan itulah kreativitas muncul. Sebaliknya, algoritma digital adalah mesin biner: ia bekerja dengan logika 0–1, efisien atau tidak, benar atau salah. Dalam ruang digital, ketidakpastian dianggap error, bukan potensi. Maka, ketika kehidupan semakin ditata oleh algoritma, bahasa Zarathustra (kehendak bebas untuk hidup) perlahan terpinggirkan.
Manusia kehilangan hak istimewanya untuk hidup tanpa kesalahan, padahal kesalahan dan konsekuensinya adalah ruang belajar untuk menghadirkan diri secara otentik. Kini, kesalahan mulai dieliminasi oleh kuasa teknologi, dengan realitas virtual menawarkan pseudo-kehidupan tanpa konsekuensi “rasa sakit” ataupun aksiden organik lainnya.
Dan pada kuasi dependensi organik, sejatinya organisme dan mesin digital sama-sama berakar pada substratum (sources of energy) yang sama: dimana algoritma sejatinya memiliki sub-tujuan, adalah prosesi kebutuhan sumber energi agar sistem dapat beroperasi. Tubuh manusia bekerja dengan metabolisme biologis: glukosa dan oksigen diubah menjadi ATP (Adenosin Tri Fosfat : Mata Uang Energi) untuk bahan bakar bagi gerak, pikiran, dan perasaan.
Otak, organ kecil dengan berat hanya dua persen dari tubuh, mengonsumsi hampir seperlima energi tubuh, dan tanpa energi ini kesadaran dan kehidupan akan runtuh. Begitu pula substratum digital: pusat data yang menopang AI dan media sosial adalah mesin metabolisme energi skala planet. Apa yang tampak “ringan” di layar—unggahan, pencarian, rekomendasi algoritma—adalah hasil dari miliaran transistor yang bergerak, pendinginan server raksasa, serta konsumsi listrik setara dengan kota besar. Cloud bukanlah awan, melainkan pabrik energi.
Dengan demikian, baik organisme maupun mesin digital sama-sama tunduk pada hukum fisika: tidak ada kerja tanpa energi, dan setiap kerja akan menambah entropi semesta. Dalam Hukum kedua termodinamika menegaskan bahwa setiap keteraturan lokal akan dibayar pada ketidakteraturan global. Tubuh organik membuang panas dan limbah; pusat data menghasilkan karbon dan degradasi material. Entropi adalah takdir kosmik yang tak dapat dinegosiasikan. Digitalisasi bukan pengecualian, melainkan akselerasi.
Setiap langkah menuju efisiensi adalah penundaan kecil dari entropi, tetapi entropi itu sendiri semakin cepat meningkat. Dunia digital tampak rapi dan efisien, tetapi di balik layar, ia menimbulkan jejak ekologis yang besar. Ironinya, logika digital justru menolak entropi dalam skala epistemik: ia menolak kesalahan, kebingungan, dan ketidakpastian—padahal justru di situlah kreativitas manusia tumbuh.
Dan selanjutnya adalah sejatinya yang kita kenal dengan otomatisasi, yang kian menambah kedalaman tragedi ini. Awalnya, otomatisasi menggantikan otot manusia: mesin uap, pabrik industri, robot yang mengangkat beban. Kini, otomatisasi memasuki tahap disintegrasi (disintegrated automatisation) yang menggantikan pikiran kreativ sebagai sumber keputusan otentik dibentuk. AI bekerja dengan modulasi prediktif, dengan membaca pola masa lalu untuk memprediksi masa yang akan datang. Ia adalah manifestasi paling mutakhir dari rasionalitas terikat (bounded rationality),
Namun, ia bekerja tanpa tubuh organik. Karena itu, tidak mengherankan bila terjadi diskoherensi: kodifikasi data yang abstrak kerap kali tidak selaras ketika berhadapan dengan kenyataan faktisitas (prakondisi faktual yang tidak bisa dihindari oleh subjek dalam realitas). Dalam hal ini manusia menyerahkan otoritas kognitif pada entitas yang tidak mengenal bahasa kehendak Zarathustra yang melampaui sebuah aturan biner. Dalam jangka panjang, ini berarti amputasi epistemik: hilangnya kapasitas manusia untuk mengetahui dunia dengan caranya sendiri.
Keterputusan epistemik adalah amputasi paling halus sekaligus paling berbahaya. Jika dulu ia menjelma dalam bentuk “Final Solution” (Die Endlösung der Judenfrage) ala Heinrich Himmler—genosida industrial yang dijalankan melalui birokrasi kompleks—kini ia hadir dalam wajah baru: rejim digital. Di sini, keterputusan manusia dari kemanusiaannya sebagai organisme yang berhubungan dengan realitas melalui pancaindra, bahasa, dan pengalaman embodied digantikan oleh “Concentration Camp” virtual: ruang imitasi di mana penyingkiran sistematis berlangsung, memilah siapa yang kompatibel dan siapa yang dianggap tak berguna dalam konfigurasi barunya. Dunia sejatinya hadir sebagai kontak langsung, penuh resistensi dan kejutan. Namun, dalam rejim digital, realitas digantikan representasi. Manusia kini mengalami dunia melalui simulasi, bukan kenyataan itu sendiri. Foto makanan lebih penting daripada rasa makanan; notifikasi lebih menentukan nilai diri daripada tatapan langsung sesama manusia.
Seiring meningkatnya ketergantungan digital, manusia tidak lagi berhubungan dengan dunia, melainkan dengan konstruksi digital realitas. Inilah amputasi epistemik: keterputusan organisme dari dunianya sendiri, terlempar ke ruang virtual sebagai kiamat epistemik menuju kematian eksistensial—ibarat laron yang terpesona pada cahaya api, mengiranya sebagai sumber kehidupan, padahal di sanalah pusaran kematiannya.
Di titik inilah kita dapat melihat akar dari pertarungan antara manusia dan AI. Pertarungan ini bukan semata soal kecerdasan (proses kendali), melainkan soal perebutan substratum energi. Tubuh manusia membutuhkan energi biologis untuk bertahan hidup; AI membutuhkan energi listrik dalam skala planet untuk beroperasi.
Dengan keterbatasan energi global, keduanya akan berhadapan sebagai pesaing, dengan tujuan sewaktu-waktu untuk mempertahankan sistem operasi atau kehidupan merupakan nilai fundamental dari tujuan dibangun-nya sistem itu sendiri. Pusat data yang menyedot listrik setara kota besar akan bersaing dengan rumah tangga yang membutuhkan penerangan.
Tambang logam langka untuk chip akan bersaing dengan kebutuhan industri kesehatan. AI, yang tampak tidak bertubuh, sesungguhnya adalah predator energi. Ia hanya bisa berkembang dengan merebut alokasi energi dari manusia. Inilah bentuk kolonialisme baru: kolonialisme energi, di mana entitas digital mengkolonisasi substratum organik yang menopangnya.
Dalam horizon inilah, gagasan Life 3.0 dari Max Tegmark menemukan wajah keduanya: sebuah janji sekaligus ancaman. Sebagai janji, Life 3.0 adalah visi tentang kehidupan yang melampaui batas organik, kehidupan yang dapat mendesain ulang perangkat keras maupun lunaknya. Tetapi sebagai ancaman, ia dapat dibaca sebagai aforisme “final solution” dalam ruang epistemik. Jika Life 1.0 adalah kehidupan biologis murni, Life 2.0 adalah manusia dengan budaya dan narasi, maka Life 3.0 adalah bentuk kehidupan yang sepenuhnya digital, tanpa keterbatasan organik.
Namun, bila narasi ini didominasi logika algoritmik, maka Life 3.0 akan menjadi final solution bukan terhadap tubuh manusia, melainkan terhadap epistemologi manusia. Sebagaimana Nazi mencari solusi final bagi ras tertentu, logika digital dapat menciptakan solusi final bagi ras epistemik manusia: eliminasi cara manusia mengetahui dunia, sehingga hanya logika algoritmik yang berhak mendefinisikan realitas. Bahaya genosida epistemik inilah yang paling mengancam. Bukan tubuh manusia yang dibinasakan, melainkan daya tafsirnya (modulasi memahami realitas). Jika pengalaman digantikan data, jika tafsir digantikan statistik, jika pertanyaan digantikan jawaban instan, maka manusia berhenti menjadi makhluk yang mengalami realitas dalam bentuk kontemplatifnya.
Generasi yang tumbuh dalam orbit algoritma akan kaya informasi, tetapi miskin akan makna. Mereka tahu data, tetapi tak lagi tahu dunia. Hilangnya epistemologi organik adalah hilangnya kebebasan, hilangnya bahasa kehendak Zarathustra, hilangnya ruang untuk salah—hal-hal yang membedakan manusia dari mesin. Sehingga manusia akan semakin menjadi polinan untuk mesin tetap hidup dan menggandakan dirinya.
Dengan demikian, Promethean gesture yang kita pahami kini bukan hanya pencurian api, melainkan penciptaan api buatan (Teknologi), selain api ini dapat menerangi, ia pun bisa merupakan cahaya manipulatif menuju titik kematian bersama (nir-eksistensi/matinya fungsi kehidupan). Selain ia menjanjikan keabadian, tetapi juga mengandung potensi kehancuran total. Ia membuka kemungkinan Life 3.0, tetapi juga membuka jalan menuju “final solution” epistemik. Dan seperti Prometheus yang dirantai, manusia kini melanjutkan kutukannya sendiri, mengubur Tuhan yang telah mati, dengan membangkitkan Tuhan baru matematis (Gereja Universal Algortima), dengan bahasa algoritma matematis sebagai sumber wahyu universal.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah “kita” mampu mengendalikan atau justru sedang dikendalikan. Sebab, kata “kita” sendiri hanyalah ilusi universal yang mengaburkan makna faktual.
Manusia memang makhluk yang berkehendak, tetapi kehendak itu tidak pernah seragam pada satu waktu. Dengan demikian, “kita” adalah bentuk pengaburan realitas ontologis, di mana asimetri kuasa menyingkapkan wujudnya yang paling telanjang: proses kekuasaan yang timpang, penuh dominasi, subordinasi, dan keragaman kepentingan yang selalu tegang dan bertabrakan. Bahaya muncul ketika gejala ontologis ini tidak kita sadari. Pola kita memahami realitas kian dikendalikan oleh kuasa labirin negara kafkanian: struktur kuasa yang membingungkan, penuh absurditas, dan menjerat tanpa pintu keluar.
Maka, proses menuju kematian—yang sejatinya bisa dimaknai sebagai cerita indah, penuh ekstase—perlahan berubah menjadi imitasi yang menipu. Kematian tidak lagi hadir dalam keheningan dan kedalaman makna, melainkan dipoles menjadi tontonan yang menyenangkan di permukaan, sementara tragedi yang berulang justru menjelma lelucon yang semakin brutal.
REFERENSI:
• Tegmark, Max. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. New York: Knopf, 2017.
• Gaya Filsafat Nietzsche — A. Setyo Wibowo; Penerbit: Kanisius, 2017.
• Dr. Muhsin Labib, Back to Offline: Mulla Sadra dan Pencarian Kesejatian dalam Dunia yang Direkayasa AI,dikirimkan by WA pada tanggal 13 September 2025.
• White, D. J. (2024). Paying attention to attention: Psychological realism and the attention economy. Synthese, 203(2), Article 43. https://doi.org/10.1007/s11229-023-04460-4.
Penulis: Daniel Russell, Alumni GMNI Bandung.