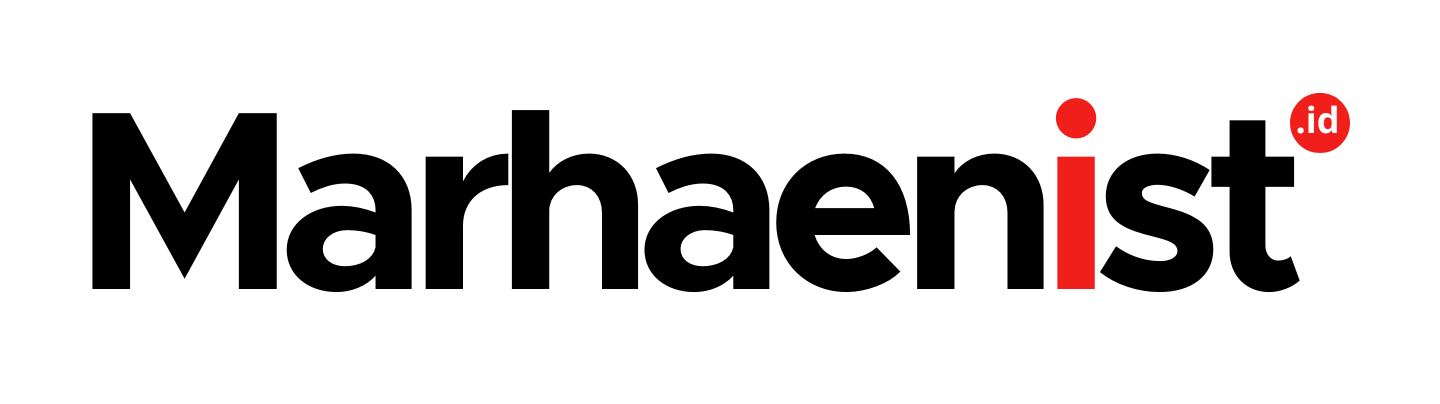Marhaenist.id – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang beberapa waktu belakangan ini muncul kembali secara masif tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, dalam artian wacana ini harus dilihat sebagai pertarungan memori, narasi, dan yang paling mendasar, sebuah bentrokan ideologis tentang makna sejati dari apa itu kepahlawanan Indonesia. dengan dalih stabilitas politik dan pertumbuhan ekonom dan “Pembangunan” yang dicapai selama tiga dekade, beberapa pihak mendukung wacana ini. namun, bagi seseorang yang mengaku dirinya marhaenis–mereka yang mengamalkan marhaenisme yang merupakan ideologi yang digali Soekarno dari kenyataan pahit kehidupan rakyat jelata, si Marhaen. Penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini adalah sebuah keharusan sebuah imperatif ideologis yang tidak bisa ditawar.
Menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya mengaburkan sejarah, melainkan pengkhianatan langsung terhadap jiwa dan semangat api perjuangan Marhaenisme itu sendiri. Orde baru merupakan bentuk nyata pengingkaran terhadap penderitaan jutaan Marhaen yang justru menjadi korban dari mesin negara represi yang dibangunnya. Untuk memahami penolakan ini, kita harus menyelami kedalaman dosa-dosa rezim Orde Baru dan membandingkannya dengan fundamen etis Marhaenisme, yang berdiri di atas tiga pilar: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan.
Secara nyata tentu kita memahami bahwa marhaenisme itu adalah keberpihakan, Marhaenisme, dalam visi Soekarno, adalah antitesis dari penindasan baik oleh kapitalisme, imperialisme, maupun feodalisme. Ia lahir dari perjumpaan dengan seorang petani miskin bernama Marhaen, yang mewakili realitas mayoritas bangsa Indonesia: rakyat kecil yang memiliki alat produksi sederhana namun hidup dalam belenggu kemiskinan struktural. sehingga marhaenisme dapat diartikan sebagai sosialisme ala Indonesia yang bertujuan membebaskan si Marhaen: petani kecil, buruh, pedagang kecil, nelayan dari segala bentuk eksploitasi, baik oleh kaum imperialis internasional, kapitalisme dalam negeri, maupun sisa-sisa feodalisme. Cita-citanya adalah terwujudnya masyarakat sosialisme Indonesia yang didalamnya;berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Dengan fondasi ini, setiap kebijakan dan tindakan penguasa harus diukur dari satu parameter utama: apakah ia memuliakan atau meminggirkan Marhaen? Melalui lensa inilah rezim orde baru Soeharto harus dinilai, dan hasilnya adalah sebuah catatan kelam yang penuh dengan pengkhianatan.
Dosa pertama dan paling mendasar Soeharto adalah pembunuhan terhadap sosio-demokrasi, baik dalam politik maupun ekonomi. Demokrasi pada masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diubah menjadi ritual formalitas yang menutupi dominasi Golkar dan militer, sementara kebebasan berserikat dan berpikir dibungkam atas nama stabilitas nasional. Rakyat kecil, kaum Marhaen yang seharusnya menjadi subjek politik, justru disingkirkan dari ruang partisipasi. Negara kehilangan peran sebagai alat pembebasan, berubah menjadi instrumen dominasi yang memastikan rakyat tetap tunduk dan terpinggirkan.
Namun pembunuhan sosio-demokrasi yang paling nyata terjadi di bidang ekonomi. Orde Baru membangun sistem kapitalisme kroni, di mana akumulasi kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang bersekongkol dengan birokrasi dan militer. Ekonomi rakyat disingkirkan, tanah dirampas, dan buruh dijadikan alat produksi murah bagi kepentingan modal besar. Ironisnya, warisan kapitalisme kroni ini terus hidup hingga kini, tampak jelas dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi yang memperkuat oligarki dan menormalisasi ketimpangan struktural melalui proyek-proyek infrastruktur yang berpihak pada korporasi besar. Pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan semangat yang sama, dengan retorika pembangunan yang mengulang logika lama: pertumbuhan ekonomi di atas penderitaan rakyat kecil. Dalam konteks ini, Soeharto bukan sekadar sosok masa lalu, melainkan simbol dari kontinuitas pengkhianatan terhadap cita-cita sosio-demokrasi yang memuliakan Marhaen.
Pengkhianatan Soeharto terhadap sosio-nasionalisme tidak hanya terjadi karena keterbukaannya terhadap modal asing, tetapi karena ia mengubah makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme yang dirumuskan Soekarno adalah nasionalisme yang hidup dan membebaskan, yang menempatkan rakyat sebagai subjek sejarah dan menolak segala bentuk penjajahan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam visi itu, kebangsaan berarti solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Namun di tangan Soeharto, nasionalisme direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan dan retorika pembangunan yang menutupi ketimpangan. Ia menukar semangat perjuangan menjadi kepatuhan terhadap negara yang diklaim sebagai satu-satunya penjaga stabilitas.
Dalam sistem Orde Baru, negara dijadikan pusat kendali yang menundukkan segala bentuk kemandirian rakyat di bawah dalih persatuan dan pembangunan. Sosio-nasionalisme yang seharusnya tumbuh dari solidaritas antar kelas dan antardaerah diubah menjadi nasionalisme administratif yang sentralistis dan militeristik.
Pembangunan dijalankan bukan sebagai upaya membangkitkan potensi bangsa dari bawah, tetapi sebagai proyek top-down yang menggiring ekonomi nasional bergantung pada utang luar negeri, bantuan teknokrat asing, dan investasi korporasi besar. Produksi nasional tidak diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk akumulasi modal oleh segelintir elite yang bersekongkol dengan negara.
Dengan demikian, pengkhianatan Soeharto terhadap sosio-nasionalisme adalah perampasan makna kebangsaan itu sendiri. Nasionalisme rakyat yang seharusnya menjadi alat emansipasi berubah menjadi nasionalisme semu yang memaksa rakyat tunduk atas nama pembangunan. Negara digunakan untuk menegakkan kapitalisme kroni, di mana kekayaan nasional diprivatisasi untuk kepentingan keluarga penguasa dan kroni ekonomi. Dalam sistem semacam ini, semangat kebangsaan kehilangan jiwa sosialnya dan berubah menjadi ideologi pengendalian. Sosio-nasionalisme yang mestinya menjadi dasar persatuan nasional menuju keadilan sosial justru dibunuh dalam sunyi oleh negara.
Dosa-dosa struktural rezim Soeharto diperparah oleh jejak kekerasan dan represi yang menghitam dalam sejarah bangsa. Tragedi 1965–1966 menjadi luka kolektif yang paling dalam dan paling menentukan arah kekuasaan Orde Baru. Pembantaian terhadap ratusan ribu hingga jutaan rakyat yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan hanya menghapus nyawa manusia, tetapi juga membunuh nalar kritis bangsa. Korban terbesarnya adalah kaum Marhaen: petani, buruh, seniman, guru, dan rakyat kecil yang sering kali tidak tahu-menahu tentang ideologi, tetapi terseret oleh tuduhan sepihak dan kebencian yang direkayasa. Mereka dibantai, dipenjara tanpa pengadilan, dan dicap sebagai “tapol” yang kehilangan hak-hak sipil dan politik selama puluhan tahun. Inilah kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern, yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara, dan menjadi fondasi kekuasaan Orde Baru. Dari tragedi itu lahir negara yang dibangun di atas ketakutan, di mana kekerasan dijadikan dasar stabilitas.
Namun kekerasan itu tidak berhenti di awal kekuasaan. Ia menjadi pola berulang. Tahun 1974, demonstrasi mahasiswa yang menolak dominasi modal asing dan kronisme kekuasaan berujung dalam tragedi Malari, di mana negara menanggapinya dengan represi brutal. Pada dekade 1980-an, penembakan misterius (Petrus) menewaskan ribuan warga tanpa proses hukum, menanamkan rasa takut kolektif yang menembus ruang privat rakyat kecil. Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989 menunjukkan wajah negara yang tak segan membunuh rakyatnya sendiri atas nama ketertiban. Di Timor Leste, Aceh, dan Papua, ribuan orang menjadi korban operasi militer yang diselimuti dalih nasionalisme dan keamanan negara. Menjelang kejatuhannya, peluru kembali dilepaskan ke dada mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan II, serta aksi-aksi yang menuntut reformasi 1998. Sebelum itu, ratusan aktivis pro-demokrasi diculik, disiksa, dan beberapa dari mereka tidak pernah kembali.
Semua itu tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem politik yang sengaja dibuat tertutup dan otoriter. Melalui Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), Soeharto mematikan ruang politik di universitas, menjadikan kampus sebagai institusi steril dari perdebatan ideologis dan perjuangan rakyat. Pers dibungkam lewat pencabutan SIUPP, partai politik direduksi menjadi tiga, dan seluruh organisasi sosial dipaksa tunduk pada satu ideologi tunggal yang disahkan negara. Ruang publik berubah menjadi panggung monolog kekuasaan. Di tengah itu semua, rakyat didorong untuk diam karena diam berarti aman.
Dosa Soeharto selanjutnya adalah bagaimana ia memutarbalikkan Pancasila dan mengkhianati konstitusi UUD 1945. Pancasila, yang seharusnya menjadi jiwa konstitusi dan landasan moral bagi kedaulatan rakyat, justru dijadikan alat legitimasi kekuasaan tunggal. Melalui indoktrinasi P4 dan asas tunggal, negara mengambil alih hak rakyat untuk menafsirkan nilai-nilai konstitusional. Pancasila yang hidup dan membebaskan diubah menjadi dogma mati yang mengajarkan kepatuhan buta. Tujuan utamanya bukan membangun karakter bangsa, melainkan mencetak rakyat yang patuh, birokrat yang setia, dan intelektual yang jinak. Dengan cara itu, rezim membangun sistem kepatuhan massal yang mematikan daya kritis, menjadikan kebenaran hanya milik penguasa. Ini bukan sekadar pelanggaran moral atau ideologis, melainkan pengkhianatan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Pengkhianatan itu juga merembes dalam bentuk pengaburan sejarah. Buku-buku pelajaran disusun untuk menghapus suara korban dan menyanjung satu nama. Generasi pasca-1965 diajarkan untuk melihat sejarah bukan sebagai dialektika rakyat, tetapi sebagai narasi tunggal kekuasaan. Ditambah satu generasi intelektual yang dikirim oleh Soekarno ke berbagai universitas di luar negeri dibuang atau dipaksa hidup di pengasingan para eksil 1965 dihapus dari ingatan nasional, seolah-olah mereka tidak pernah menjadi bagian dari bangsa. Semua ini adalah proyek besar pemandulan kesadaran: menjauhkan rakyat dari sejarahnya sendiri, agar mereka tidak lagi memiliki dasar untuk melawan.
Dan dosa itu masih bergaung hingga hari ini. Politik dinasti, kooptasi simbol nasionalisme, dan pembungkaman suara kritis atas nama “persatuan” menunjukkan bahwa warisan Orde Baru belum benar-benar mati. Di bawah Jokowi, dan kini berlanjut di bawah Prabowo-Gibran, semangat yang sama mengemuka kembali: sentralisasi kekuasaan, militerisasi politik, dan kapitalisme kroni yang menempatkan negara sebagai alat patronase bagi segelintir elite. Rakyat dijadikan objek pembangunan, bukan subjek yang berdaulat. Pancasila kembali diperlakukan sebagai jargon kosong untuk menutupi kesenjangan, sementara UUD 1945 terus ditafsirkan sepihak demi melanggengkan kekuasaan. Bila kita tidak sigap membaca tanda-tandanya, maka pengkhianatan terhadap konstitusi akan kembali terjadi dalam wajah yang lebih modern, lebih rapi, dan lebih berbahaya.
Oleh karena itu, ketika wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto muncul, kita tidak sedang menilai satu individu, melainkan seluruh warisan pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu sama dengan menyatakan bahwa membunuh rakyat, membungkam nalar, dan memanipulasi Pancasila adalah hal yang bisa dimaafkan demi “pembangunan.”
Bagi seorang Marhaenis, ini adalah racun nyata bagi jiwa bangsa. Pahlawan sejati adalah mereka yang mempertahankan kedaulatan rakyat dan kemanusiaan: para petani yang melawan perampasan tanah, buruh yang menuntut upah adil, dan aktivis yang hilang karena menyuarakan kebenaran. Soeharto bukan pahlawan mereka; ia adalah simbol dari apa yang mereka lawan.
Menolak gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini bukan sekadar menolak nama, tetapi menolak amnesia. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap upaya menghapus jejak kejahatan negara dari ingatan kolektif bangsa. Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang melupakan penderitaan rakyatnya demi mitos stabilitas. Bagi kaum Marhaenis, penolakan ini adalah bentuk kesetiaan pada janji kemerdekaan: bahwa republik ini didirikan untuk membebaskan manusia, bukan menaklukkannya. Atas nama mereka yang dibunuh, yang dibungkam, yang diasingkan, dan yang terus berjuang agar kebenaran tidak terkubur, kita harus bersikap tegas dan tanpa ragu: Soeharto bukan pahlawan !!!***
Penulis: Deodatus Sunda Se, Direktur Institut Marhaenisme 27.