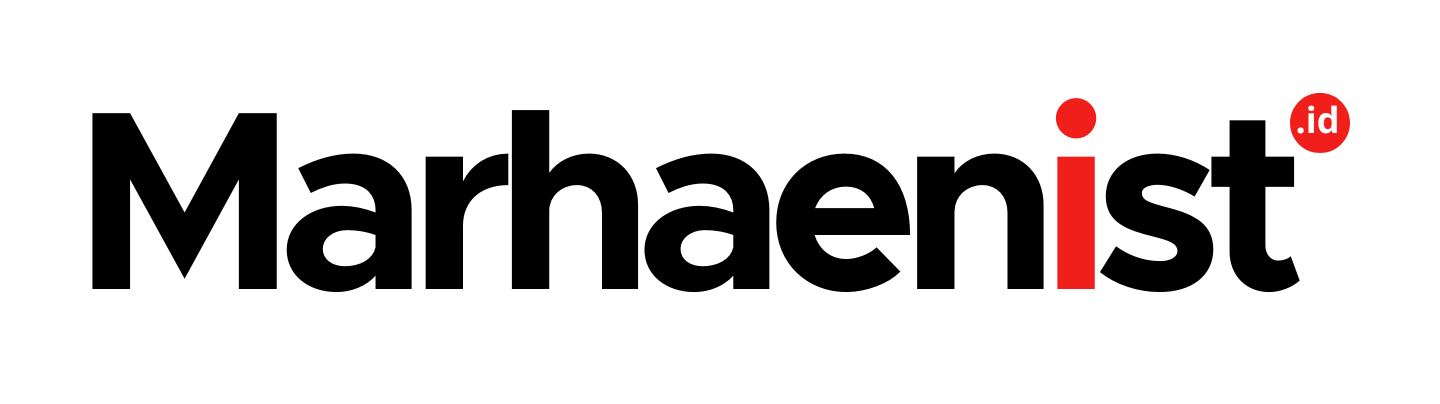Marhaenist.id – (Pendahuluan) Hidup di Tengah Kelelahan Kolektif: Kita hidup dalam zaman yang mendambakan kecepatan tanpa batas, melampaui limitasi biologis manusia. Batas antara “bekerja” dan “beristirahat” kian kabur: jam kerja merambah waktu pribadi, sementara ruang batin pun digerogoti oleh tuntutan produktivitas tanpa henti. Media sosial, ruang kerja digital, bahkan percakapan sehari-hari menjadi arena di mana kita terdorong untuk “menjadi lebih”, “mencapai lebih banyak”, dan “tidak ketinggalan apa pun”.
Filsuf Korea-Jerman, Byung-Chul Han, dalam karyanya The Burnout Society (2010/2015), menyebut fenomena ini sebagai tanda lahirnya masyakarakat kelelahan. Berbeda dengan masyarakat disipliner ala Michel Foucault—yang dikontrol melalui represi eksternal—masyarakat hari ini justru mendorong dirinya sendiri untuk bekerja tanpa batas, bahkan hingga titik auto-eksploitasi.
Artikel ini akan membahas pergeseran dari masyarakat disipliner menuju masyarakat pasca-disipliner atau Achievement Society, menjelaskan konsekuensi patologisnya, dan menyingkap bagaimana “kebebasan semu” justru menjadi rezim baru yang memperbudak subjek dari dalam dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kita akan melihat kemungkinan bentuk perlawanan melalui penciptaan jeda, ruang kontemplasi, dan keberanian untuk menolak logika produktivitas yang tanpa henti.
Dari Masyarakat Disipliner ke Masyarakat Pasca-Disipliner
Michel Foucault menjelaskan bahwa masyarakat modern (disipliner) dibangun dengan batasan tegas (Otoritas dan ancaman dapat teridentifikasi). Ada yang benar dan salah, normal dan abnormal, patuh dan melanggar. Otoritas nilai dipegang pada kuasa institusi yang solid : negara, agama, hukum, dan sains. Dengan kata lain kehidupan dijalankan dalam ruang dan waktu yang kaku: jam kerja, ruang sekolah, prosedur hukum telah terbangun pada prinsip fundamental yang tegas atas kemewaktuannya, sebelumnya sistem (kuasa-nya) beroperasi.
Namun, memasuki era digital, pasca-pandemi, dan postmodern, batas-batas itu mulai melebur dalam ketidakpastiannya. Realitas menjadi cair—sejalan dengan gagasan liquid society– (Eric Butler : Penerjemah Byung-Chul Han). Benar dan salah kini bergantung pada konteks dan narasi. Ruang dan waktu menjadi fleksibel (Hibridasi ruang dan wakti) yang secara kontemporer dipraksiskan dengan istilah “kerja jarak jauh“, “pertemuan virtual“, hingga “kehadiran di ruang digital“. Disamping fakta dan opini bercampur dalam arus post-truth, di mana otoritas kebenaran tidak lagi tunggal.
Dalam kondisi ini, individu merasa memiliki kebebasan tanpa batas. Namun justru di situlah jebakan tersembunyi: kebebasan berubah menjadi tekanan baru yang memaksa kita untuk selalu aktif, selalu terhubung, dan selalu produktif. Artinya kekuasaan telah merubah mekanisme kerjanya, dengan sebelumnya ia adalah hasil produksi atas kuasa diluar tubuh subjek, namun hari ini ia bekerja dalam level imanensi di luar bacaan potensi “bahaya”.
Patologi Positivitas: “Yes Man Society” Menjadi Sumber Penyakit
Dalam masyarakat disipliner, ancaman selalu datang dari luar—entah berupa bakteri, virus, maupun represi politik. Sebaliknya, dalam masyarakat kontemporer, ancaman justru lahir dari dalam: dari eksesivitas positivitas, ketika subjek memanipulasi dan memaksakan aktualisasi ide tanpa saringan rasional yang memadai.
Han menekankan bahwa penyakit kontemporer bersifat imunologis, bukan bakteriologis. Artinya, bukan lagi dimaknai sebagai ancaman “musuh dari luar” yang menyerang tubuh, melainkan tubuh (atau pikiran) itu sendiri yang melakukan auto-agresi . Seperti penyakit autoimunitas, di mana sistem kekebalan justru menyerang jaringan tubuh sendiri, masyarakat burnout mendorong individu untuk terus mengeksploitasi diri sampai melewati batas biologisnya.
Kita melihat gejala ini dalam kehidupan sehari-hari: orang yang tak mampu berhenti bekerja meski lelah, mahasiswa yang selalu merasa kurang meski prestasinya tinggi, atau konten kreator yang setiap hari harus memproduksi karya baru agar tidak dilupakan oleh algoritma. Semua ini bukanlah represi dari luar, melainkan dorongan internal untuk selalu berkata “ya” pada setiap hal di luar kapasitas biologis manusia.
Paradoks Kebebasan: Dari Ruang Kontemplasi ke Eksploitasi Diri
Di permukaan, kita merasa hidup dalam kebebasan tanpa batas. Namun, Byung-Chul Han menyebut kebebasan ini sebagai kebebasan paradoksal. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar pula tekanan yang lahir dari kewajiban untuk selalu memilih dengan tepat. Alih-alih menjadi ruang jeda yang memungkinkan subjek untuk merenung dan berefleksi, kebebasan justru berubah menjadi rezim baru yang menuntut eksploitasi diri secara total dalam ranah praksis. Jika dalam masyarakat disipliner kita dikurung oleh dinding-dinding otoritas, maka dalam masyarakat prestasi kita “terbakar habis” oleh tuntutan untuk mencapai lebih banyak tanpa henti.
Konsekuensi dari logika ini adalah semakin terpinggirkannya vita contemplativa—ruang kontemplasi, perenungan, dan istirahat yang memberi jarak dari banjir stimulus informasi. Hidup hanya dianggap bernilai jika produktif, dapat diukur, dan bisa ditampilkan dalam bentuk kuantifikasi: angka, rating, atau pencapaian. Lebih jauh, waktu istirahat kehilangan makna otentiknya. Ia direduksi menjadi sekadar “strategi pemulihan” agar tubuh dan pikiran siap kembali bekerja—bukan lagi aktivitas bernilai pada dirinya sendiri.
Burnout sebagai Gejala Sistemik, Bukan Sekadar Urusan Personal
Dalam International Classification of Diseases (ICD-11), burnout diakui sebagai sindrom akibat stres kerja kronis, dengan tiga ciri utama:
1. Kehabisan energi,
2. Jarak mental dengan pekerjaan,
3. Penurunan efektivitas profesional.
Namun, Han menegaskan bahwa burnout bukan hanya kondisi medis, melainkan fenomena sistemik. Burnout adalah tanda kegagalan masyarakat dalam merawat dirinya sendiri. Ia bukan sekadar masalah personal yang harus diselesaikan dengan motivasi tambahan, melainkan gejala struktural dari sebuah sistem yang mendorong individu untuk mengorbankan tubuh dan pikirannya demi produktivitas tanpa akhir.
Kekerasan Baru: Dari Represi ke Auto-Imunitas
Di sinilah letak pergeseran besar. Jika dahulu kekerasan muncul sebagai represi eksternal—hukuman, pengawasan, atau kontrol—kini kekerasan hadir dalam bentuk internalisasi. Dorongan produktivitas tanpa henti mendorong individu ke dalam lingkaran setan kelelahan, depresi, ADHD, hingga disfungsi saraf.
Dalam masyarakat ini, kebebasan tidak lagi menjadi kesempatan untuk beristirahat atau merenung, tetapi berubah menjadi proyek tanpa akhir yang dibebani oleh surplus kebebasan itu sendiri. Kebosanan akut, FOMO (fear of missing out), dan siklus konsumsi-kreativitas instan hanyalah gejala dari kekerasan yang halus namun destruktif ini.
Perlawanan: Menghidupkan Kembali Vita Contemplativa
Jika demikian, apa yang bisa dilakukan?
Han menyarankan untuk kembali kepada vita contemplativa—ruang jeda, istirahat, dan perenungan. Idleness (tidak terikat pada gempuran stimulus yang membebani diri sendiri, ex : sosial media) bukanlah penolakan total terhadap aktivitas, melainkan sebuah pemulihan yang memberi jarak dari tuntutan produktivitas.
Dalam praktiknya, perlawanan bisa dimulai dari hal sederhana: berani berkata “tidak”, mengambil jeda dari layar, memberi ruang bagi tubuh untuk beristirahat tanpa merasa bersalah, serta mengembalikan makna hidup pada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.
Perlawanan bukan berarti berhenti bekerja, tetapi menolak reduksi hidup hanya pada kerja. Itu adalah tindakan revolusioner dalam dunia yang mengukur segalanya dengan kuantifikasi.
Penutup: Menolak Terbakar Habis
Masyarakat burnout adalah cermin dari paradoks zaman ini: semakin banyak kebebasan, semakin besar pula beban yang kita pikul. Stres, kelelahan, dan depresi bukan lagi gejala personal, melainkan tanda dari sebuah sistem yang memanipulasi positivitas menjadi paksaan.
Menolak terbakar habis berarti berani mengambil jeda, menemukan kembali ruang kontemplasi, dan merawat diri sebagai subjek manusia yang utuh. Dalam dunia yang semakin cepat dan melelahkan, melambat sejenak bukanlah kelemahan—ia justru bentuk perlawanan paling manusiawi.
Referensi :
• Han, B.-C. (2015). The Burnout Society (E. Butler, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 2010).
• Christophorus Bagas Ompusunggu, 22-Januari-2024, Masyarakat Kontemporer yang Frustrasi, Lelah, dan Cemas: Menelaah Burnout Society dalam Pemikiran Byung-Chul Han, diakses pada tanggal : 09 Agustus 2025. Dari : https://lsfcogito.org/masyarakat-kontemporer-yang-frustrasi-lelah-dan-cemas-menelaah-burnout-society-dalam-pemikiran-byung-chul-han/g.
• Membaca Liquid Society dari perspektif burnout society. Jurnal Media : Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol 6, no 1 Februari 2025, halaman 66-86.
• Seth Mnookin, Making Mental Health a Global Development Priority (Washington, DC: World Bank Group dan World Health Organization, 2016), https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/25279556/making-mental-health-a-global-development-priority.
Penulis: Daniel Russell, Alumni GMNI Bandung.