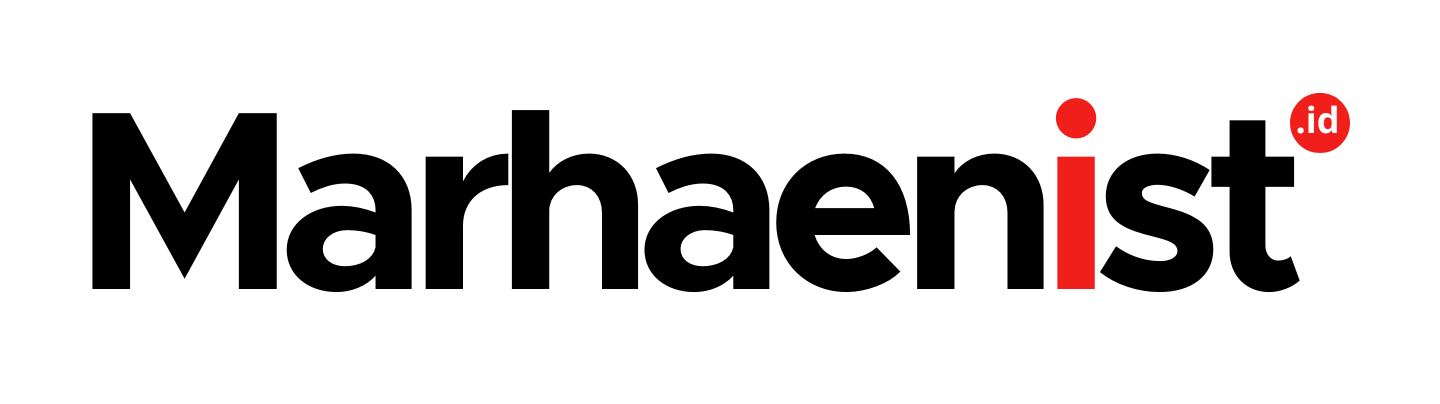Marhaenist.id – (Pengantar) Krisis kesadaran yang muncul di era digital menemukan bentuk konseptualnya dalam apa yang disebut oleh Jonathan Haidt sebagai Diskronitas Eksistensial, yaitu keterputusan antara temporalitas tubuh biologis dan temporalitas digital yang tidak mengenal jeda. Tubuh manusia, yang bekerja dalam ritme biologis dan waktu linear dengan kebutuhan untuk beristirahat, memproses, dan mengendapkan pengalaman dipaksa untuk beroperasi dalam kecepatan ruang digital yang serba instan, simultan, dan tanpa kontinuitas.
Dunia digital menuntut kehadiran permanen dan reaksi segera, sehingga tidak ada lagi ruang bagi keterlambatan, penundaan, atau kontemplasi. Dalam kondisi ini, waktu tidak lagi dialami sebagai aliran yang mengalir secara alami, melainkan sebagai jaringan simultan yang terus menuntut partisipasi.
Hibridasi ruang dan waktu digital bekerja dengan cara menghapus jarak, baik jarak spasial maupun temporal, antara pengalaman dan respons. Segala sesuatu hadir sekarang dan sekaligus: peristiwa di berbagai belahan dunia tampil dalam waktu yang sama, notifikasi datang tanpa ritme, dan kesadaran dipecah ke dalam rentetan momen yang tidak saling terhubung. Inilah yang disebut sebagai presentisme permanen, suatu kondisi di mana manusia hidup dalam keabadian “sekarang”, tanpa masa lalu yang dapat direnungkan atau masa depan yang dapat diantisipasi.
Dalam keadaan ini, tubuh biologis manusia yang masih beroperasi secara linear menjadi “usang” di hadapan tuntutan digital yang bekerja secara non-linear, terfragmentasi, dan hiperaktif.
Ketegangan antara dua rezim temporal ini melahirkan bentuk keterpecahan kesadaran antara “aku yang tampil” dan “aku yang mengalami”. “Aku yang tampil” adalah persona digital yang dikurasi, disunting, dan disimulasikan melalui algoritma visibilitas, sedangkan “aku yang mengalami” adalah subjek fenomenologis yang masih terikat pada pengalaman eksistensial tubuh, pada rasa letih, cemas, lapar, rindu, dan waktu yang berjalan lambat.
Friksi antara keduanya menciptakan residu eksistensial berupa keterasingan diri (self-estrangement): manusia hidup dalam dua ruang yang tak pernah benar-benar sinkron. Tubuh tertinggal di dunia yang lambat, sementara kesadaran terus dikejar oleh kecepatan digital yang tak mengenal batas. Akibatnya, muncul tekanan psikis yang berwujud dalam kecemasan kronis, disorientasi temporal, dan kelelahan eksistensial (existential fatigue) yang kini menjadi gejala umum masyarakat digital.
Lebih jauh, dunia digital yang awalnya menjanjikan kebebasan tanpa batas justru berubah menjadi penjara performatif. Dalam tatanan ini, eksistensi tidak lagi ditentukan oleh kedalaman makna, tetapi oleh intensitas keterlihatan. Manusia modern hidup dalam logika visibilitas, di mana “menjadi terlihat” lebih penting daripada “menjadi berarti”.
Algoritma media sosial bekerja sebagai kurator eksistensi yang menentukan siapa yang layak hadir dan siapa yang akan dilenyapkan dalam arus informasi. Dengan demikian, makna keberadaan tidak lagi bersumber dari pengalaman reflektif, melainkan dari logika pengakuan sosial yang dikalkulasi oleh sistem digital. Kehadiran bergeser dari fenomena eksistensial menjadi strategi performatif: manusia tidak lagi ada, melainkan dipertontonkan.
Fenomena ini diperparah oleh apa yang dapat disebut sebagai Kegagalan Inokulasi Digital. Dalam analogi biologis, tubuh memiliki sistem imun yang berfungsi mengenali, menahan, dan menetralisir serangan dari luar. Dalam konteks kesadaran, fungsi imunologis ini termanifestasi dalam kemampuan untuk menyaring informasi, menunda reaksi, dan menafsirkan makna sebelum merespons.
Namun, dalam arsitektur digital, mekanisme imunologis ini lumpuh. Kesadaran manusia kini terpapar oleh arus representasi, notifikasi, dan impuls afektif yang terus-menerus menyerang sistem kognitif tanpa memberi waktu untuk refleksi.
Arsitektur digital dirancang untuk menembus sistem afektif secara langsung, memicu emosi sebelum rasio sempat berfungsi. Rasa senang, marah, iri, takut, atau penasaran muncul bukan sebagai hasil interpretasi, melainkan sebagai efek instan dari desain antarmuka dan algoritma prediktif. Dalam situasi ini, kesadaran bekerja secara reaktif, bukan reflektif. Tubuh biologis masih memerlukan waktu untuk memproses, tetapi sistem digital terus memproduksi impuls baru sebelum proses sebelumnya sempat diselesaikan. Akibatnya, muncul bentuk disosiasi kognitif, di mana kesadaran terfragmentasi dan kehilangan kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman.
Kegagalan inokulasi ini menjadikan manusia kehilangan fungsi imunologis kesadaran: ia tidak lagi mampu membedakan mana yang perlu direspons dan mana yang seharusnya diabaikan. Kesadaran menjadi terbuka tanpa pertahanan, selalu terpapar dan terprovokasi oleh setiap rangsangan.
Dalam kondisi demikian, manusia tidak lagi menjadi subjek yang mengarahkan perhatian, melainkan objek yang diarahkan oleh arus stimulus yang tak berkesudahan. Ketika setiap impuls eksternal menuntut reaksi segera, maka kemampuan untuk menunda, menimbang, dan memahami menjadi mustahil.
Dengan demikian, krisis kesadaran di era digital bukan hanya tentang kehilangan makna, melainkan tentang keruntuhan struktur epistemik dan afektif yang selama ini menopang keberadaan manusia. Tubuh kehilangan sinkronisasi dengan kesadaran, kesadaran kehilangan daya imunologisnya terhadap informasi, dan manusia kehilangan kemampuan untuk mengalami dunia dengan kedalaman reflektif. Kita hidup dalam kecepatan yang meniadakan pengalaman, dalam keterhubungan yang meniadakan kehadiran, dan dalam keterlihatan yang meniadakan kebermaknaan.
Kolonisasi Kekuasaan : Heterotopia dan Simultanitas Ruang Digital
Keterhilangan eksistensial manusia dalam era digital bukan hanya sekadar akibat dari keterpisahan individu terhadap realitas konkret, melainkan juga hasil dari transformasi mendasar terhadap struktur kekuasaan yang bekerja di dalam ruang digital itu sendiri. Ruang digital, apabila dianalisis melalui kacamata konsep Heterotopia yang dikemukakan Michel Foucault, dapat dipahami sebagai ruang lain, yaitu ruang yang diciptakan di luar tatanan ruang yang kita kenal secara fisik, tetapi memiliki sistem logika dan prinsip keteraturan yang tidak selamanya linear, sebagai contoh kuburan dan perpustakaan yang bisa memberhentikan proses kemewaktuan linear dalam pengalaman subjek.
Dalam heterotopia digital, hubungan antara subjek, waktu, dan kebenaran tidak lagi tunduk pada hukum linearitas, sebab waktu di sini hadir dalam bentuk yang terfragmentasi, bersifat simultan dan dikonstinue. Setiap momen digital tidak berlangsung secara berurutan, melainkan berlapis dan tumpang tindih di dalam jaringan arus data yang tanpa batas geografis.
Namun demikian, meskipun ruang digital tampak seperti tempat tanpa batas yang menjanjikan kebebasan dan keterbukaan, sesungguhnya ia tetap diatur oleh logika otoritas yang bersifat sistemik. Otoritas ini tidak lagi menampakkan diri dalam bentuk kekuasaan yang bersifat fisik atau koersif, melainkan termanifestasi dalam struktur algoritma, regulasi platform, dan logika distribusi informasi.
Dengan kata lain, kekuasaan dalam ruang digital bersifat imanen, tersebar di dalam mekanisme yang mengatur bagaimana data diolah, interaksi sosial dibingkai, dan kebenaran dimanifestasikan. Di titik inilah, ruang digital menjadi suatu bentuk “space within no space”, yaitu ruang yang tidak bergantung pada lineritas kemewaktuan realitas fisik, tetapi tetap dikendalikan oleh struktur logis yang menentukan batasan dan arah perilaku penggunanya.
Transisi dari ruang analog menuju ruang digital dengan demikian bukanlah proses pembebasan dari kekuasaan, tetapi hanya transformasi bentuk dari otoritas itu sendiri. Jika dalam ruang analog kekuasaan bekerja melalui lembaga dan norma sosial yang eksplisit, maka dalam ruang digital kekuasaan bekerja dalam bentuk yang lebih subtil dan tersembunyi.
Ia hadir dalam algoritma pencarian, sistem rekomendasi, serta dalam bentuk eksploitasi data yang menentukan arah dan bentuk interaksi manusia di dunia maya. Individu merasa bebas karena ia dapat mengekspresikan diri tanpa batas, padahal ekspresi tersebut selalu dimediasi dan diarahkan oleh struktur sistem yang menentukan apa yang layak muncul dan apa yang harus tersembunyi.
Maka, pernyataan-nya bahwa kebebasan dalam ruang digital merupakan bentuk lain dari perbudakan bukanlah paradoks yang berlebihan. Justru hal itu menunjukkan bagaimana otoritas menjelma menjadi sesuatu yang halus dan nyaris tak terlihat, tetapi tetap menjamin agar fungsi ruang digital berjalan sesuai dengan logika dan kepentingan kecerdasan yang menentukannya. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang telah dimanipulasi, kebebasan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, eksistensi manusia di dalam ruang digital selalu berada dalam tegangan antara ilusi kebebasan dan kenyataan keterikatan terhadap otoritas yang tak kasat mata, yang tidak jarang keterbenaman digital yang memberikan implikasi logis pada dunia kongkrit dimana hukum fisika linear bekerja seringkali ditentukan oleh daya rekayasa dunia digital, terutama bagaimana pikiran, hasrat dan hidup dikondisikan kembali.
Di sinilah keterhilangan eksistensial menemukan bentuknya yang paling kompleks. Manusia bukan lagi kehilangan dirinya karena terasing dari dunia nyata, melainkan karena dirinya larut di dalam sistem representasi digital yang membentuk ulang kesadarannya. Identitas menjadi cair, pengalaman menjadi data, dan makna menjadi produk dari kalkulasi algoritmik.
Dalam konteks inilah, ruang digital dapat dipandang sebagai heterotopia kontemporer yang merepresentasikan paradoks modernitas itu sendiri, yaitu pencarian kebebasan yang berujung pada penemuan bentuk baru dari sistem kendali yang tidak teridentifikasi atas operasi sistemiknya.
Timelessness Digital: Fragmen Eksistensi dan Alienasi Modern
Kekuatan utama dari heterotopia digital terletak pada konsep heterokroni, yaitu kondisi ketidakmewaktuan atau timelessness. Dalam ruang digital, waktu tidak lagi dipahami sebagai urutan yang linear, melainkan sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai titik secara simultan. Ruang dan waktu melebur menjadi satu kesatuan yang cair, di mana segala sesuatu dapat hadir bersamaan tanpa urutan kronologis yang pasti.
Konsekuensi filosofis dari kondisi ini sangat mendalam. Muncul keadaan yang dapat disebut sebagai kondisi nir-eksistensial pada subjek, ketika waktu sebagai medium bagi pengalaman yang bermakna kehilangan fungsinya di bawah logika simultanitas digital. Dalam keadaan demikian, pengalaman yang tidak lagi berakar pada alur waktu yang berkesinambungan, sehingga subjek kehilangan kemampuan untuk memahami proses sebab-akibat yang menjadi dasar atas cara kerja rasio manusia. Padahal, rasionalitas bergantung pada struktur temporal yang memungkinkan seseorang menafsirkan realitas melalui hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Ketika prosesi berpikir kehilangan fondasi kemewaktuan atau kausalitasnya, maka pengetahuan yang dihasilkan pun menjadi dangkal. Manusia semakin kesulitan mengaktualisasikan dirinya di dalam realitas, sebab melalui pengetahuan yang terfragmentasi manusia tidak lagi mampu memberikan kerangka utuh bagi kesadaran.
Proses berpikir berubah menjadi sekadar reaksi terhadap arus informasi yang terus berulang, tanpa refleksi yang mendalam atau dimana pengetahuan adalah proses unifikasi subjek dalam realitasnya. Dalam situasi ini, ruang digital berperan sebagai mekanisme kooptasi yang menyerap dan membentuk cara berpikir manusia, menjadikannya hadir tanpa kemampuan untuk menginterupsi atau menafsirkan realitas yang melingkupinya.
Aktivitas di ruang digital sering kali berlangsung tanpa jejak pengalaman yang autentik, karena setiap peristiwa segera digantikan oleh peristiwa lain dalam arus informasi yang tidak pernah berhenti. Akibatnya, manusia mengalami keterputusan antara keberadaan dan pengalaman. Eksistensi kehilangan kedalaman reflektifnya dan berubah menjadi sekadar kehadiran yang mengambang di permukaan realitas digital yang terus bergerak tanpa arah.
Kedua, kondisi heterokroni juga menimbulkan bentuk alienasi baru. Perspektif tanpa waktu mengganggu koordinasi sosial dan melemahkan ikatan emosional antarindividu. Ketika segala hal berlangsung secara bersamaan tanpa kesinambungan, relasi sosial kehilangan dimensi temporal yang diperlukan untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan empati. Akibatnya, ruang sosial tampak padat oleh interaksi, namun sesungguhnya kosong dari kehadiran diri yang autentik karena sepenuhnya dimediasi oleh rekayasa virtual. Kehadiran manusia telah bermigrasi ke dalam ruang virtual, tempat di mana segala sesuatu mengalami proses dehumanisasi.
Dalam realitas tersebut, apa pun yang tampak tidak lagi merepresentasikan kehadiran yang utuh, melainkan berubah menjadi sumber daya yang dapat dieksploitasi, dimanipulasi, dan diubah sesuai dengan logika teknologis yang mendasarinya.
Dalam konteks tersebut, dapat disisipkan apa yang disebut sebagai paradoks Abenvile, yaitu suatu kondisi di mana keterhubungan justru melahirkan keterputusan yang lebih dalam. Masyarakat modern hidup dalam keadaan yang secara teknologis sangat terkoneksi, namun secara eksistensial semakin terasing dari dirinya dan sekitarnya.
Di balik bentuk keterhubungan yang imersif melalui berbagai platform digital, tersembunyi kenyataan bahwa tidak seorang pun benar-benar memahami kebutuhan eksistensialnya. Hal ini terjadi karena setiap bentuk realitas virtual selalu terkait dengan proses rekayasa dan manipulasi yang mengatur bagaimana realitas dihadirkan. Realitas digital tidak dibangun di atas prinsip autentisitas, melainkan berlandaskan pada konstruksi ilusi yang disusun secara sistematis untuk menggantikan pengalaman nyata dengan representasi yang semu.
Dalam situasi semacam ini, ilusi menjadi nilai yang diidamkan. Subjek modern tidak lagi mencari kebenaran melalui proses verifikasi logis atau refleksi diri yang rasional, tetapi justru menerima apa pun yang tertampak di ruang digital sebagai kenyataan. Mekanisme persepsi dikendalikan oleh logika visual dan impresi, bukan oleh kontemplasi dan penalaran. Akibatnya, subjek kehilangan kemampuan untuk menginterupsi realitas yang dihadirkan oleh platform.
Dengan demikian, heterokroni dalam ruang digital tidak hanya menciptakan bentuk baru dari pengalaman waktu, tetapi juga mengubah cara manusia memahami keberadaan dirinya dengan orang lain. Dalam ketidakmewaktuan ini, eksistensi tidak lagi menjadi proses yang berkelanjutan, melainkan fragmen-fragmen yang melayang tanpa arah di dalam jaringan yang terus bergerak.
Kontrol Tanpa Aparatus: Kekuasaan dan Manipulasi Digital
Di dalam ruang yang tidak mengenal waktu ini, kekuasaan bertransformasi menjadi bentuk baru: kontrol tanpa aparatus fisik yang tidak teridentifikasi, yaitu otoritas yang imanen melalui cara kerja struktur algoritma dan arsitektur digital. Kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk lembaga yang memaksa, melainkan melalui mekanisme representatif yang bersifat manipulatif, yang dalam konteks teknologi dikenal sebagai intelligent persuasive design. Melalui mekanisme ini, proses kontrol bekerja secara halus namun efektif, menembus batas kesadaran subjek dan mengarahkan perilaku tanpa harus memaksakan kehendak secara eksplisit.
Proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk subjektivikasi, yakni cara kekuasaan menaklukkan subjek melalui pembentukan identitas dan perilaku yang sesuai dengan struktur kekuasaan yang telah ditetapkan.
Subjek tidak lagi dibentuk oleh pengalaman reflektif atau kesadaran otonom, melainkan oleh desain sistem yang secara invasif menstrukturkan cara berpikir, berinteraksi, dan menghadirkan diri dalam dunia. Dengan demikian, diri bukanlah entitas yang tetap dan stabil, melainkan arena pertarungan yang terus berlangsung, di mana kekuasaan berupaya menaklukkan kesadaran dan menjadikan subjek sebagai host atas ide kekuasaan itu sendiri.
Fenomena ini juga melahirkan apa yang dapat disebut sebagai user hostile stipulation, yaitu kondisi ketika ketentuan, kebijakan, atau desain sistem digital secara halus menempatkan pengguna pada posisi yang dirugikan, meskipun secara permukaan tampak netral. Konsep ramah pengguna dalam hal ini merupakan ilusi universal yang menegasikan kesadaran subjek akan adanya prosesi kekuasaan yang terselubung di balik setiap interaksi digital.
Dalam situasi seperti ini, manipulasi dilembagakan melalui desain yang secara sistematis mengatur cara pengguna berpikir dan bertindak tanpa disertai kesadaran dan kemampuan untuk melakukan interupsi terhadapnya.
Kekuasaan bekerja bukan melalui larangan atau paksaan langsung, melainkan pertama melalui alur persuasif yang bersifat imanen, kedua melalui gesekan halus antara kehendak platform dan kehendak pengguna, ketiga melalui pembiasaan yang dibangun dalam pola yang berulang. Ketiga mekanisme ini menjadikan proses penaklukan berlangsung secara subtil melalui kebiasaan, kenyamanan, dan keterbiasaan yang tampak alami. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi hadir sebagai entitas eksternal yang menindas, melainkan sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari yang diterima tanpa resistensi.
Dengan demikian, kekuasaan digital tidak lagi memerlukan aparatus yang represif, karena ia telah menyatu ke dalam fungsi algoritma & arsitek desain digital yang menentukan bagaimana manusia mengalami realitas. Yang terbentuk bukan lagi subjek yang mampu berkontestasi (mengaktifkan nalar berpikir kritis), melainkan subjek yang dikondisikan untuk berpikir sesuai dengan logika kekuasaan yang tersembunyi di balik representasi digital yang menjadikan kenyamanan sebagai sistem kendali terbarukannya.
Kapitalisme Digital dan Transformasi Eksistensial Manusia
Dalam pendekatan teori Marxian yang dikembangkan oleh Christian Fuchs mengenai kapitalisme digital, sistem ini tidak hanya dipahami sebagai fungsi dari kompresi ruang dan waktu, di mana kapital mengekstensifikasi sekaligus mengintensifikasi dirinya, tetapi juga sebagai mekanisme kendali yang secara fundamental bekerja melalui proses komodifikasi kesadaran. Sebelum sistem division of labour internasional dapat beroperasi secara efektif, yang terlebih dahulu harus ditentukan adalah bagaimana pikiran manusia dikendalikan.
Ide tentang kemajuan menjadi instrumen penindasan yang berjalan secara halus di bawah tingkat kesadaran, menciptakan kepatuhan tanpa interupsi melalui internalisasi nilai-nilai fundamentalnya. Kapitalisme digital dengan demikian adalah bentuk akselelator untuk mempercepat keterhilangan eksistensial manusia melalui dua mekanisme utama, yakni robotifikasi dan kolonisasi atensi.
A. Fragmentasi Epistemik dan Robotifikasi
Christian Fuchs, dalam kerangka pemikiran Marxian, menyoroti bagaimana kapitalisme digital tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga mengubah cara manusia berpikir dan memahami dunia. Kritiknya berangkat dari gagasan bahwa sistem kapitalistik yang beroperasi di ruang digital tidak lagi sekadar mengeksploitasi tenaga kerja fisik, melainkan juga tenaga kognitif dan kesadaran manusia.
Ketika Fuchs berbicara tentang dekualifikasi kerja, ia mengacu pada kondisi di mana kemampuan intelektual dan keterampilan manusia kehilangan otonomi karena digantikan oleh teknologi otomatis. Dalam sistem ini, pekerja tidak lagi memegang kendali penuh atas proses kerja atau makna dari apa yang ia kerjakan. Pekerjaan manusia dibatasi pada fungsi-fungsi kecil, terfragmentasi, dan terukur.
Hal ini berkaitan dengan fragmentasi epistemik, yaitu terpecahnya pengetahuan menjadi fragmen spesialisasi yang tidak lagi memiliki hubungan organik satu sama lain. Akibatnya, manusia kehilangan pandangan menyeluruh tentang realitas sosialnya, karena setiap orang hanya memahami sebagian kecil dari sistem besar yang ia layani.
Di sinilah muncul konsep assemblage of machine, yang menggambarkan manusia sebagai kumpulan fungsi mekanis yang bekerja di bawah kendali perhitungan matematis dari logika industri yang mendambakan efesiensi yang rigid dan massifikasi produksi yang tereduksi dalam langskap matematis semata. Dalam kondisi ini, manusia diperlakukan seperti bagian dari mesin, bukan sebagai makhluk reflektif yang memiliki kesadaran dan makna dalam tindakannya. Fuchs menegaskan bahwa rasio kontemplatif secara inheren adalah kemampuan untuk merenung (sources of self determination), memahami, dan memberi makna pada pengalaman yang kian digantikan oleh rasio instrumentalis mesin, yaitu rasio yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan produktivitas.
Dari proses ini lahirlah konsep robotifikasi, yaitu transformasi struktural di mana bukan hanya mesin yang menjadi cerdas, tetapi manusia juga secara perlahan dikondisikan untuk berpikir dan bertindak menurut logika mesin. Robotifikasi bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan juga fenomena ideologis yang menstrukturkan kesadaran manusia agar selaras dengan nilai-nilai produktivitas, kecepatan, dan efisiensi yang dikultuskan oleh kapitalisme digital di balik mitos kata kemajuan. Dalam kerangka ini, terjadi proses kurasi terhadap kehadiran manusia dalam realitasnya sendiri, sehingga kerja tidak lagi dipahami semata sebagai transaksi energi dan relasi upahan, melainkan sebagai basis eksistensial atau sebagai suatu cara dimana manusia meneguhkan keberadaannya melalui tindakan dan pemaknaan atas dirinya di dunia.
Konsekuensi dari proses negasi kemanusiaan ini sangat mendalam. Penyesuaian manusia terhadap cara kerja mesin sering kali terjadi di balik diksi “profesionalitas” yang secara halus menormalisasi pelepasan unsur kemanusiaan demi efisiensi dan produktivitas.
Dalam kerangka ini, manusia mengalami keterhilangan sisi emosional, etis, dan spiritual dari dirinya sendiri, suatu bentuk pengasingan eksistensial yang memisahkan pikiran dan tubuh dari kesadaran hidup yang utuh. Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, penderitaan, dan solidaritas semakin tersingkir karena tidak dapat diukur atau dikalkulasi secara kuantitatif. Bahkan, dalam sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh objektivitas terkuantifikasi, nilai-nilai tersebut kerap dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas dan efisiensi operasional.
Padahal, bagi Christian Fuchs dan para pemikir kritis lainnya, di sanalah letak sumber keadilan dan makna kehidupan perlu dipertanyakan kembali. Kemampuan manusia untuk merasakan ketidakadilan, untuk menderita bersama yang tertindas, merupakan alasan dimana resistensi atau koreksi sistemik mungkin dilakukan dengan penalaran eksistensial. Dalam konteks ini, perlawanan manusia memiliki dimensi ontologis yang tidak dapat direplikasi oleh mesin, sebab kecerdasan buatan tidak memiliki kapasitas untuk merasakan penderitaan atau melakukan demonstrasi menuntut keadilan sebagaimana yang dilakukan manusia dalam membangun peradaban.
Namun, dalam sistem kapitalisme digital, nilai-nilai tersebut digantikan oleh logika kuantifikasi, yaitu cara berpikir yang menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran performa, data, dan hasil terukur. Nilai kemanusiaan menjadi sekunder, sementara nilai produktivitas menjadi pusat. Akibatnya, manusia tidak lagi dinilai dari keberadaannya sebagai subjek yang mengada dalam realitas, melainkan sejauh mana ia dapat berkontribusi pada sistem ekonomi yang diatur oleh kuasa fungsi algoritma.
B. Eros Machine dan Human Trafficking Digital
Krisis ini mencapai puncaknya dalam apa yang disebut sebagai Ekonomi Atensi, yaitu suatu sistem yang beroperasi dengan merampas fokus manusia melalui peretasan skema hasrat dan kenikmatan yang diolah menjadi mekanisme candu.
Proses ini berlangsung melalui bentuk industrialisasi persuasi, di mana sistem digital secara sistematis mengeksploitasi kecenderungan kognitif dan emosional manusia untuk mempertahankan keterikatan terhadap platform. Dalam sistem ini, perhatian manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dimanipulasi dan diperdagangkan melalui mekanisme monetisasi. Logika algoritmik berfungsi sebagai instrumen utama yang mengatur bagaimana manusia melihat, merasakan, dan berinteraksi dengan realitas.
Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perdagangan manusia dalam ranah digital pada tingkat psikis. Kesadaran dan perhatian, yang seharusnya menjadi milik pribadi dan bebas, kini dijadikan objek eksploitasi yang tersembunyi di balik ilusi “gratis” yang ditawarkan oleh berbagai platform digital. Istilah “perdagangan manusia” dalam konteks ini merujuk pada perampasan kendali atas diri, yang sejak awal telah dibajak melalui sistem imbalan atau reward system yang direkayasa untuk menstimulasi respons hasrat dan kepuasan instan.
Kateryna Spravtseva menyebut bahwa mekanisme yang beroperasi di balik fungsi teknis dan matematis teknologi tidak dapat dipahami semata-mata secara fungsi instrumental teknologi, namun cara kerja teknologi justru mencerminkan logika mesin yang juga memproduksi hasrat, atau yang ia sebut sebagai Eros Machine, yaitu merupakan sistem yang beroperasi dengan memanfaatkan hasrat manusia sebagai sumber energi produksi.
Dalam kerangka ini, hasrat tidak lagi berfungsi sebagai dorongan eksistensial yang mendorong manusia untuk mencipta, mencintai, dan menjalin relasi yang bermakna. Sebaliknya, hasrat telah direduksi menjadi instrumen ekonomi yang menopang sirkulasi kapital digital dengan perhitungan kuantifikasi visibilitas. Kekuatan kreatif dan kapasitas pembuka makna yang seharusnya melekat pada hasrat kini diarahkan sepenuhnya pada konsumsi berulang, perhatian yang terus dikuras, serta pembentukan identitas yang direkayasa oleh fungsi sistem.
Singkatnya Platform digital juga bekerja di tingkat yang paling dalam dari kesadaran manusia, yakni pada ranah hasrat dan fantasi.
Terdapat tiga pola mendasar bagaimana “Eros Machine” membentuk perilaku manusia di ruang digital melalui manipulasi hasrat dan motivasi psikologis. Pola pertama adalah hasrat untuk diakui. Dalam konteks digital, individu terus mencari validasi dari orang lain melalui representasi diri, seperti unggahan, komentar, atau tanda “like”. Hasrat ini mendorong individu untuk selalu menampilkan citra tertentu yang diharapkan disetujui oleh komunitas atau algoritma platform. Validasi menjadi mekanisme internal yang menahan keterikatan pengguna pada sistem, karena kepuasan psikologis tergantung pada pengakuan eksternal. Pola kedua adalah kecemasan akan ketidakhadiran atau “fear of missing out”. Perasaan takut tertinggal dari arus sosial mendorong individu untuk selalu terhubung, memeriksa informasi terbaru, dan mengikuti dinamika sosial secara terus-menerus. Ketergantungan ini membuat pengguna tidak hanya hadir secara fisik di platform, tetapi secara kognitif dan emosional terus diikat oleh logika digital yang menuntut keterlibatan permanen. Pola ketiga adalah kenikmatan dalam menampilkan diri, atau pleasure of exposure. Proses eksposur diri di ruang digital tidak lagi sekadar komunikasi atau berbagi informasi, tetapi menjadi sumber kepuasan yang adiktif. Semakin sering individu memamerkan dirinya, semakin mereka menerima umpan balik yang memperkuat perilaku tersebut, sehingga muncul siklus terus-menerus antara representasi diri, pengakuan sosial, dan kesenangan yang dihasilkan dari perhatian orang lain.
Dengan demikian, Eros Machine tidak hanya mengatur interaksi manusia dengan teknologi, tetapi juga membentuk subjektivitas mereka, menjadikan individu hidup dan bertindak demi logika platform. Pola-pola tersebut berkelindan membentuk siklus hasrat yang terus berputar tanpa tujuan akhir. Manusia tidak lagi mengendalikan hasratnya sendiri, melainkan dikendalikan oleh sistem yang menata dan memproduksi hasrat itu. Dalam kondisi ini, Eros Machine tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga membentuk struktur batin manusia, menjadikan individu bukan lagi subjek yang memiliki hasrat, melainkan medium tempat hasrat sistem beroperasi.
Keseluruhan mekanisme ini melahirkan keadaan yang dapat disebut sebagai being for the algorithm, yaitu kondisi di mana subjektivitas manusia dibentuk dan diarahkan oleh relasi dengan sistem algoritmik. Identitas manusia direduksi menjadi profil pengguna yang terkomputasi, dan setiap bentuk interaksi dengan dunia dimediasi oleh logika data. Sistem ini dirancang untuk menumbuhkan kondisi ketidakpuasan yang produktif, yaitu keadaan psikologis di mana rasa kurang, iri, dan keinginan yang tak pernah terpenuhi menjadi bahan bakar utama bagi siklus konsumsi dan keterikatan pada platform yang tidak pernah berhenti.
Dengan demikian, kolonisasi atensi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan ontologis. Ia menandai bentuk baru penaklukan kesadaran, di mana manusia tidak lagi sekadar bekerja untuk sistem, tetapi hidup di dalam sistem yang bekerja melalui dirinya.
Implikasi Psikologis: Dari Depresi hingga Apokaliptik Epistemik
Keterhilangan eksistensial manusia di era digital tidak hanya bersifat konseptual atau filosofis, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang nyata dan mendalam. Jonathan Haidt dalam bukunya Anxiety Generation berpendapat bahwa kehancuran mental tidak terjadi semata karena penyakit, krisis ekonomi, atau ketidakstabilan geopolitik, melainkan muncul dalam situasi damai, di mana penyebab utamanya adalah ekosistem informasi yang terus-menerus menggerogoti pola pikir dan persepsi individu.
Fenomena ini dapat dipahami melalui aforisme Mars, dimana seseorang mengirim anak-anaknya ke planet lain dalam situasi yang ia tidak ketahui, yang menjadi metafora bagi kondisi manusia modern dalam ruang digital. Seperti anak yang tiba-tiba ditempatkan di planet asing dengan aturan, atmosfer, dan tantangan yang sama sekali baru, manusia kini hidup di lingkungan digital yang penuh dengan logika algoritmik dan mekanisme platform yang tidak dipahami. Individu terpaksa menavigasi dunia ini tanpa panduan yang memadai, menghadapi arus informasi yang simultan, fragmentasi pengetahuan, dan tekanan psikologis yang konstan.
Untuk bagian selanjutnya, penulis akan menjelaskan gagasan tersebut melalui dua konsep utama yang muncul dari manifestasi aforisme Mars: pertama, Internalizing dan Externalizing Disorder, yang semakin sering dialami oleh remaja di era digital; kedua, Tragedi Otonomi Sistem Modern dan Apokaliptik Epistemik, yang menggambarkan hilangnya agensi manusia dan krisis pemahaman dalam tatanan sistemik kontemporer.
Internalizing dan Externalizing Disorder
Keterlibatan yang intens dalam ruang digital menciptakan tekanan psikologis yang halus namun signifikan, yang berkaitan dengan meningkatnya gangguan internalizing, seperti depresi dan kecemasan, serta gangguan externalizing, seperti agresi dan perilaku impulsif.
Internalizing disorder muncul ketika tekanan psikologis diarahkan ke dalam diri sendiri. Individu mengalami perasaan negatif yang mendalam, overthinking, atau rasa tidak berharga. Gejala yang timbul termasuk penarikan diri dari interaksi sosial, kecemasan berlebihan, kesedihan, dan perasaan tidak berdaya.
Dalam konteks ruang digital, arus informasi yang terus-menerus dan kurangnya ruang refleksi mendorong fenomena ini, sehingga individu semakin terasing dari pengalaman dan eksistensinya sendiri.
Sebaliknya, externalizing disorder terjadi ketika tekanan psikologis diekspresikan melalui perilaku yang tampak secara eksternal. Individu mungkin menunjukkan agresi, impulsivitas, atau perilaku destruktif. Dalam ekosistem digital, interaksi instan, notifikasi konstan, dan tuntutan respons cepat memicu tindakan reaktif tanpa kontrol reflektif. Hal ini menciptakan siklus di mana frustrasi internal diterjemahkan menjadi perilaku yang memengaruhi lingkungan, baik secara sosial maupun digital.
Kedua mekanisme ini sering saling berkelindan. Tubuh biologis dipaksa menyesuaikan diri dengan realitas digital yang non-linear, menghasilkan disinkronitas psiko-biologis yang memicu stres, kelelahan mental, dan ketidakstabilan emosional. Kondisi ini juga memunculkan fenomena yang disebut kegilaan impulsif, yaitu ledakan dorongan afektif yang muncul tanpa mediasi rasional. Notifikasi instan, klik cepat, dan tuntutan respons segera mempercepat dorongan ini, sehingga individu cenderung bertindak reaktif tanpa refleksi.
Di sisi lain, rasa terisolasi secara sosial muncul sebagai bentuk ketakutan yang mendalam, yang bagi banyak orang terasa lebih menakutkan bahkan daripada kematian biologis. Dengan kata lain, keterikatan yang tampak padat di dunia digital justru memperkuat pengalaman kesepian dan alienasi eksistensial, di mana tekanan internal dan eksternal saling memperkuat dan memperburuk kondisi psikologis manusia.
Kesimpulan
Keterhilangan eksistensial menandai hilangnya agensi ontologis manusia. Kehendak individu, yang seharusnya menjadi inti dari tindakan moral dan reflektif, terserap dan direduksi menjadi perpanjangan dari logika sistem. Tragedi struktural dari rasionalitas modern muncul ketika niat baik manusia tenggelam dalam logika mekanistik yang diciptakannya sendiri, sehingga moralitas dan nilai etis kehilangan pijakan dalam tatanan digital.
Fenomena ini sejalan dengan gagasan Heidegger tentang teknologi sebagai takdir, di mana teknologi berhenti menjadi alat dan justru menjadi kekuatan yang mendikte cara hidup dan berpikir manusia.
Dalam konteks ini, koreksi filosofis menjadi sangat penting. Sejalan dengan gagasan Digital Athena Marxian, teknologi seharusnya menjadi sarana pembebasan yang membuka ruang bagi pengembangan intelektual, kreativitas, dan kehidupan sosial manusia, bukan semata untuk mempercepat produksi atau memperkuat dominasi.
Tanpa fondasi korektif ini, teknologi akan terus beroperasi sebagai sistem dominasi tersamar di balik ilusi kemajuan, menuntun manusia ke kondisi yang dapat disebut apokaliptik epistemik, yaitu kehilangan kemampuan memahami totalitas pengetahuan dan merasakan pengalaman yang autentik.
Dengan kata lain, tantangan filosofis terbesar abad kedua puluh satu bukan sekadar melawan mesin atau algoritma, tetapi melawan logika yang telah menguasai kesadaran manusia, membentuk perilaku, hasrat, dan identitas. Jika tidak direspon, manusia berisiko kehilangan kendali atas otonomi, refleksi, dan pencarian makna, menjadi saksi sekaligus korban dari sistem yang bekerja melalui dirinya sendiri.
Referensi:
Tegmark, Max. Life 3.0: Menjadi Manusia di Era Kecerdasan Buatan. Terjemahan Indah Lestari. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
Avcı, S. “The Transformation of the Understanding of Self in the Metaverse Reality as a Heterotopia Place.” Etkileşim 10 (2022): 186–206.
https://doi.org/10.32739/etkilesim.2022.5.10.175
Fuchs, Christian. Membaca Kembali Marx di Era Kapitalisme Digital. Terjemahan Fatkhur Rahman.
Yogyakarta: Penerbit Independen, 2021.
Spravtseva, Kateryna. “Digital Narcissism: Psychoanalytic Mechanisms of Personality Manifestation in Social Media and Their Impact on Psychological Well-Being.” Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology” 11, no. 1 (2025): 104–112. https://doi.org/10.52534/msu-pp1.2025.104
Williams, James. Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Haidt, Jonathan. Generasi Cemas. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2025.
Harari, Yuval Noah. Nexus: Menghubungkan Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2025.
Shadr, Muhammad Baqir. Falsafatuna: Materi, Filsafat dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam. Jakarta: Rausyan Fikr, 2020.***
Penulis: Daniel Russell, Alumni GMNI Bandung.