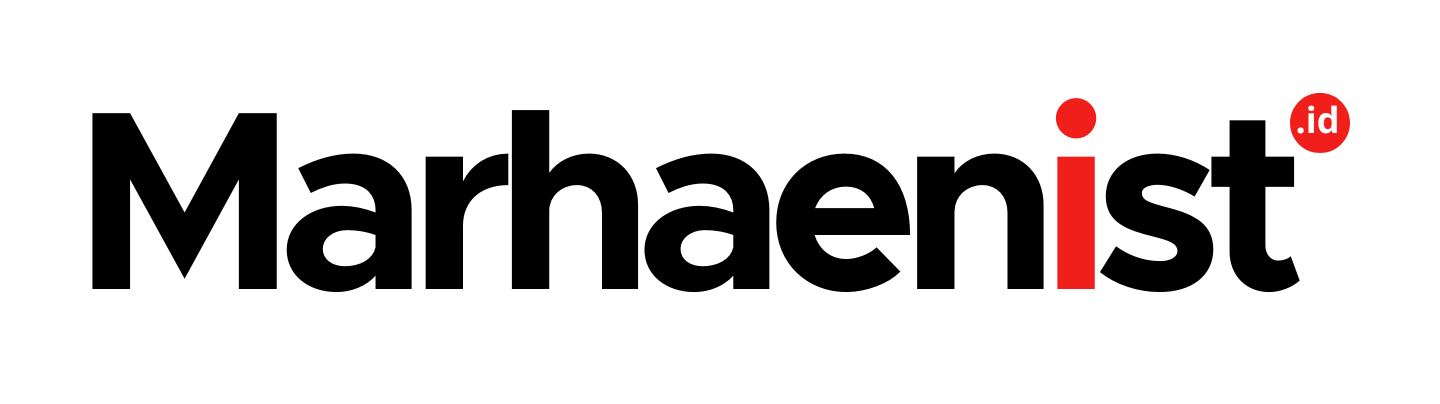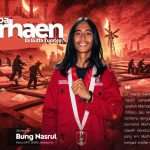Marhaenist.id – Kondisi ekonomi Indonesia butuh waktu untuk kembali membaik. Tiap saat kita mendengar keluhan sulitnya mencari penghidupan. Mereka yang bekerja pun selalu dibayangi kekhawatiran kemungkinan kehilangan penghidupan setiap saat.
Tak heran di dunia maya orang muda mengungkapkannya lewat tagar #KaburAjaDulu.
Kendati sudah mulai surut tapi kita tetap yakin banyak orang terpengaruh, buktinya makin banyak sebaran konten medsos yg mengajak WNI cari kerja di negara-negara lain di seluruh dunia.
“Kita mesti bersikap kritis penting agar tidak nekad berangkat lalu kena masalah dan atau kecewa sampai tujuan”.
Meninggalkan tanah air untuk bekerja dan tinggal diluar negeri kini menjadi pilihan yang makin populer di kalangan anak muda Indonesia. Di mata sebagian, langkah ini dipandang sebagai keputusan oportunistik. Namun sesungguhnya, bagi banyak orang, ini adalah pilihan rasional demi masa depan yang lebih baik, bukan karena kurangnya nasionalisme.

Merantau adalah peluang emas bagi siapa pun yang ingin memperbaiki taraf hidup dan mengembangkan kapasitas diri. Negara-negara maju menawarkan kompensasi yang jauh lebih tinggi di sektor-sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, dan teknik. Tak hanya itu, sistem kerja yang profesional, transparan, dan meritokratis menjadi magnet kuat bagi para pekerja terdidik dari negara berkembang.
Bekerja di luar negeri menumbuhkan etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab. Perantau belajar hidup mandiri, menghadapi tekanan, dan beradaptasi dengan budaya baru. Mereka juga mendapat akses ke teknologi mutakhir dan jaringan profesional global, yang memperluas wawasan serta memperkaya keterampilan. Singkatnya, merantau sering kali menjadi “sekolah kehidupan” yang tak tersedia di dalam negeri.
Namun, di balik cerita-cerita sukses itu, tidak sedikit yang pulang dalam keadaan hancur. Ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa persiapan matang, kendala bahasa dan budaya, biaya hidup yang tinggi, tekanan mental, hingga eksploitasi di tempat kerja menjadi sisi gelap dari pengalaman merantau. Ada yang kehilangan tabungan, bahkan kesehatan mental. Realita ini kerap tersembunyi di balik narasi glamor para perantau yang berhasil.
Yang lebih mencemaskan adalah dampaknya bagi bangsa. Ketika generasi terbaik Indonesia memilih tinggal dan berkarya secara permanen di luar negeri, negara kehilangan aset paling berharga, manusia unggul. Ini adalah wajah nyata dari brain drain. Akibatnya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset kekurangan tenaga ahli. Proses inovasi tersendat. Ketimpangan antara pusat dan daerah makin lebar. Daya saing nasional melemah di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Sayangnya, Indonesia belum mampu membendung gelombang ini. Upah yang tak kompetitif, birokrasi lambat, minimnya dukungan pada riset, serta lemahnya sistem meritokrasi membuat banyak profesional muda merasa tak dihargai di negeri sendiri. Mereka pergi bukan karena benci, tapi karena tak menemukan ruang untuk berkembang.
Tentu kita tak bisa dan tak boleh menghalangi orang merantau. Itu adalah hak individu. Tapi yang penting adalah menciptakan ekosistem yang membuat mereka ingin kembali. Negara harus membuka ruang partisipasi nyata, menciptakan iklim kerja yang adil dan kompetitif, serta memberi ruang bagi reverse brain drain. Mereka yang telah belajar dan bekerja di luar negeri semestinya bisa pulang membawa pulang ilmu, jaringan, dan pengalaman untuk membangun negeri.
Karena sejatinya, nasionalisme bukan soal tinggal di tanah air sepanjang hidup, tetapi soal keberanian untuk kembali, dan memberi.
Penulis : Dr. med. vet. Rudi Samapati, Alumni GMNI, FKH UGM. Penulis tinggal di Berlin, Jerman.