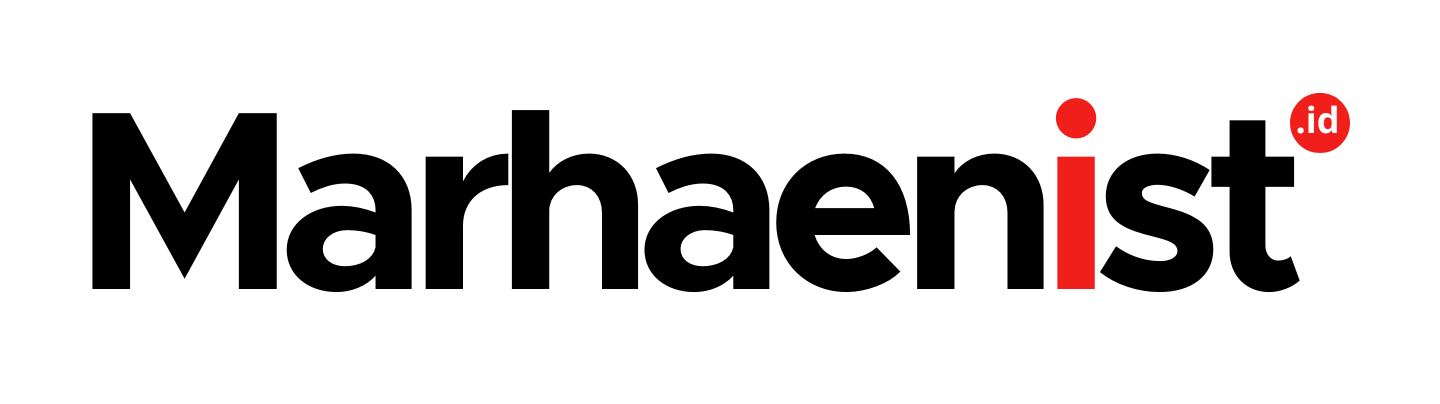Marhaenist.id – Dua puluh tujuh tahun setelah reformasi, makna demokrasi di Indonesia kian menyempit. Apa yang dulu diperjuangkan sebagai sarana pembebasan rakyat dari kekuasaan yang menindas, kini menjelma menjadi sekadar pesta lima tahunan tanpa ruh emansipasi. Partisipasi rakyat berhenti di bilik suara, sementara politik kehilangan daya gugatnya terhadap ketimpangan yang terus melebar. Seperti dicatat Chantal Mouffe, kita hidup dalam era post-politics — sebuah zaman di mana konflik ideologis dan perjuangan kelas dibungkam oleh bahasa teknokratis yang dibalut slogan “rasionalitas bersama.”
Dalam kerangka pemikiran Chantal Mouffe, post-politics adalah ketika politik kehilangan watak konfrontatifnya dan direduksi menjadi urusan manajerial belaka. Persoalan sosial dianggap sekadar soal teknis yang bisa diselesaikan dengan efisiensi dan administrasi, bukan lagi medan pertempuran ideologis antara visi masyarakat yang saling bertentangan. Akibatnya, politik tercerabut dari semangat emansipatorisnya. Di Indonesia, gejala ini tampak gamblang: selepas pemilu, hampir semua partai politik berduyun-duyun merapat ke lingkar kekuasaan dengan dalih stabilitas dan rekonsiliasi nasional. Oposisi dipinggirkan, kritik dicurigai, dan perbedaan pandangan dianggap mengancam “persatuan.” Ruang publik pun kehilangan denyut politiknya sehingga demokrasi seolah masih hidup, tetapi jiwa dari demokrasi tersebut telah lama mati.
Dalam keadaan seperti ini, penting untuk menghadirkan kembali narasi tandingan yang membangkitkan semangat agonisme, yaitu ruang bagi perbedaan untuk beradu gagasan, bukan disingkirkan. Di sinilah gagasan Populisme Kiri dari Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau menjadi relevan. Populisme Kiri bukan nostalgia omong kosong terhadap masa lalu, melainkan upaya membangun kekuatan baru dari rakyat kecil dan kelas tertindas dengan bahasa politik yang bisa menandingi dominasi wacana neoliberal hari ini.
Di Indonesia, jejak populisme kiri sesungguhnya sudah lama ada. Dari berdirinya ISDV yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia pada 1914, hingga gagasan marhaenisme Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin, semuanya merupakan usaha untuk mempersatukan rakyat tertindas di bawah cita-cita keadilan sosial.
Soekarno dalam Mencapai Indonesia Merdeka tidak pernah menyebut bahwa partai sekadar alat elit untuk berebut kursi, melainkan ia menegaskan fungsi partai sebagai pelopor yang membangunkan kesadaran rakyat tertindas. Ia menulis:
Welnu, bagaimanakah kita bisa menjelmakan pergerakan yang onbewust dan ragu-ragu dan raba-raba menjadi pergerakan yang bewust dan radikal? Dengan suatu partai! Dengan suatu partai yang mendidik Rakyat jelata itu ke dalam ke-bewust-an dan keradikalan. Dengan suatu partai, yang menuntun Rakyat jelata itu di dalam perjalanannya ke arah kemenangan, mengolah tenaga Rakyat-jelata itu di dalam perjuangannya sehari-hari, — menjadi pelopor daripada Rakyat jelata itu di dalam menuju kepada maksud cita-cita.
Di pidato Rediscovery of Our Revolution, ia bicara soal herordening politik yaitu penataan ulang politik. Ia ingin rakyat tidak lagi ditunggangi pemimpin, tapi justru memegang kendali atas demokrasi itu sendiri. Demokrasi, kata Soekarno, bukan soal “satu orang satu suara”, tapi soal tanggung jawab bersama, soal bagaimana setiap orang berhak hidup layak dan berkewajiban memperjuangkan kepentingan umum.
Sekarang, kalau kita lihat sekitar, kata-kata itu terasa semakin relevan. Di tengah kota yang gemerlap, di balik gedung-gedung tinggi, masih banyak orang tidur di bawah jembatan. Masih ada keluarga yang terusir dari rumahnya karena proyek pembangunan nasional. Upah buruh yang tidak cukup buat beli beras sebulan. Semua itu membuat kita sadar bahwa demokrasi yang ada hari ini tidak lebih dari sekadedar omong kosong. Hidup, tapi tanpa isi. Dan di situ, gagasan Soekarno hidup lagi, mengajarkan bahwa demokrasi sejati bukan soal memilih dan dipilih, tapi soal bagaimana rakyat marhaen merebut lagi kendali atas hidup dan nasibnya sendiri.
Gagasan Soekarno ini terasa penting untuk membayangkan ulang peran partai politik di tengah iklim post-politics Indonesia hari ini. Partai seharusnya tidak lagi berfungsi sebagai “koeliewerver suara” seperti di masa kolonial — sekadar pengumpul massa untuk kepentingan elektoral — melainkan menjadi alat perjuangan ideologis, tempat lahirnya kesadaran kelas dan keberpihakan politik yang nyata. Dalam situasi sekarang, yang dibutuhkan bukan hanya oposisi elektoral yang hadir di parlemen demi memenuhi syarat demokrasi prosedural, tapi oposisi yang punya basis sosial, ideologi, dan kemandirian. Oposisi yang tumbuh dari bawah, bukan dibentuk dari kompromi kekuasaan.
Kita bisa belajar dari tempat lain. Di Amerika Latin, ada Movimiento al Socialismo di Bolivia, ada juga Partido dos Trabalhadores di Brasil. Dua-duanya lahir dari bawah, dari pergulatan rakyat biasa yang ingin mengubah nasibnya sendiri. Mereka melihat politik bukan sekadar perebutan kursi, tapi soal siapa yang berkuasa atas hidup dan kerja mereka.
Di Eropa, Podemos di Spanyol dan La France Insoumise di Prancis mencoba hal serupa. Mereka menyatukan amarah sosial, protes jalanan, dan energi politik dalam satu arah: menolak logika neoliberal yang membuat segalanya tampak wajar, bahkan ketimpangan. Dari mereka kita belajar, politik bisa kembali punya arti kalau berpihak pada orang kecil, bukan pada meja perundingan para elite.
Contoh yang lebih nyata bisa kita lihat di Amerika Latin, lewat Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) di Brasil. Gerakan petani tak bertanah ini bukan cuma menuntut reforma agraria. Mereka membangun kekuatannya sendiri dari bawah, menata kehidupan tanpa menunggu negara turun tangan.
Di banyak tempat, MST membangun sekolah sendiri, klinik, bahkan sistem ekonomi kecil yang dikelola bersama. Semua dijalankan dengan semangat gotong royong dan solidaritas kelas tertindas. Mereka hidup dari tanah yang mereka perjuangkan, dan dari situ mereka membuktikan bahwa oposisi sejati bisa tumbuh di luar kekuasaan, tapi tetap berpengaruh. Bukan lewat pidato omong kosong, tapi lewat cara hidup yang menolak tunduk.
Dari berbagai pengalaman itu, kita bisa menarik satu kesimpulan: di tengah iklim post-politics dan ancaman fasisme-militeristik di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, Indonesia butuh ruang politik baru yang bisa menjadi wadah oposisi rakyat. Tapi wadah itu tak bisa lahir dari kompromi dengan kekuasaan. Ia harus berdiri di atas prinsip non-cooperative — sikap untuk tidak tunduk pada struktur yang menindas.
Non-cooperative bukan berarti menolak politik, tapi menolak logika politik borjuis yang membatasi rakyat hanya sebagai penonton dalam permainan kekuasaan. Partai semacam ini tidak berjuang demi kursi, tapi demi kesadaran. Ia tidak mengejar kemenangan elektoral, melainkan membangun solidaritas di antara mereka yang tertindas. Partai yang tidak memobilisasi rakyat untuk kepentingan sesaat, tapi mengorganisir mereka agar sadar, kuat, dan mampu mengatur nasibnya sendiri.
Bagi Soekarno, partai adalah obor yang menyinari jalan gelap rakyat, mengorganisir kekuatan mereka, memimpin massa untuk merebahkan musuh, dan memberi kesadaran maupun keradikalan dalam perjuangan. Oleh karena itu, partai tidak boleh pragmatis atau kompromistis, tetapi harus menjadi partai yang bewust, sadar, dan radikal, karena hanya partai yang sadar dan radikal yang dapat melahirkan massa yang sadar dan radikal pula.
Masalahnya, hukum di Indonesia justru jadi penghalang utama buat lahirnya oposisi macam itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan aturan Pemilu bikin syarat partai baru begitu berat. Belum lagi proses verifikasi yang rumit dan ambang batas parlemen yang tinggi. Semua itu bikin politik dikuasai partai-partai besar yang punya uang dan jaringan, sementara partai kecil yang tumbuh dari rakyat tersingkir dari awal.
Akhirnya, politik kita cuma jadi milik segelintir orang. Rakyat yang ingin membangun kekuatannya sendiri tak punya jalan masuk. Hukum yang seharusnya melindungi justru jadi pagar pembatas. Dan disitulah, benih oposisi rakyat sulit sekali tumbuh.
Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran bersama untuk membangun kekuatan politik di luar demokrasi formal. Buruh, tani, mahasiswa, perempuan, dan kelas menengah progresif harus bersatu menolak kooptasi politik dan menghidupkan kembali peran rakyat sebagai subjek sejarah. Dari situ bisa lahir oposisi sejati yang tidak mengejar kekuasaan, tapi memperjuangkan pembebasan rakyat.
Di tengah fasisme yang pelan-pelan merayap lewat militerisasi ruang sipil dan pembungkaman suara, membangun kekuatan rakyat jadi satu hal yang tak bisa ditunda. Oposisi bukan lagi sekadar urusan politik, tapi soal keberanian menjaga martabat dan kedaulatan. Kalau Soekarno hidup hari ini, mungkin ia akan bilang: demokrasi bukan untuk dipajang, tapi untuk dipakai melawan penindasan.
Dan dari kesadaran itu pula menurut kami, harus lahir Partai Politik Alternatif Kaum Marhaen yaitu sebuah wadah yang bukan dibangun dari ambisi elektoral, tapi dari kesadaran kolektif rakyat marhaen untuk mengorganisir diri. Partai ini harus berangkat dari prinsip kemandirian ekonomi, pendidikan politik yang membebaskan, dan solidaritas lintas sektor rakyat. Ia tidak boleh tunduk pada logika kapital, melainkan mengakar di kampung, pabrik, dan kampus.
Partai alternatif marhaen bukan sekadar partai, melainkan sekolah politik rakyat tempat di mana kesadaran tumbuh, di mana buruh dan tani belajar memimpin dirinya sendiri, dimana mahasiswa tak hanya bicara perubahan sejarah tapi menjadi bagian darinya. Di tengah tatanan yang semakin menindas, partai semacam ini menjadi simbol perlawanan: menolak tunduk, menolak diam, dan berani merebut kembali politik dari tangan elite.
Sebab seperti kata Bung Karno, “Marhaenisme adalah pelaksanaan sosialisme yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.” Maka tugas kita hari ini bukan sekadar melestarikan warisan itu, tapi menghidupkannya kembali dengan cara membangun partai pelopor perubahan, partai kaum marhaen, partai yang lahir dari rahim penderitaan rakyat dan berdiri tegak demi tercapainya sosialisme Indonesia.***
Penulis: Dhiva Trenadi Pramudia, Institut Marhaenisme 27.