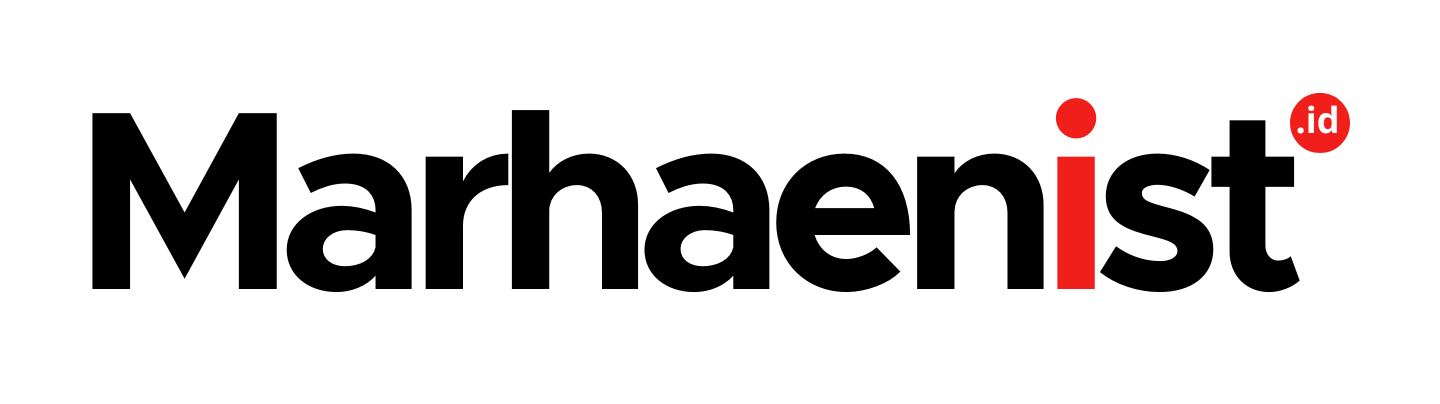Marhaenist.id – Pada akhir 2019, ketika saya berkesempatan mengunjungi Kanada untuk mempelajari gerakan koperasi di sana, satu lembaga langsung mencuri perhatian saya. Namanya Desjardins Bank. Sebuah raksasa keuangan yang sepenuhnya dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Kantor pusatnya berdiri megah di jantung Montreal, simbol bahwa ekonomi rakyat pun bisa berdiri setara, bahkan menandingi, lembaga finansial kapitalis paling mapan sekalipun.
Hari ini, Desjardins mengelola aset sekitar Rp4.735 triliun, memiliki 7 juta anggota pemilik, dan beroperasi di 1.030 kantor pelayanan. Jika dibandingkan dengan BRI, aset Desjardins dua setengah kali lebih besar. Namun dari sisi jangkauan, BRI unggul jauh: 70 juta nasabah dan 7.422 kantor cabang. Potensi raksasa ekonomi rakyat bernama BRI ini sebetulnya tidak tertandingi jika saja ia benar-benar menjadi badan usaha koperasi milik rakyat.
Hanya sayang, perbandingan sejarahnya walaupun BRI dan Desjardins sebenarnya lahir dari rahim ide koperasi yang sama, kini sudah jauh berbeda. Bedanya, Bank Desjardins di Kanada ide itu ditumbuhkan menjadi ekonomi milik rakyat, sementara di Indonesia, kolonialisme memotong batangnya sebelum sempat berkembang sebagai koperasi.
Asisten Residen Purwokerto, De Wolff van Westerrode, pada 1895 mengusulkan pembentukan koperasi kredit sebagaimana yang ia pelajari dari Eropa. Tetapi Menteri Hindia Belanda, Cremer, melarangnya. Bukan karena koperasi itu buruk, melainkan terlalu berbahaya bagi kepentingan kolonial. Koperasi dianggap akan menumbuhkan kemandirian ekonomi pribumi, dan pada akhirnya melahirkan kedaulatan politik. Demi meredam bahaya “rakyat mandiri”, pemerintah kolonial merombak gagasan itu menjadi Hulp Spaarbank, sebuah bank berbantuan yang dikendalikan pemerintah Kolonial.
Tabungan masyarakat yang baru terkumpul 0,1 juta florin dikembalikan. Pemerintah lalu mengelontorkan dana besar sebanyak 318 juta florin dana negara untuk mengoposisinya (Furnivall, 1938). Sejak saat itu, arah sejarah berubah.
Lembaga yang seharusnya menjadi alat kebangkitan ekonomi rakyat justru menjadi instrumen kekuasaan negara, dan kemudian menjadi instrumen kapital pasar modern. Oleh karena itu, ketika Desjardins tumbuh menjadi bank koperasi terbesar di Amerika Utara, BRI justru bergerak semakin jauh dari akar koperasinya. Masyarakat tidak pernah menjadi pemilik; mereka hanya menjadi nasabah, objek pemasaran produk. Keuntungan triliunan rupiah mengalir ke kas negara, lalu ke pemegang saham publik yang kini sebagian besar adalah investor asing.
Bandingkan dengan Desjardins: setiap dolar keuntungan kembali ke pemilik yang jadi nasabahnya sendiri. Struktur kelembagaan yang adil ini melahirkan stabilitas sosial dan kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Bahkan menginspirasi lahirnya raksasa koperasi lain di sektor keuangan di Kanada seperti Vancity Credit Union dan Coast Capital.
Sementara di Indonesia, kebijakan negara bahkan secara sistematis mendiskreditkan koperasi. Semua fasilitas istimewa diberikan kepada bank-bank besar seperti penjaminan simpanan, subsidi bunga, dana penempatan, modal penyertaan, talangan likuiditas, supervisi ahli, bahkan pentalangan (bailout) ketika kehilangan likuiditas. Untuk Koperasi? Tidak mendapatkan satupun keistimewaan kebijakan di atas. Tidak mengherankan bila sektor koperasi keuangan mandek, sementara konglomerasi perbankan tumbuh.
Akibatnya, rakyat Indonesia semakin digiring masuk ke sistem keuangan kapitalis secara monokultur yang menjadikan mereka hanya sebagai nasabah seumur hidup, bukan pemilik. Keuntungan bank tidak kembali kepada mereka; justru banyak yang terjerat utang konsumtif. Sistem ini akhirnya turut memperlebar jurang antara segelintir elite kaya dan mayoritas rakyat.
Di titik ini, pertanyaan kuncinya sederhana namun fundamental:
Mengapa lembaga sebesar BRI tidak dikembalikan saja kepada rakyatnya sendiri?
BRI masih dikuasai pemerintah melalui BPI Danantara. Artinya, peluang untuk melakukan rekonfigurasi institusional masih sangat terbuka. Andaikan pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, langkah paling progresif dan revolusioner adalah mengubah BRI menjadi bank koperasi—persis seperti Desjardins.
Bayangkan transformasinya:
70 juta warga negara Indonesia menjadi pemilik sah BRI. Bukan sekadar pemilik nomor rekening, tetapi menjadi pemilik bank dengan hak suara. Keuntungan bank triliunan rupiah tiap tahun mengalir kembali ke kantong rakyat. Kebijakan kredit dan program pemberdayaan ekonomi diputuskan oleh rakyat sendiri.
Setiap kantor cabang menjadi ruang demokrasi ekonomi lokal. BRI tidak lagi menjadi mesin akumulasi untuk investor asing atau elite pemegang saham, tetapi menjadi mesin kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.
Kakek Presiden Prabowo, Margono Djojohadikusumo, menyebut De Wolff sebagai Bapak Perintis Koperasi Indonesia. Ia sendiri merupakan salah satu kurator atau dewan penyantun Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (Credit Union) tahun 1970 an bersama tokoh lainya seperti Mochtar Lubis, Ibnoe Soedjono, Pater Albrecht Kariem Arbie, Fuad Hasan yang hingga kini terbukti sukses karena tetap dimiliki nasabahnya. Maka, gagasan penyerahan kepemilikan BRI kepada rakyat bukanlah lompatan liar, justru sebagai upaya mengembalikanya ke akar sejarah yang pernah dirintis oleh para pendiri bangsa.
Oleh karena itu saya membayangkan, andaikan Presiden Prabowo mau melanjutkan pemikiran Kakeknya, dan berani melakukan penyerahan (imbreng) asset BRI sebagaimana para pemimpin sebelumnya berani menyerahkan BUMN strategis kepada elite kaya melalui privatisasi, maka kebijakan itu akan mengguncang republik ini, bahkan mengguncang dunia. Sebuah langkah yang tidak hanya memulihkan martabat rakyat, tetapi mengubah struktur ekonomi Indonesia secara mendasar. Mungkinkah?***
Penulis: Suroto, Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis), Alumni GMNI.