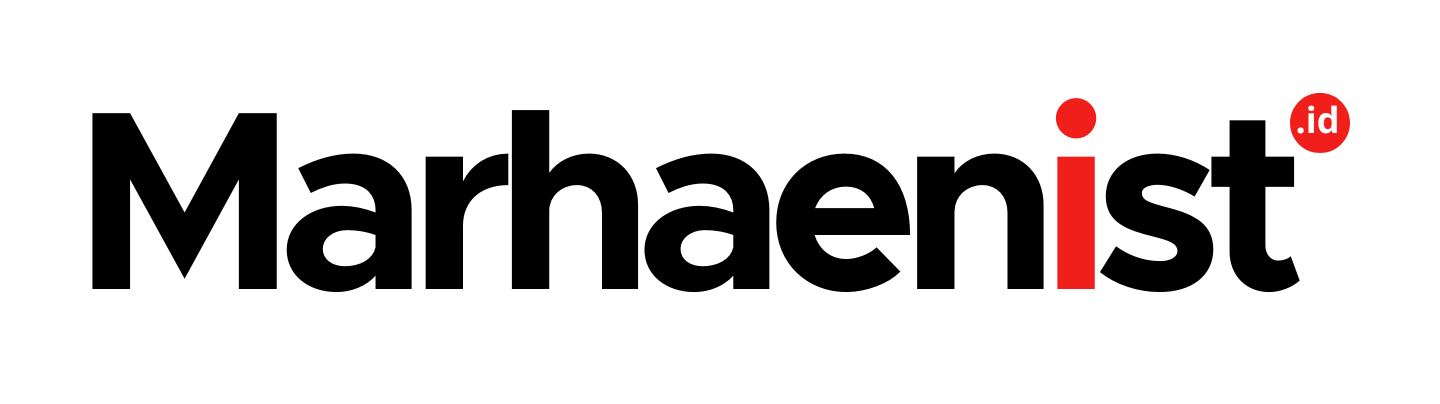Marhaenist.id – Diskursus mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat seiring menguatnya kekhawatiran publik bahwa lembaga legislatif berpotensi menjadi ruang akumulasi kekuasaan tanpa batas. Hingga hari ini, masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD masih tidak dibatasi kemungkinan dipilihnya kembali. Artinya, siapa pun yang telah menjabat dapat terus duduk sebagai anggota legislatif selama ia mampu mempertahankan kursinya lewat pemilu. Secara yuridis, ketentuan ini bersandar pada Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang hanya mengatur bahwa masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun,
tanpa menyebutkan batasan periode.
Situasi ini telah berulang kali dipersoalkan melalui jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon umumnya berargumen bahwa ketiadaan pembatasan periode jabatan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional warga negara yang menjunjung persamaan hak dan kesempatan politik yang setara. Namun hingga kini, Mahkamah Konstitusi belum pernah mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian, posisi hukum kita masih mengakui kemungkinan masa jabatan legislatif yang tak terbatas.
Ketidakterbatasan masa jabatan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait konsentrasi kekuasaan. Hal ini kontras dengan pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tegas dibatasi maksimal dua periode sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945. Pembatasan tersebut lahir dari kesadaran historis bangsa ini atas bahaya kekuasaan yang terlalu panjang dan terlalu besar, yang pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi otoritarianisme yang dibungkus stabilitas. Jika eksekutif dibatasi demi mencegah tirani, maka logika yang sama seharusnya juga berlaku bagi legislatif.
Banyak negara demokratis telah menerapkan pembatasan jabatan untuk parlemen. Kosta Rika, misalnya, membatasi periode anggota legislatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan membuka akses politik bagi warga negara yang lebih luas. Bolivia menerapkan formula serupa dengan tujuan menyeimbangkan dinamika politik dan mendorong regenerasi. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan bukan sesuatu yang asing dalam demokrasi modern; sebaliknya, ia merupakan mekanisme penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak menjadi ruang yang tertutup.
Sejarah panjang pemikiran politik memberi peringatan tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Lord Acton pernah mengingatkan, “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely.” Ungkapan ini bukan sekadar retorika, tetapi refleksi mendalam bahwa kekuasaan yang terlalu lama di tangan kelompok yang sama akan cenderung menumpuk kepentingannya sendiri, sering kali dengan biaya yang ditanggung publik. Dalam konteks DPR, tanpa pembatasan periode, lembaga ini berpotensi menjadi tempat bagi oligarki politik untuk berakar dan menguat. Seseorang atau kelompok tertentu dapat mendominasi proses legislasi selama puluhan tahun, bahkan seumur hidup, selama mereka
tetap terpilih.
Di sinilah relevansi pemikiran Gustav Radbruch, yang menyebut bahwa hukum idealnya mencerminkan tiga tujuan besar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika kita melihat absennya pembatasan masa jabatan DPR, ketiga tujuan ini justru tergerus. Keadilan terganggu karena kesempatan politik menjadi timpang; mereka yang sudah kuat secara
elektoral semakin mudah mempertahankan posisinya, sementara wajah-wajah baru sulit menembus sistem. Dari perspektif kemanfaatan, DPR yang dihuni orang-orang yang sama
dalam jangka panjang berpotensi kehilangan kesegaran ide dan semangat perubahan. Dan dari sisi kepastian hukum, siklus kekuasaan yang tanpa batas membuat proses politik menjadi terlalu bergantung pada kontinuitas individu, bukan pada institusi yang sehat.
Masalah ini semakin kompleks ketika kita memeriksa kondisi internal partai politik sebagai sumber utama rekrutmen para legislator. Partai politik di Indonesia umum digambarkan memiliki problem laten berupa praktek oligarki internal. Tidak sedikit partai yang dikelola seperti milik pribadi atau keluarga, sehingga keputusan-keputusan strategis terpusat pada segelintir elite. Selama tidak ada pembatasan masa jabatan legislatif, praktek oligarki partai berpeluang besar untuk terus hidup dan bahkan menguat. Para elite partai dapatmemastikan bahwa orang-orang dekat, loyalis, atau bahkan kerabat mereka menempati kursi legislatif secara terus-menerus. Dalam kondisi seperti ini, parlemen berisiko menjadi perpanjangan tangan oligarki partai, bukan wakil rakyat secara substantif.
Partai politik yang oligarkis cenderung menutup ruang bagi regenerasi. Figur-figur baru yang memiliki integritas, kapasitas, dan gagasan segar sering kali sulit menembus struktur kekuasaan internal karena dianggap mengganggu kenyamanan status quo. Mekanisme pemilu pun tidak sepenuhnya dapat mengoreksi ini, sebab hasil akhir masih banya dipengaruhi struktur internal partai dalam menentukan siapa yang diberi peluang maju.
Tanpa pembatasan periode, sistem ini akan terus berulang dan mengakar dari pemilu ke pemilu. Maka, pembatasan masa jabatan bukan hanya upaya untuk memutus rantai kekuasaan yang terlalu panjang, tetapi juga untuk memulihkan dinamika politik yang sehat. Pembatasan periode akan menciptakan sirkulasi kepemimpinan yang lebih teratur. Ini membuka ruang regenerasi bagi politisi muda, profesional, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan masuk dalam arena politik yang dikontrol elite. Dari sisi publik, pembatasan periode juga dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPR. Mereka yang tahu bahwa masa pengabdiannya dibatasi cenderung lebih fokus meninggalkan legacy yang baik daripada sekadar mempertahankan kursi tanpa batas.
Secara yuridis, pembatasan masa jabatan DPR juga dapat memperkuat tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Radbruch. Keadilan terwujud karena setiap warga negara memiliki peluang yang lebih seimbang untuk berpartisipasi. Kemanfaatan tercapai karena parlemen dapat terus diperbarui dengan energi, ide, dan perspektif baru. Sementara kepastian hukum diwujudkan melalui aturan yang memberi batas waktu yang jelas bagi setiap legislator, sehingga siklus politik menjadi lebih tertata dan sehat.
Pada akhirnya, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang membuka ruang bagi kebaruan, tidak hanya mempertahankan mereka yang sudah lama berkuasa. Pembatasan masa jabatan anggota DPR adalah langkah mendasar untuk menjaga agar parlemen tetap menjadi institusi yang hidup, dinamis, akuntabel, dan benar-benar mewakili rakyat. Tanpa langkah ini, risiko oligarki politik akan terus membayangi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat terus menurun. Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang tentang bahaya kekuasaan yang tanpa batas. Maka, pembatasan masa jabatan DPR bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan masa depan demokrasi yang lebih sehat, terbuka, dan adil bagi semua.***
Penulis: Rendy Rizaldy Putra, S. Pd, Mantan Sekretaris GMNI DIY 2022-2024.