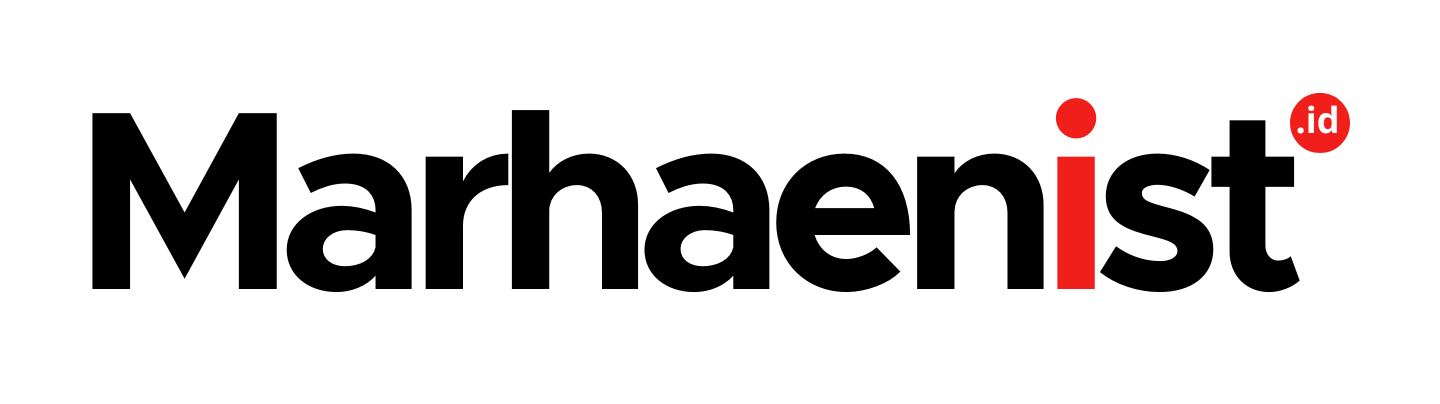Marhaenist.id – Isu penganugerahan Pahlawan Nasional untuk Soeharto memang sering menimbulkan perdebatan di Indonesia. Namun ada beberapa alasan mengapa banyak pihak menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto termasuk pengagum Bung Karno dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), meskipun sebagian orang mengatakan bahwa ia juga punya jasa tertentu bagi pembangunan Indonesia.
Asalan Menolak Gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto Secara Umum
Berikut alasan penolakannya secara umum, berdasarkan sudut pandang historis, moral, dan hukum:
1. Pelanggaran HAM Berat
Soeharto dianggap bertanggung jawab (langsung maupun tidak langsung) atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
Pemberian gelar pahlawan itu juga akan mengaburkan sejumlah catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi sepanjang masa Orde Baru.
Soeharto secara spesifik disebut dalam TAP MPR 11/1998 atas perlakuan nepotisme dan tindakan korupsi. TAP MPR itu mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia.
Menurut catatan yang diambil dari Kompas dan beberapa media lainnya, terdapat beberapa kejahatan kemanusiaan yang terjadi saat Soeharto memimpin, antara lain:
Pertama, kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985 dengan perintah langsung Soeharto untuk menghukum mati para bromocorah hingga preman tanpa proses peradilan.
Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat bahwa korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung.
Kedua, peristiwa Tanjung Priok 1984-1987. Soeharto disebut menggunakan militer sebagai instrumen kebijakan politiknya. Akibat dari kebijakan ini, dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih dari 24 orang meninggal, 36 terluka berat, dan 19 luka ringan.
Ketiga, peristiwa Talangsari 1984-1987 yang menyebabkan 130 orang meninggal, 77 orang mengalami pengusiran paksa, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalami penganiayaan.
Keempat, peristiwa 27 Juli 1996 atau lebih dikenal dengan peristiwa Kudatuli yang mencoba mendongkel Megawati sebagai Ketua DPP PDI saat itu.
Peristiwa ini menyebabkan 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Kemudian, ada peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang juga terjadi perkosaan massal, dan penculikan para aktivis.
Kelima, Tragedi 1965–1966: ratusan ribu orang yang dituduh terlibat PKI dibunuh tanpa proses hukum, dan banyak yang ditahan tanpa pengadilan.
Keeman, Penindasan di Timor Timur (1975–1999): invasi dan pendudukan menyebabkan banyak korban sipil dan pelanggaran HAM berat.
Ketujuh, Tragedi Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), hingga Mei 1998: penembakan, penghilangan paksa, dan kekerasan negara terhadap warga sipil.
Dalam konteks hukum dan moral, pahlawan nasional semestinya memiliki rekam jejak kemanusiaan yang bersih — sedangkan Soeharto justru meninggalkan banyak luka sejarah.
2. Korupsi dan Nepotisme
Selama Orde Baru, Soeharto membangun kekuasaan yang sangat sentralistik dan nepotistik.
Keluarganya dan kroni-kroninya mendapatkan monopoli bisnis besar, dari perbankan sampai migas.
Transparency International (2004) bahkan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan korupsi hingga US$ 15–35 miliar.
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang seharusnya mengutamakan kejujuran dan pengabdian pada rakyat.
3. Kekuasaan Otoriter dan Represi Politik
Selama lebih dari 32 tahun berkuasa, Soeharto menjalankan rezim otoriter yang membungkam oposisi politik dan kebebasan berpendapat.
Banyak aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang ditangkap atau diintimidasi karena mengkritik pemerintah.
Demokrasi praktis dibekukan, partai politik dibatasi, dan media disensor ketat.
4. Merekayasa Pemilu Selama 32 Tahun untuk Melanggengkan kekuasaannya
Agar dapat melanggengkan kekuasaannya, Soeharto melalui kekuatan rezim orba selama 32 tahun telah merekayasa pemilu dan hasinya untuk memastikan Golongan Karya (Partai Pemerintah) mendapatkan kemenangan.
Selama 32 Tahun itu pula, Soeharto melalui rezim Orde Baru membuat 2 partai lainya, yakni; PDI dan PPP hanyalah pelengkap demokrasi dalam setiap pemilu.
5. Kriteria Pahlawan Nasional Tidak Terpenuhi
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seorang Pahlawan Nasional harus:
~ Berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
~ Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
~ Mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa.
Banyak kalangan menilai Soeharto tidak memenuhi kriteria ini karena terlibat dalam korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Masih Ada Luka Kolektif di Masyarakat
Bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya, memberi gelar pahlawan kepada Soeharto terasa seperti menghapus penderitaan dan trauma masa lalu.
Rekonsiliasi belum tuntas, dan penghargaan seperti ini bisa memperdalam luka sosial serta menimbulkan ketidakadilan sejarah.
Dosa Soeharto terhadap Bung Karno
Hubungan antara Soeharto dan Soekarno (Bung Karno) memang penuh dinamika, terutama di masa transisi kekuasaan sekitar tahun 1965–1967.
Kalau kita bicara tentang “dosa” Soeharto terhadap Bung Karno, ini bisa dilihat dari berbagai sisi — politik, moral, dan sejarah. Berikut penjelasan ringkas namun mendalam:
1. Mengambil alih kekuasaan secara perlahan
Setelah peristiwa G30S 1965, Soeharto sebagai Panglima Kostrad diberi Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Soekarno.
Tujuannya semula adalah agar Soeharto memulihkan keamanan dan ketertiban.
Namun, Soeharto menggunakan Supersemar sebagai dasar untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap.
Ia membubarkan PKI dan menahan tokoh-tokoh yang dianggap terlibat, tanpa perintah langsung dari Soekarno.
Dalam praktiknya, Soekarno makin kehilangan kendali, hingga akhirnya dicopot dari jabatan presiden melalui Sidang MPRS tahun 1967.
Bagi banyak pendukung Soekarno, ini dianggap sebagai pengkhianatan besar — Soeharto dianggap “menikam dari belakang” sang Proklamator.
2. Menghancurkan warisan politik dan ideologi Soekarno
Soeharto mengganti Orde Lama menjadi Orde Baru, dengan arah politik yang berlawanan:
Soekarno: anti-imperialisme, pro-blok Timur, dan nasionalis revolusioner.
Soeharto: pro-Barat, ekonomi liberal, dan stabilitas di atas segalanya.
Banyak karya, gagasan, dan simbol Soekarno disingkirkan.
Pidato-pidato Soekarno dilarang,
Namanya jarang disebut di sekolah-sekolah pada masa awal Orde Baru,
Dan ia dijauhkan dari publik hingga akhir hayatnya.
3. Menempatkan Soekarno dalam tahanan rumah
Setelah dicopot, Bung Karno tidak diadili secara terbuka, tapi juga tidak dibiarkan bebas.
Ia ditahan secara politik di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala) dan dijaga ketat.
Soekarno mengalami masa tua yang sulit — akses ke keluarga, dokter, dan publik sangat dibatasi.
Ia meninggal dunia pada 21 Juni 1970, dalam kondisi terisolasi dan tanpa penghormatan kenegaraan layak pada saat itu.
Bagi banyak sejarawan dan rakyat Indonesia, inilah “dosa terbesar” Soeharto terhadap Bung Karno — memperlakukan sang Proklamator dengan cara yang dianggap tidak manusiawi.
4. Menghapus narasi sejarah versi Soekarno
Di era Orde Baru, sejarah versi pemerintah didominasi oleh narasi Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari komunisme,
sementara Soekarno digambarkan ambigu terhadap PKI.
Buku-buku sejarah sekolah dikontrol ketat untuk menonjolkan peran Soeharto dan mengecilkan kontribusi Soekarno pasca-1965.
Dosa Soeharto terhadap GMNI
Dizamannya, Rezim Orde Baru menekan, menyelewengkan, dan bahkan memecah organisasi yang dulu menjadi bagian penting dari gerakan nasionalis Soekarnois.
GMNI didirikan tahun 1954, berasaskan Marhaenisme — ajaran Bung Karno tentang perjuangan kaum kecil dan nasionalisme Indonesia.
Di era Soekarno (Orde Lama), GMNI termasuk organisasi mahasiswa yang dekat dengan kekuasaan dan menjadi bagian dari Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).
Namun setelah peristiwa G30S 1965, dan terutama setelah Soeharto naik, posisi GMNI langsung jadi sasaran represi.
2. Soeharto menuduh GMNI dekat dengan PKI
Karena GMNI pro-Soekarno dan mendukung konsep Nasakom, maka Orde Baru menuduhnya terpengaruh ideologi kiri/komunis.
Banyak kader GMNI ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh, terutama di daerah-daerah yang dianggap “basis kiri”.
Kampus-kampus “dibersihkan” dari unsur-unsur mahasiswa yang dianggap simpatisan Soekarno atau PKI — termasuk dari GMNI.
Nama GMNI sempat dibekukan secara tidak resmi di banyak universitas karena dicurigai tidak loyal pada Orde Baru.
Dosa pertama Soeharto terhadap GMNI: stigmatisasi dan pembantaian terhadap kader nasionalis Soekarnois.
3. Pemecahan GMNI dari dalam
Soeharto dan aparat intelijen Orde Baru mendorong perpecahan internal GMNI agar organisasi itu melemah.
Terjadi dua faksi besar:
1. GMNI Soekarnois/GMNI Asli — setia pada ajaran Marhaenisme dan Soekarno.
2. GMNI Pancasila/GMNI Moderat — lebih kompromis.
Sebagian orang berpendapat bahwa Soeharto juga punya jasa pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan keberhasilan di awal masa jabatannya. Namun, banyak sejarawan menilai jasa itu tidak bisa menutupi kerusakan sosial, politik, dan moral yang ditinggalkan.
Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan sejarahnya, tetapi menegaskan bahwa gelar kepahlawanan harus diberikan pada sosok yang benar-benar menjunjung nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan.***
Penyusun: La Ode Mustawwadhaar/Disclaimer: Tulisan ini diambil dari berbagai macam sumber yang terpercaya.