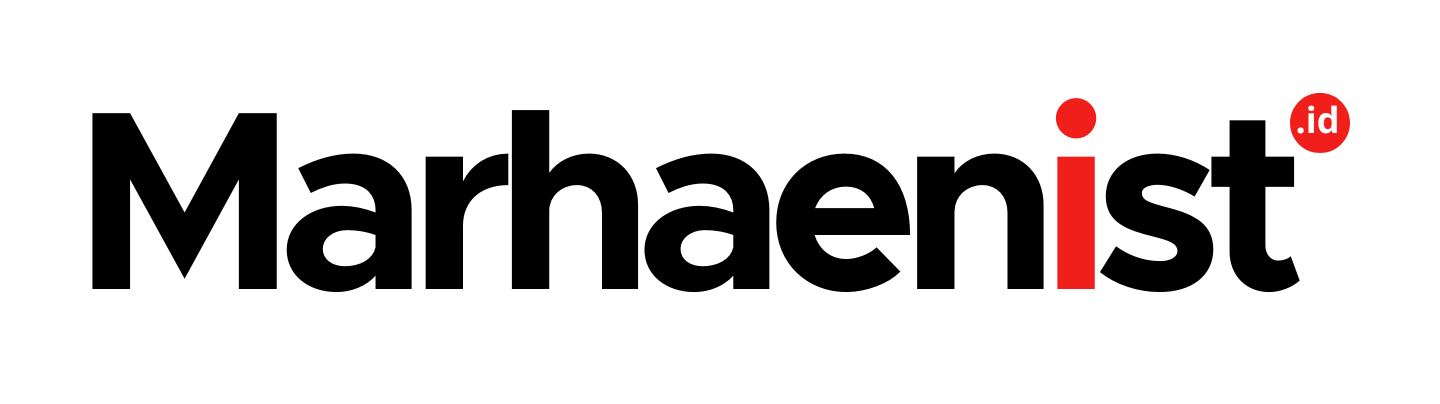Marhaenist.id – Ditengah gelombang tanda tanya dikalangan pengusaha perihal logo HUT ke 80 republik Indonesia yang tak kunjung keluar padahal sudah tinggal beberapa minggu lagi menuju kemerdekaan.
Nyatanya perayaan kemerdekaan yang sebentar lagi kita sambut dengan gegap gempita itu belum bisa memberi kita kemerdekaan 100 % sebagaimana harap Tan Malaka dan para founding father-mother (agar tidak bias gender) lainnya yang mungkin saja kualitas mereka tidak sebanding dengan trio GBL (Gibran, Bahlil, dan Luhut) yang hari ini sedang menahkodai Indonesia menuju 2045 dengan campuran emas, nikel, Timah, Batubara, dan serangkaian klarifikasi.
Kemerdekaan yang saya maksud disini bukan semata-mata pembebasan dari bangsa asing berserta anteknya yang dikhawatirkan oleh bapak presiden kita yang gemoy itu tetapi juga pembebasan dari penindasan oleh sesama bangsa sendiri, Bung karno pernah berujar tentang kemerdekaan yang di idealkannya dalam Pidato berjudul “Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit Jalannya Revolusi Kita yang disampaikannya pada peringatan kemerdekaan tahun 1960 di Jakarta yang termuat dalam DBR jilid 2 dengan kondisi “yang Merdeka-Penuh, Makmur-Penuh, Adil-Penuh, Damai-Penuh, Sejahtera-Penuh, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat, dan sesuai dengan ujaran-ujaran nénék-moyang kita: “gemah-ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja!”
Ironisnya menjelang ultahnya yang ke 80 , Republik yang kita harapkan tetap ada selama-lamanya ini masih diselubungi oleh eksistensi aliansi yang menindas dalam bentuk premanisme yang terstruktur, massif, dan sistematis masih eksis dan selalu berkelindan dalam simbiosis parasitik (hubungan yang merugikan) bersama penguasa yang tetap memberi derita di kalangan rakyat
Persis seperti yang diungkap Ian Douglas dalam politik jatah preman dimana reformasi politik pasca 1998 ternyata tidak memutus tali pusar kekuasaan preman sebagai bentuk informal dari penindasan oleh kelas penguasa terhadap rakyat.
Pasca reformasi memang sempat muncul harapan baru akan Indonesia yang lebih baik namun dengan adanya demokrasi yang prosedural yang dirayakan dengan pembagian kaos, serangan fajar, dan memainkan identitas SARA itu justru semakin membuat peran preman semakin menguat karena bagi penguasa kehadiran preman dianggap mampu menentukan dan mengamankan kemenangan.
Praktik premanisme dalam proses demokrasi di Indonesia menjadi wajar apalagi landskap perpolitikan di Indonesia masih didominasi permainan politik massa yang hanya berdasarkan pada kuantitas mengambang yang diselubungi dengan ketidaksadaran terhadap hal-hal yang esensial dari proses demokrasi itu sendiri termasuk melawan premanisme itu sendiri.
Premanisme di Indonesia: Berguna Dimasa Chaos, Malapetaka di Masa Damai
Membahas tentang premanisme tidak lengkap jika tidak menelisik sejarah tentang premanisme sendiri Indonesia yang sudah ada sejak zaman kolonial, baik Belanda maupun jepang di mana kelompok seperti heibo (pembantu polisi) jepang dan centeng perkebunan Hindia Belanda menjadi cikal bakal praktik premanisme sebagai alat pengendalian sosial dan ekonomi. Pasca-kemerdekaan, fenomena ini berkembang kompleks, di era 1945-1960-an, banyak bekas laskar revolusi beralih menjadi preman lokal yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan, sementara pada masa Orde Baru (1966-1998) preman secara sistematis dikooptasi dan diorganisir sebagai instrumen kekuasaan untuk represi politik terutama saat tragedi 1965, penguasaan ekonomi, dan kontrol sosial sehingga menciptakan dualisme fungsi sebagai pelaku kriminal sekaligus alat negara.
Meskipun pada masa-masa kemerdekaan kehadiran para preman atau kaum jago turut serta berjuang melawan kolonialis & imperialis sebagaimana yang ditulis oleh Robert Cribb dalam bukunya para jago dan kaum revolusioner Jakarta 1945-1949.
Dari secuil fakta tadi jika kaitkan dengan perkataan Yusuf Kala pada tahun 2012 silam saat menghadiri acara Tentara orange yang menyatakan Preman yang berasal dari akar kata Freeman atau manusia bebas yang kehadirannya layak dipuji karena sifat aslinya ialah melindungi kampung sendiri dari ancaman kampung lain seakan-akan menemukan pembenarannya.
Meskipun sifat yang katanya asli itu, akan berubah 180 derajat menjadi malapetaka dalam bentuk ekstrimnya berupa budaya centeng yang bisa menjadi cara negara dalam mengelola kehidupan berbangsanya dengan basis yang mengakumulasi modal untuk segelintir pihak, menormalkan konflik, menolak kompromi, mengabaikan akal dan nurani, serta berupaya untuk memperkuat kuasa absolut satu eksponen sehingga tidak ada ruang bagi berlakunya prosedur-prosedur demokrasi yang saling mengoreksi sebagaimana tulis Wibowo dalam Negara centeng :Negara dan saudara di era globalisasi.
Dari Negara Centeng menuju Dystopia Orwellian
Tak pelak, kondisi ini makin mendekatkan kita pada distopia Orwellian yang dulu hanya menjadi bahan bacaan. Dalam novel 1984, George Orwell melukiskan bagaimana sebuah rezim mampu menciptakan masyarakat yang dikendalikan oleh bahasa manipulatif, teror psikologis, dan kebingungan kolektif.
Secara sederhana karakter dari Distopia Orwellian merujuk pada masyarakat fiktif yang distopis (anti-utopia) sebagaimana tertulis dalam novel George Orwell, terutama *1984*, yang dicirikan oleh pengawasan totaliter, manipulasi kebenaran, penindasan kebebasan individu, dan kontrol pikiran melalui propaganda sistematis. Martabat manusia kemudian direduksi menjadi debu di bawah sepatu penguasa dengan privasi, cinta, kebebasan,keamanan, bahkan bahasa itu sendiri dilenyapkan, digantikan oleh konformitas yang nihil makna.
Distopia orwelian sebenarnya adalah gambaran masa depan yang selaras dengan yang diistilahkan bung Karno dengan “exploitation de l’homme par l’homme” penindasan manusia ke atas Manusia lainnya.
Lalu apa hubungannya Distopia Orwellian ini dengan premanisme ? , untuk menjawab ini mari kita memakai perspektif Marxist , dari perpektif Marxist pada dasarnya menawarkan analisis untuk menelanjangi kekacauan dari dystopia Orwellian. Dalam kapitalisme pinggiran seperti yang terjadi diIndonesia, yang berlaku dikawasan yang jauh dari pusat ekonomi utama, seperti kawasan-kawasan penduduk yang melibatkan kompetisi, eksploitasi sumber daya, dan pencarian keuntungan, tetapi dengan cara yang lebih sederhana atau tidak formal itu . biasanya akumulasi modal tak hanya bergantung pada penguasaan alat produksi, tetapi juga pada pengendalian kekerasan simbolik. Preman dan influencer politik sama-sama menjalankan fungsi mendasar yaitu memastikan tak seorang pun menentang logika pasar dan kekuasaan yang menindas.
Kelas borjuis lokal, yang dulunya berkoar-koar soal kedaulatan, ternyata hanya menggantikan penjajah asing dengan rezim domestik yang serupa rakus dan lebih lihai dalam menjual kebohongan dan melenggengkan penindasan manusia ke atas manusia lainnya.
Itulah mengapa republik ini pelan-pelan berubah menjadi Pasar Pertikaian, dimana menjadi tempat kekuasaan dilelang kepada penawar tertinggi, kebohongan diperjualbelikan bak saham gorengan, dan kekerasan menjadi alat tawar-menawar yang sah yang praktiknya sendiri dilakukan oleh sesama warga negara yang sudah terjebak dalam isme-nya preman.
Dan kita, rakyat yang konon pernah merdeka, kini dipaksa beradaptasi. Seperti kawanan domba yang sudah lupa rupa rumput asli, kita menerima absurditas sebagai kewajaran. Mungkin beginilah babak terbaru ironi republik ini, saat bangsa yang katanya berdaulat rela menjadi penonton dalam opera kekuasaan yang digarap oligarki, disponsori para kaum jago , dibela oleh para buzzer, dan diiringi koor rakyat yang sudah terlalu letih untuk marah atau bahkan takut untuk mengekpresikan amarahnya
Kalau sudah begini lalu apa solusinya ? kiranya nasehat bung karno soal kemutlakan dan kesadaran perjuangan kemerdekana perlu kita internalisasi dalam praktik sekecil apapun itu dalam konteks kemutlakan perjuangan, Bung Karno dalam pidatonya berjudul Re – So – Pim; Revolusi–Sosialisme Indonesia–Pimpinan Nasional yang disampaikan pada ulang tahun Proklamasi 17 agustus 1961 di Jakarta yang termuat dalam DBR jilid 2 mengingat agar “Kita mutlak berdiri di fihak menyelamatkan Negara-Kesatuan, mutlak hendak kembali kepada Kepribadian sendiri, mutlak berdiri di fihak merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan, mutlak berdiri di fihak memperjoangkan satu Dunia Baru, social justice dan political justice, untuk segala bangsa. Nasional kita bersikap sintetis menyelamatkan Kesatuan Negara dan menyelamatkan kepribadian nasional serta merealisasikan keadilan nasional”.
Sementara pada soal kesadaran juga dalam Re – So – Pim; Revolusi–Sosialisme Indonesia–Pimpinan Nasional , Bung karno mengingatkan jika kesadaran itu “merupakan sumber utama daripada pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. Kesadaran inilah merupakan sumber maha-agung yang mendeburkan sosialisme Indonesia. Kesadaran inilah merupakan sumber Tirta-Kencana yang memancurkan Manipol-USDEK, yang sekarang sedang kita laksanakan dan pertumbuhkan.
Kesadaran inilah dapat kita pakai sebagai sumber untuk menghindari dan menghantam penyeléwéngan-penyeléwéngan secara besar-besaran, atau untuk mengkoreksi penyeléwéngan secara kecil-kecilan yang kadang-kadang terjadi di sana-sini. Kesadaran inilah dapat dipakai untuk mengetahui (onderkennen) penyeléwéngan –penyeléwéngan besar di masa yang lampau, yang hampir saja membawa Republik ke dalam
Kehancuran. Kesadaran inilah dapat dipakai sebagai perisai-jiwa, agar kita tidak jatuh lagi ke dalam ulangan penjeléwéngan-penjeléwéngan tadi. Dan, – ini penting! -, kesadaran inilah dapat dipakai sebagai sumber-ilham, sumberfikiran, sumber-tekad, sumber-tenaga, untuk memberikan sumbangan positif dalam memperkembang-kan konsepsi-konsepsi baru dalam Penghidupan Nasional kita yang sekarang sedang tumbuh-hebat dan kita pertumbuhkan itu”.***
Penulis: Mansurni Abadi, Pengurus DPLN PDIP Malaysia.