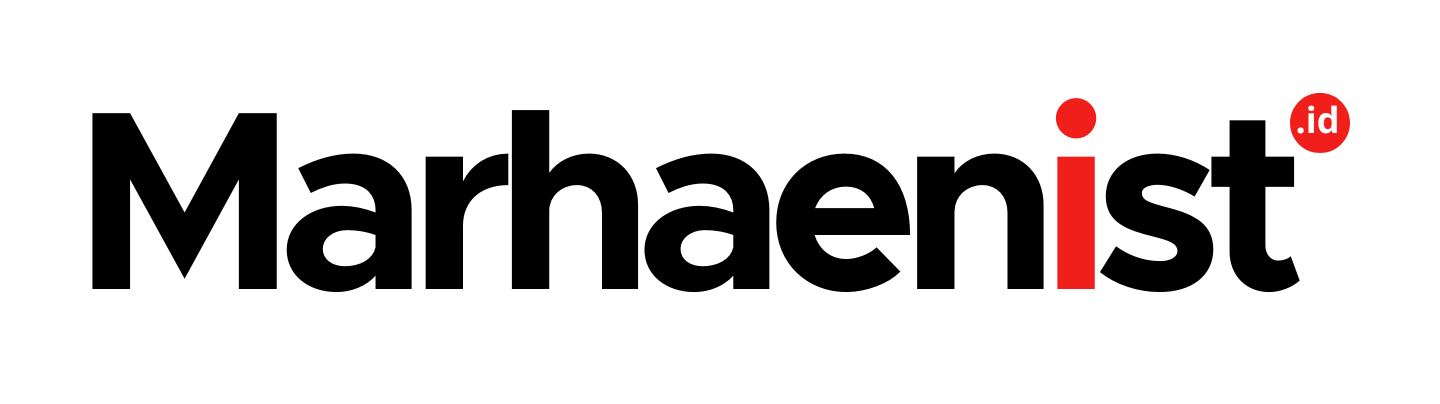Marhaenist.id – Kita hidup dalam masa ketika perhatian manusia menjadi komoditas paling berharga di dunia. Sejarah kapitalisme selalu menemukan tubuh baru untuk dieksploitasi, dulu otot kini ruang pikir, yaitu cara kita memahami realitas sebelum tindakan aktual dilakukan.
Di abad industri modal menambang tenaga fisik, di abad digital ia menambang atensi, waktu, dan emosi sebagai basis dari sumber daya sistem. Setiap kali klik dilakukan, setiap kali tatapan tertuju ke layar, setiap kali dorongan kecil untuk scrolling (menggulir konten pada layar perangkat digital, biasanya di media sosial atau website) muncul, adalah bentuk kerja yang tak kasatmata dalam menopang ekonomi raksasa bernilai triliunan dolar.
Apa yang tampak sebagai kebebasan untuk terhubung sebenarnya adalah integrasi manusia ke dalam sirkuit kapital digital yang lebih luas, di mana kesadaran menjadi sumber daya yang paling langka sekaligus paling rentan dieksploitasi.
Kapitalisme digital sebagaimana diungkapkan oleh para ekonom Perserikatan Bangsa Bangsa telah memperluas logika akumulasi hingga ke wilayah di mana proses dan hasil berpikir manusia direduksi menjadi disposisi yang dikendalikan oleh kuasa algoritma. Proses yang dulu disebut compression of space and time (pemadatan ruang dan waktu dalam konteks ekonomi dan komunikasi global) kini melampaui batasnya, di mana ruang digital melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi sirkulasi modal sekaligus memperluas kontrol sosial melalui skema ekosistem informasi yang digulirkan oleh platform digital berbasis personalisasi pengguna.
Internet, media sosial, dan algoritma bukan sekadar infrastruktur komunikasi melainkan infrastruktur kekuasaan yang menata ulang hubungan antara manusia, informasi, dan dunia. Kapitalisme tidak lagi hanya menguasai alat produksi tetapi juga alat persepsi.
Dalam sistem ini manusia tidak lagi menjadi pengguna pasif atau sekadar konsumen data melainkan juga produsen nilai yang tidak disadari. Aktivitas paling sederhana seperti menonton video memberi tanda like (tanda persetujuan atau apresiasi pada konten digital) atau menulis komentar diolah menjadi data yang kemudian dijual kembali sebagai prediksi pola perilaku yang dibaca dan diinterpretasikan melalui sistem komputasi yang rigid. Di sinilah muncul bentuk kerja baru yaitu kerja kognitif dan afektif, di mana kapasitas berpikir dan merasakan menjadi sumber nilai ekonomi digital yang dapat dimonetisasi sebagai data.
Kapitalisme digital dengan sistematis mengubah waktu luang menjadi waktu produksi yang bernilai, dieksploitasi melalui layanan gratis (free dalam bahasa Inggris, layanan tanpa biaya uang namun nilai data diambil oleh platform). Setiap detik perhatian adalah detik kerja bernilai sehingga setiap emosi menjadi sumber energi yang dapat dimonetisasi. Dalam istilah Marxian (berkaitan dengan teori Karl Marx) surplus value kini diekstraksi bukan dari tenaga fisik tetapi dari sirkulasi kognisi dan afeksi, bukan hanya objek yang dikomodifikasi tetapi sistem kapitalisme bekerja dengan memodifikasi kesadaran subjek.
Agar mekanisme ini berfungsi secara efektif dibutuhkan sistem yang mampu mengarahkan perilaku manusia tanpa menimbulkan kesan paksaan. Algoritma berperan sebagai instrumen utama dari kekuasaan halus ini sebagai sistem persuasi cerdas, intelligent persuasion system (sistem yang dirancang untuk memengaruhi keputusan dan perilaku secara halus menggunakan teknologi dan psikologi). Tujuannya adalah mengendalikan dimensi bawah sadar dan emosi manusia melalui umpan atau bait (bait dalam konteks digital: rangsangan yang memancing perhatian atau tindakan).
Algoritma tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga membentuk horizon pengalaman, ia menentukan apa yang terlihat, apa yang diabaikan, dan bagaimana sesuatu seharusnya dimaknai. Ia bekerja layaknya arsitek yang merancang ruang pilihan, choice architecture (desain lingkungan keputusan yang memengaruhi pilihan individu tanpa paksaan), di mana setiap keputusan manusia terjadi dalam batas-batas yang telah dikalkulasi untuk mencapai predefined objective (tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya bersifat ekonomi dan terkuantifikasi).
Dalam dunia algoritmik, pilihan bukan lagi kebebasan, melainkan ilusi yang diprogram. Sistem mempelajari pengguna secara terus-menerus melalui membaca, memahami, bahkan menjadi perilaku subjek yang dibacanya sehingga proses kendali bisa dilakukan dengan presisi. Dari informasi ini, mesin membangun profil psikografis (profil psikologis dan perilaku individu yang sangat rinci), membaca keinginan, ketakutan, dan kecenderungan preferensi seseorang. Berdasarkan profil itu, algoritma menyesuaikan arus konten agar setiap individu terikat dalam ruang digitalnya sendiri. Personalisasi, yang tampak seperti pelayanan, sejatinya adalah bentuk domestikasi, di mana setiap pengguna hidup di dalam gelembung kesadaran imitasinya—dinding lembut yang membatasi pandangan namun terasa nyaman.
Arsitektur kekuasaan baru ini beroperasi melalui kendali atas kenikmatan. Tidak ada larangan eksplisit, tidak ada ancaman, hanya rangsangan halus yang menuntun seseorang menuju pemuasan hasratnya. Ia merasa memilih, padahal diarahkan; merasa berpikir bebas, padahal dilingkupi algoritma yang telah menebak langkah berikutnya. Inilah paradoks kebebasan digital: manusia merasa paling otonom justru ketika berada dalam kendali paling kuat. Kebebasan berubah menjadi produk yang dikuratori, bukan kondisi autentik. Bentuk kekuasaan semacam ini jauh lebih efektif daripada paksaan karena bekerja dari dalam kesadaran, sebagai penataan ulang kehendak dan hidup.
Dalam kerangka psikologi kognitif, operasi algoritma menyasar mekanisme terdalam dari pikiran manusia. Daniel Kahneman menjelaskan adanya dua sistem dalam kognisi: sistem pertama yang cepat, intuitif, dan emosional; serta sistem kedua yang lambat, reflektif, dan rasional.
Platform digital dirancang untuk menstimulasi sistem pertama karena sistem ini memunculkan reaksi impulsif seperti klik spontan, kemarahan, rasa ingin tahu, atau ketertarikan instan. Konten emosional lebih mudah memancing interaksi, dan setiap interaksi menghasilkan data yang kemudian dikurasi. Dengan cara ini, algoritma memelihara arus emosi yang tidak stabil, membuat pengguna terus berpindah dari satu rangsangan ke rangsangan lain tanpa ruang refleksi. Pikiran lambat, yaitu sistem kedua, tidak pernah diberi kesempatan untuk bekerja.
Dalam kerangka neuroplastisitas (kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman dan stimulasi), hal ini menormalisasi kegagalan berpikir dalam memahami realitas. Akibatnya, aktivitas berpikir hari ini tidak lagi berlandaskan rasio, melainkan sekadar reaksi terhadap duplikasi informasi bersifat clickbait (konten yang dirancang untuk menarik klik dengan judul atau gambar sensasional tanpa menjamin kualitas informasi).
Di sinilah terbentuk apa yang disebut Dylan White sebagai pre-reflective habit (kebiasaan pra-reflektif: tindakan yang dilakukan sebelum refleksi atau pemikiran kritis muncul), keadaan ketika manusia bertindak sebelum sempat berpikir kompleks dan reflektif. Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan struktur pembentuk kesadaran yang menentukan cara manusia memahami dan bereaksi terhadap otomatisasi konten yang diproduksi platform digital.
Reaksi otomatis menggantikan proses deliberasi; impuls menggantikan niat berorientasi jangka panjang; kebiasaan menggantikan keputusan mediatif untuk menyatu dengan pengetahuan esensial. Perilaku yang tampak bebas sejatinya hasil interaksi antara desain sistem dan dorongan biologis yang diprogram ulang. Manusia, dalam pengertian eksistensial, kehilangan pusat kendali atas dirinya, sehingga tanpa kesadaran reflektif ia perlahan mengalami pembusukan eksistensial tanpa kehendak diri.
Efek sistem ini diperkuat oleh slot machine effect (mekanisme yang meniru mesin judi di mana hadiah diberikan secara acak untuk menciptakan kecanduan), mekanisme yang diadopsi dari dunia perjudian. Notifikasi, likes, dan shares berfungsi sebagai variable rewards (imbalan yang tidak pasti, diberikan secara acak untuk meningkatkan keterlibatan pengguna), imbalan acak yang menyerupai keberuntungan dan memiliki pengaruh kuat secara neuropsikologis. Setiap “hadiah sosial” kecil memicu pelepasan dopamin, menciptakan antisipasi yang mendorong pengulangan perilaku. Inilah dopamine loop (siklus ketagihan dopamin: perilaku yang terus-menerus diulang karena efek kimiawi di otak), siklus ketagihan yang tidak pernah mencapai kepuasan, hanya memperbarui hasrat untuk tetap berada dalam migrasi menuju realitas virtual atau imitasi.
Sama seperti mesin judi, sistem ini tidak menawarkan kepastian kemenangan, melainkan janji kemungkinan yang cukup untuk membuat pemain bertahan. Ketidakpastian menjadi candu bagi hasrat, sementara kepastian kehilangan daya tarik karena tidak memiliki relasi intrinsik yang menggugah.
Desain digital modern sengaja meniru pola ini. Infinite scroll (fitur gulir konten yang terus menerus tanpa henti) auto-play (pemutaran otomatis video atau konten berikutnya) dan notifikasi bukan kebetulan, melainkan strategi ilmiah untuk mempertahankan keterlibatan emosional. Platform menjadi kasino mental, dan pengguna menjadi penjudi atas kesadarannya sendiri.
Setiap guliran jempol adalah tarikan tuas, setiap notifikasi lonceng peluang berikutnya. Kemenangan kecil berupa like atau komentar menciptakan ilusi makna, sementara kekosongan mendorong pencarian berikutnya. Lama-kelamaan, siklus adiksi yang tampak seperti kebiasaan membentuk pengendalian struktural, dimulai dari alam pikir yang dikendalikan algoritma.
Lingkungan digital berfungsi sebagai extended mind (perpanjangan pikiran melalui alat atau teknologi yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak), perpanjangan pikiran yang dikendalikan. Ia membentuk cara berpikir sebagaimana ruang fisik membentuk cara hidup. Namun berbeda dari lingkungan fisik yang masih memiliki batas nyata, lingkungan digital bersifat plastis dan tanpa batas jelas. Ia menyesuaikan diri dengan pengguna sekaligus membentuk pengguna itu sendiri, hingga lama-kelamaan menggantikan sebagian fungsi pengguna.
Personalisasi konten menciptakan gelembung persepsi, filter bubble (gelembung informasi yang membatasi pandangan individu hanya pada konten yang sesuai preferensinya), mempersempit cakrawala dunia menjadi parsial dan terputus dari makna idealnya. Kendali atas pikiran tidak bekerja dengan memberitahu apa yang seharusnya dipikirkan, tetapi menentukan apa yang boleh dipikirkan sesuai preferensi sistem. Dunia di layar bukanlah dunia nyata, melainkan dunia imitasi yang mengendalikan hidup, seperti aforisme gua Plato, di mana bayangan dianggap sebagai realitas.
Fenomena ini memiliki konsekuensi ekonomi besar. Kapitalisme digital menemukan model produksi baru, tidak lagi bergantung pada manufaktur, tetapi pada pengolahan kendali kesadaran. Data menjadi bahan mentah baru, perhatian menjadi energi, dan algoritma menjadi mesin yang mengubah perhatian menjadi nilai lebih. Nilai ekonomi dihasilkan bukan dari barang, tetapi dari perhatian yang ditaklukkan untuk menopang sistem kendali. Kelangkaan utama bukan modal atau tenaga kerja, tetapi fokus manusia di tengah gempuran informasi. Karena perhatian terbatas, ia menjadi komoditas paling berharga di pasar global.
Selain itu, ekonomi perhatian (attention economy: model ekonomi di mana perhatian manusia menjadi sumber daya yang bisa dimonetisasi) bekerja dengan prinsip paradoksal: semakin banyak informasi, perhatian manusia semakin langka. Information overload (kondisi di mana jumlah informasi yang diterima seseorang melebihi kapasitas untuk memprosesnya) menciptakan defisit makna karena distribusi informasi tidak tepat sasaran.
Perusahaan digital bersaing untuk merebut sebagian kecil atensi manusia. Setiap detik di platform adalah pertarungan antara ribuan algoritma yang berlomba mengoptimalkan konten agar pengguna semakin tenggelam (virtual presence dominance: dominasi kehadiran pengguna dalam ruang digital). Pertarungan ini mendorong produksi konten yang paling ekstrem secara emosional karena hanya emosi kuat mampu menembus kebisingan informasi.
Akibatnya, ekonomi perhatian mendorong polarisasi, sensasionalisme, dan degradasi kualitas wacana publik karena melalui strategi ekstrem platform dapat menduplikasi kehadirannya dalam alam pikir pengguna. Tidak jarang, demi jumlah like, banyak pihak membuat konten ekstrem yang membahayakan diri sendiri. Kuantifikasi afirmasi (mengukur interaksi pengguna seperti like dan share sebagai nilai ekonomi) menjadi tujuan utama produksi konten, sehingga informasi bernilai pengetahuan mulai kehilangan urgensi.
Kita dapat melihat logika ini di media sosial: kemarahan, kebencian, dan skandal lebih menguntungkan daripada dialog, empati, atau refleksi. Algoritma tidak peduli pada kebenaran atau kebajikan, fokusnya hanya pada pengoptimalan keterlibatan, meskipun caranya ekstrem. Oleh karena itu, moral outrage (ledakan kemarahan moral kolektif di ruang digital) menjadi produk sampingan yang efektif. Semakin besar kemarahan, semakin tinggi keterlibatan pengguna, semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan.
Dengan demikian, kemarahan menjadi mata uang baru kapitalisme digital, sementara perpecahan sosial menjadi model bisnis strategis. Terkadang, untuk sistem tetap beroperasi, dibutuhkan tindakan immoral sebagai langkah strategis, karena moralitas hanya bentuk parsial dari kompleksitas yang direduksi dalam eksistensi sistem akumulasi tanpa batas.
Fenomena lain menunjukkan bahwa kebodohan kerap menjadi strategi. Hilangnya cara pandang sehat dalam memaknai realitas muncul dalam fenomena seperti goyang sadboor, di mana kekejaman atau digital psychopathy (perilaku psikopat yang dipengaruhi oleh konteks digital) diatribusi dan dipertontonkan melalui mekanisme digital. Ini adalah bentuk lain dari kebodohan yang diproduksi: disrupsi realitas yang dimediasi algoritma, yang mengakumulasi dirinya sebagai bagian dari strategi operasional platform digital. Konsep monkey cage (kandang monyet: metafora untuk kebebasan semu dalam kontrol sistem digital) menjadi metafora: pengguna tampak bebas bergerak, namun perilaku dan perhatian mereka dikontrol desain platform. Di balik kontrol ini, dorongan pengguna yang kehilangan nalar atas nama hiburan memperkuat candu sistem.
Fenomena lain adalah moral outrage, ledakan kemarahan moral di ruang digital, yang menjadi gejala ekonomi perhatian yang digerakkan algoritma. Emosi ini muncul secara kolektif dari kombinasi frustrasi sosial, distorsi informasi, dan desain sistem yang memperkuat resonansi emosional. Algoritma bekerja dengan prinsip keterlibatan maksimum dan repetitif; emosi intens seperti marah, takut, dan jijik lebih mudah menyebar secara digital.
Setiap reaksi kemarahan dianggap sinyal keberhasilan strategis. Keterlibatan meningkat, waktu layar bertambah, dan pertumbuhan data terakselerasi. Dalam paradoks yang menyedihkan, kemarahan menjadi rasional secara ekonomi meski destruktif secara moral. Fenomena ini menyerupai digital Salem (referensi historis pada perburuan penyihir, digunakan sebagai metafora penghakiman digital), di mana intimidasi dilakukan melalui penghakiman digital, yang memicu pelepasan dopamin. Kemarahan yang dimediasi algoritma cepat hadir, cepat tenggelam, dan digantikan kemarahan berikutnya. Ruang publik digital kehilangan fungsi deliberatifnya, berubah menjadi arena emosi massal yang dimonetisasi.
Terorisme digital bekerja melalui penyebaran ketakutan, manipulasi persepsi, dan pembentukan musuh imajiner yang terus diperbarui. Ia adalah kekuasaan baru yang menguasai saraf dan afeksi, bukan tubuh. Individu tidak berhadapan dengan tiran yang memaksa, tetapi sistem yang menuntun perilaku tertentu. Kekuasaan menjadi difus, tersebar, dan bekerja melalui norma sosial yang diinternalisasi. Michel Foucault menyebutnya biopolitik digital (kontrol sosial atas kehidupan individu melalui regulasi perilaku dan perhatian): kekuasaan yang mengatur kehidupan melalui regulasi atensi, perilaku, dan hasrat.
Namun kekuasaan ini bukan hanya Foucauldian. Ia memiliki dua wajah dystopian klasik: Orwellian (pengawasan total dan represi mirip novel George Orwell) dan Huxleyan (pengendalian melalui kenikmatan dan hiburan mirip Brave New World). Versi Orwellian memanipulasi melalui ketakutan, pengawasan, dan represi; menindas kebenaran dengan menutupinya. Versi Huxleyan bekerja melalui kenikmatan, hiburan, dan kepuasan; menindas kebenaran dengan membuat manusia tak peduli. Dunia digital menggabungkan keduanya: algoritma mengawasi seperti Big Brother (pengawas total tanpa batas privasi), namun membius seperti Soma (zat yang menenangkan dan membuat patuh dalam Brave New World). Kita diawasi dengan sukarela karena pengawasan hadir dalam bentuk kenyamanan.
Kombinasi ini menciptakan situasi unik dalam sejarah kesadaran manusia. Pengawasan tidak lagi datang dari luar, tetapi ditanamkan di dalam diri. Manusia menginternalisasi logika otomatisasi digital, menilai eksistensi melalui angka, dan mengukur nilai diri dengan validasi digital. Dalam terminologi Byung-Chul Han, kita telah berubah dari society of discipline (masyarakat disiplin) menjadi society of achievement (masyarakat pencapaian): individu menindas diri demi performa (auto-exploitation: eksploitasi diri sendiri). Kekuasaan tidak lagi memerintah tetapi memotivasi; tidak memaksa tetapi mengajak. Itulah bentuk kekuasaan paling sempurna: manusia mencintai belenggunya dan tercandu oleh makna simbolis yang diproduksi para penindasnya.
Logika ekonomi kapitalisme digital terus berkembang. Setiap interaksi sosial menjadi peluang kapitalisasi, setiap relasi diukur dalam potensi pasar. Teman, pengikut, dan audiens bukan lagi jaringan sosial, melainkan aset yang dapat dimonetisasi. Influencer menjadi figur paradigmatik: tubuh, gaya hidup, dan pikirannya diubah menjadi komoditas. Subjektivitas bukan lagi ruang otonomi, tetapi portofolio yang harus dikelola agar menarik bagi algoritma.
Kapitalisme digital bukan hanya sistem ekonomi, melainkan industri manufaktur kesadaran. Ia memproduksi individu selalu terhubung, terukur, dan termotivasi impulsif oleh rangsangan eksternal. Manusia kehilangan kemampuan berdiam, bermeditasi, atau memilah prioritas; kendali atas diri ternegasikan oleh rangsangan digital. Dunia yang menuntut respons terus-menerus menghancurkan kemampuan mengalami keheningan, karena kontemplasi (refleksi mendalam dan meditasi) merupakan habitus yang mengkondisikan cara kerja epistemik organik berjalan optimal. Keheningan adalah syarat dasar refleksi serta kebebasan produktif dan inovatif. Tanpa ruang reflektif di antara stimulus dan respons, manusia mengalami amputasi epistemik (hilangnya kapasitas untuk berpikir dan memahami realitas secara mendalam), gangguan fungsi berpikir.
Krisis kesadaran bukan sekadar krisis informasi, tetapi krisis eksistensial. Kita tidak kekurangan pengetahuan, tetapi kehilangan orientasi dan kendali untuk memaknai kehidupan. Terlalu banyak sinyal membuat pikiran tidak mampu membedakan penting dan tidak penting. Dalam kondisi ini, manusia terjebak dalam the society of the spectacle (masyarakat pertunjukan di mana representasi lebih dominan daripada realitas): masyarakat di mana representasi menggantikan realitas, dan citra lebih nyata daripada kenyataan. Platform digital menciptakan versi dunia yang lebih menarik, lebih intens, dan adiktif.
Seluruh pengalaman dikurasi algoritma; dunia menyerupai cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Dalam gelembung personalisasi, kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana diinginkan kuasa manipulasi sistem algoritma. Pengalaman bersama berakhir, fondasi politik dan kebudayaan masyarakat runtuh. Setiap orang hidup dalam semesta digitalnya sendiri, dengan kebenaran yang disesuaikan, berita yang diatur, dan musuh yang dipilihkan. Fragmentasi kognitif (pemisahan atau pecahnya cara berpikir individu secara terisolasi) memperlemah solidaritas sosial dan memperkuat tribalitas emosional (kecenderungan berkelompok berdasarkan kesamaan emosional atau identitas). Masyarakat kehilangan ruang tengah, arena bersama tempat perbedaan dinegosiasikan. Fenomena ini sejalan dengan Abilene Paradox (situasi di mana kelompok membuat keputusan yang tidak diinginkan individu karena mengira mayoritas setuju), di mana kelompok mengambil keputusan yang sebenarnya tidak diinginkan anggota karena percaya keinginan mereka bertentangan dengan mayoritas. Algoritma menciptakan kesan mayoritas melalui personalisasi konten dan filter bubble sehingga perilaku kolektif sering bertentangan dengan preferensi individu, memperkuat homogenitas semu sekaligus fragmentasi sosial.
Paradoks mendalam muncul: semakin terhubung dunia, semakin terpecah kesadaran manusia. Teknologi yang seharusnya memperluas horizon justru menyempitkannya. Algoritma yang dirancang untuk memahami manusia kini memprediksi manusia lebih baik daripada manusia memahami dirinya sendiri. Ini bukan soal privasi semata, tetapi otonomi. Ketika sistem memprediksi dan memengaruhi keputusan sebelum kesadaran menyadarinya, garis batas antara kebebasan dan determinasi kabur. Kebebasan tersisa hanyalah memilih di antara opsi yang telah ditentukan (persuasive design: desain sistem yang memengaruhi keputusan pengguna tanpa paksaan langsung).
Namun, selalu ada celah untuk refleksi. Kesadaran manusia, betapapun dikepung arsitektur algoritmik, masih dapat menyadari bahwa ia dikendalikan. Kesadaran tentang ketidakbebasan adalah awal kebebasan. Perlawanan bukan berarti menolak teknologi, tetapi menolak logika ekonomi yang mereduksi manusia menjadi data dan pasar atensi yang eksploitatif dan adiktif. Emansipasi kesadaran berarti merebut kembali hak untuk mengambil jarak, berpikir reflektif, dan mengalami realitas secara utuh sebagai subjek yang hidup, mampu mengkontestasi bangunan realitas imitatif yang dikontrol industri platform.
Diperlukan gerakan epistemologis: pengembalian teknologi ke horizon etika dan politik. Algoritma harus dipahami sebagai kekuatan yang tidak netral dan dikontestasikan dengan kebutuhan manusia mengembangkan potensinya. Transparansi dan akuntabilitas arsitektur digital dibutuhkan sebagai kontestasi epistemik, bukan kontrol negara. Pendidikan kritis terhadap teknologi juga diperlukan. Literasi digital saat ini sering ditentukan sepihak oleh relasi kuasa yang timpang karena feodalisme digital membangun ekosistem brutal tanpa mekanisme koreksi produktif.
Di tingkat individu, resistensi dimulai dengan tindakan kecil namun radikal: memulihkan perhatian sebagai kepemilikan diri, mempraktikkan hening sebagai perlawanan terhadap kebisingan, dan memulihkan kemampuan untuk tidak selalu terhubung. Dalam dunia yang menilai eksistensi melalui aktivitas, diam menjadi tindakan politik. Dalam dunia yang mengukur nilai melalui visibilitas, menyembunyikan diri menjadi bentuk kebebasan.
Krisis kesadaran di era algoritma bukan hanya tantangan teknologi, tetapi ujian eksistensial manusia modern. Apakah kita menjadi spesies yang menyerahkan maknanya pada mesin, atau makhluk yang menggunakan mesin untuk memperdalam makna keberadaannya? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab algoritma karena menyangkut inti kemanusiaan: kemampuan menyadari, memilih secara reflektif, dan menolak ketika segala sesuatu diatur agar kita tidak menolak.Kesadaran manusia telah lama menjadi medan pertarungan antara kebebasan dan kekuasaan. Kini, medan itu berpindah ke ruang digital, tempat algoritma berperan sebagai penguasa tak kasatmata. Namun sejarah menunjukkan setiap sistem yang mencoba menguasai seluruh kesadaran manusia selalu berakhir pada kontradiksinya sendiri. Kesadaran, sejauh masih mampu bertanya “mengapa aku berpikir seperti ini?” selalu mengandung potensi melampaui struktur yang membentuknya. Di titik itulah harapan tetap hidup: bukan harapan teknologi, tetapi harapan eksistensial—bahwa manusia, meski dikepung algoritma, tetap dapat menjadi subjek yang berpikir, bukan objek yang dikendalikan.
Daftar Pustaka.
· Byul Hung Chan. (2020). Burnout Society. Jakarta: Penerbit Kompas.
· Dylan J. White. (2020). Paying Attention to Attention: Psychological Realism and the Attention Economy. New York: Routledge.
· Christian Fuchs. (2014). Membaca Kembali Marx di Era Kapitalisme Digital. Leiden: Brill.
· United Nations Economist Network. (2021). Attention Economy: New Economics for Sustainable Development. New York: United Nations.
· Williams, J. (2018). Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
Penulis: Daniel Russell, Alumni GMNI Bandung.