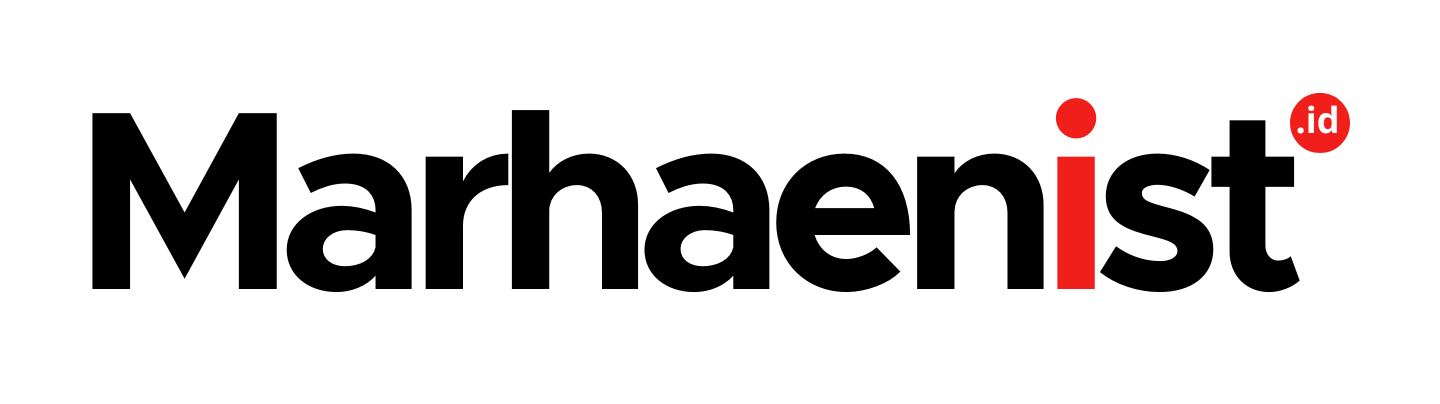Marhaenist.id – Pancasila adalah dasar falsafah negara, pandangan hidup bangsa dan norma dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan didasarkan pada pidato penggali Pancasila, yakni Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan “teks kosong” yang hanya bersifat legal, melainkan suatu filsafat politik yang sistematis dan komprehensif. Konsep Pancasila dasar negara yang selaras dengan konsep filsafat Pancasila sebagaimana dicetuskan oleh Sukarno, membuat dasar negara ini sangat layak dijadikan sebagai objek studi ilmiah, terutama dalam konteks filsafat.
Dalam kaitan ini, konsep Pancasila yang dicetuskan Sukarno merupakan filsafat politik yang ia rumuskan berdasarkan metodologi pemikiran sosial tertentu, dalam hal ini, materialisme historis sebagaimana dikembangkan dalam tradisi filsafat sosial radikal.
Oleh karenanya, sangat memungkinkan ia dikaji melalui metode materialisme historis tersebut yang dianalisasi dalam perspektif filsafat ilmu. Dalam konteks ini, filsafat ilmu merupakan “metode analitis” untuk memilah dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis dari filsafat Pancasila yang sejak awal dirumuskan oleh Sukarno melalui metode materialisme historis.
Dalam hal ini, pemikiran Pancasila Sukarno menempati posisi sentral dalam sejarah intelektual Indonesia modern. Ia bukan sekadar rumusan dasar negara, melainkan kristalisasi dari seluruh proses historis, sosial, dan intelektual bangsa Indonesia yang sedang mencari bentuk dirinya di tengah arus kolonialisme dan modernitas Barat.
Dalam pandangan Sukarno, Pancasila bukan hanya hasil perenungan individual seorang filsuf, melainkan buah dari pengalaman kolektif bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan. Karena itu, Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks material dan historis tempat ia lahir.
Tulisan ini berangkat dari pandangan bahwa untuk memahami Pancasila secara mendalam, diperlukan pendekatan materialisme historis dan filsafat ilmu. Materialisme historis memberikan kerangka untuk menafsirkan gagasan-gagasan Pancasila Sukarno sebagai produk dari kondisi sosial-ekonomi dan perjuangan historis bangsa Indonesia.
Pemikiran Pancasila yang digali Sukarno merupakan kristalisasi dari pemikiran dan perjuangannya dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Inilah yang membuatnya menggunakan materialisme historis yang memiliki visi yang sama dengan Marxisme meskipun dalam konteks yang berbeda.
Sementara filsafat ilmu memberi perangkat reflektif untuk menelaah bagaimana Sukarno membangun bentuk pengetahuan yang khas—pengetahuan yang berpijak pada realitas empiris bangsa, tetapi juga mengandung cita-cita transendental tentang kemanusiaan dan keadilan.
Sukarno tidak menulis sistem filsafat yang tertutup. Ia lebih menyerupai pemikir praksis yang menyatukan gagasan dengan tindakan, teori dengan sejarah. Karena itu, Pancasila dalam pemikirannya dapat dilihat sebagai suatu epistemologi praksis, yaitu cara berpikir yang menempatkan pengetahuan dalam fungsi sosialnya: membebaskan manusia dan membangun masyarakat yang berkeadilan.
Di sini, relevansi filsafat ilmu menjadi kuat, sebab ia menghubungkan dimensi ontologis (realitas masyarakat kolonial), epistemologis (cara bangsa memahami dirinya), dan aksiologis (tujuan moral pengetahuan itu sendiri).
Tulisan ini juga berupaya memulihkan dimensi filosofis dan ilmiah dari Pancasila yang sering kali tereduksi menjadi slogan politik. Dengan menempatkan pemikiran Pancasila dalam kerangka filsafat ilmu, kita dapat melihat bahwa Pancasila sebenarnya mengandung struktur pengetahuan yang utuh: berangkat dari pengalaman material, berkembang melalui refleksi rasional, dan berujung pada cita-cita moral universal. Inilah yang disebut sebagai ilmu sosial transendental—sebuah bentuk pengetahuan yang menolak reduksi positivistik, namun tetap berpijak pada realitas empiris sejarah manusia.
Dengan demikian, uraian dalam tulisan ini berusaha mengurai Pancasila, bukan sebagai mitos ideologis, melainkan sebagai konstruksi intelektual yang lahir dari dialektika sejarah bangsa dan pemikiran dunia modern. Melalui pendekatan materialisme historis, kita menelusuri akar sosial pembentuk gagasan Pancasila yang sejak awal dirumuskan Sukarno. Melalui filsafat ilmu, kita menilai rasionalitas dan struktur epistemologisnya. Pada akhirnya, tujuan dari kajian ini bukan sekadar memahami Sukarno sebagai tokoh sejarah, tetapi menempatkannya kembali sebagai pemikir ilmiah bangsa, yang melihat Pancasila sebagai metode berpikir, bukan hanya dasar bernegara.
Pemikiran Pancasila Sukarno
Pemikiran Sukarno tentang Pancasila lahir dari konteks sosial, politik, dan historis bangsa Indonesia yang tengah berjuang membebaskan diri dari kolonialisme. Ia bukan sekadar hasil renungan metafisis seorang pemikir, melainkan kristalisasi pengalaman kolektif rakyat yang berabad-abad hidup dalam penindasan. Dalam pidato bersejarah di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945, Sukarno mengatakan bahwa dasar negara Indonesia harus berakar dari jiwa bangsa sendiri dan bukan hasil meniru ideologi asing (Sukarno, 1947: 5). Ia menyebut lima dasar yang kemudian dinamakan “Pancasila” — Kebangsaan Indonesia, Perikemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang semuanya, menurutnya, telah hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia sejak lama.
Sukarno menolak menjadikan ideologi negara sebagai dogma yang kering. Ia ingin dasar negara yang hidup dalam denyut nadi rakyat. Baginya, nasionalisme Indonesia harus berangkat dari kesadaran sosial bahwa bangsa yang besar tidak dapat berdiri di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Dalam tulisan-tulisan awalnya pada 1926–1933, Sukarno banyak menguraikan kritik terhadap kapitalisme dan kolonialisme yang telah menciptakan struktur penindasan ekonomi. Ia menulis bahwa “penindasan ekonomi adalah induk dari segala penjajahan” (Sukarno, 1964: 112). Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa gagasan Pancasila pada akhirnya tumbuh dari kerangka material-historis: perjuangan melawan sistem ekonomi kolonial yang menindas dan pencarian tatanan sosial yang adil.
Konsep Marhaenisme yang diperkenalkan Sukarno sejak 1927 menunjukkan kerangka pikir sosial-ekonominya. Ia menceritakan perjumpaannya dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung Selatan yang memiliki tanah dan alat kerja sendiri tetapi tetap hidup miskin. Dari pengalaman itu, Sukarno menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kolonial tidak memberi ruang bagi rakyat kecil untuk sejahtera, bahkan ketika mereka memiliki alat produksi. “Marhaen bukan proletar, tetapi ia tertindas oleh sistem,” tulis Sukarno (Sukarno, 1964: 134). Gagasan ini menjadi akar sosial dari sila kelima Pancasila, “Kesejahteraan atau Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, yang dimaksudkan sebagai penolakan terhadap eksploitasi manusia atas manusia.
Dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno menjelaskan bahwa sila Ketuhanan YME menegaskan pentingnya kehidupan spiritual bangsa tanpa menjadikan negara teokratis. Ia berkata, “Negara Indonesia hendaknya menjadi negara yang bertuhan, tetapi tiap orang hendaknya bertuhan menurut cara masing-masing” (Sukarno, 1947: 10). Pernyataan ini memperlihatkan pandangan pluralis yang mengakui keberagaman kepercayaan rakyat Indonesia. Sukarno tidak memandang agama sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kekuatan moral yang menumbuhkan solidaritas sosial dan rasa kemanusiaan.
Sila kedua, “Perikemanusiaan atau Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menurut Sukarno adalah reaksi moral terhadap praktik dehumanisasi kolonialisme. Ia menyebut bahwa imperialisme telah menghancurkan martabat manusia Timur dan menjadikan bangsa-bangsa terjajah sebagai obyek eksploitasi. Oleh sebab itu, kemerdekaan bangsa harus juga menjadi pembebasan manusia dari perendahan martabat. Dalam tulisannya pada 1930, ia menulis, “Pergerakan nasional adalah pergerakan kemanusiaan, karena ia menentang sistem yang memeras manusia oleh manusia” (Sukarno, 1964: 187).
Sila Kebangsaan atau Persatuan Indonesia sebagai sila pertama dalam usulan 1 Juni 1945, bagi Sukarno bukan sekadar kesatuan teritorial, melainkan solidaritas historis yang mengatasi perbedaan suku, agama, dan kelas. Ia berkata, “Persatuan yang kita maksud bukan uniformitas, melainkan gotong royong dari segala lapisan masyarakat” (Sukarno, 1947: 12). Pandangan ini selaras dengan konsep sosialisme gotong royong yang kelak ia kembangkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, nilai persatuan bukan dogma politik, tetapi sintesis dari realitas sosial yang majemuk dan pengalaman penderitaan bersama di bawah penjajahan.
Sukarno juga menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus berbeda dengan demokrasi liberal Barat. Ia menolak individualisme yang menjadi dasar sistem parlementer kapitalistik. Demokrasi Indonesia, katanya, “harus berdasarkan musyawarah dan mufakat yang berakar dalam jiwa bangsa” (Sukarno, 1947: 15).
Pandangan ini memperlihatkan konsepsi demokrasi partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek kekuasaan. Dalam kerangka Pancasila, inilah isi sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai-nilai Pancasila tersebut, jika dibaca dalam keseluruhan konteks pemikiran Sukarno, bukanlah ide yang mengawang-awang. Ia lahir dari kesadaran material dan praksis sejarah bangsa. Legge (1972: 56) mencatat bahwa Sukarno sejak muda sudah berupaya menyatukan gagasan nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme sebagai tiga kekuatan revolusioner yang dapat menggerakkan rakyat Indonesia. Pancasila adalah wujud sintesis dari tiga ide besar itu. Nasionalisme memberikan arah perjuangan kebangsaan, Islamisme memberi dasar etika, dan sosialisme memberi kerangka keadilan sosial.
Pada masa awal kemerdekaan, Sukarno menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi perjuangan revolusi. Ia berkata dalam pidato 17 Agustus 1959 bahwa “Pancasila adalah alat pemersatu, pedoman hidup, dan bintang penuntun revolusi Indonesia” (Sukarno, 1964: 423). Dengan demikian, Pancasila bersifat dinamis dan historis, bukan teks yang beku. Ia tumbuh bersama perjalanan bangsa dan harus terus ditafsirkan melalui praksis sosial.
Hal ini ditegaskan dalam Sarinah (1947), dimana Sukarno menegaskan keterkaitan antara pembebasan perempuan dan cita-cita Pancasila. Ia menulis bahwa perjuangan perempuan bukan hanya perjuangan jenis kelamin, melainkan bagian dari perjuangan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan sosial (Sukarno, 1947b: 38). Pandangan ini memperluas makna kemanusiaan dalam Pancasila ke ranah kesetaraan sosial yang konkret.
Bagi Sukarno, Pancasila adalah bentuk khas dari humanisme Indonesia. Ia bukan humanisme individualistik sebagaimana lahir di Barat, melainkan humanisme yang berpijak pada gotong royong dan solidaritas sosial. Dalam pidato 1 Juni 1945, ia bahkan mengatakan bahwa jika Pancasila diperas menjadi satu sila saja, maka intinya adalah gotong royong (Sukarno, 1947: 17). Gotong royong inilah yang menjadi dasar moral dan sosial dari seluruh sila lainnya. Ia menyatukan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam satu prinsip praksis.
Dengan demikian, pemikiran Sukarno tentang Pancasila merupakan upaya untuk menempatkan ideologi negara di tengah dialektika antara realitas material bangsa dan cita-cita moral universal. Ia memadukan gagasan Karl Marx tentang keadilan sosial dengan semangat humanisme dan spiritualitas Nusantara. Dalam istilahnya sendiri, Pancasila adalah “Philosophische Grondslag” atau dasar filsafat bagi negara merdeka (Sukarno, 1947: 3), tetapi bukan filsafat yang berhenti di tataran ide. Ia adalah filsafat tindakan, filsafat rakyat yang menuntut keadilan dan persamaan.
Pemikiran ini memperlihatkan bahwa Pancasila menurut Sukarno tidak dapat dipahami secara metafisik semata, melainkan sebagai konstruksi historis yang hidup. Ia menyerap pengaruh sosialisme Eropa, nasionalisme Asia, dan spiritualitas Timur, tetapi mengolah semuanya menjadi milik bangsa Indonesia sendiri. Dalam pandangan filsafat ilmu, Pancasila Sukarno mengandung kesadaran epistemologis bahwa pengetahuan tentang bangsa harus lahir dari pengalaman sejarah bangsa itu sendiri. Kebenaran Pancasila bukanlah kebenaran logis deduktif, melainkan kebenaran historis-praksis yang dibuktikan dalam perjuangan sosial. Karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilepaskan dari kondisi material rakyat yang menuntut keadilan, kemerdekaan, dan martabat manusia.
Perspektif Materialisme Historis
Pemahaman tentang ideologi negara tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial-ekonomi yang melingkupinya. Demikian pula Pancasila yang tidak hanya merupakan dasar negara legal, tetapi dasar filosofis negara yang lahir dari perjuangan material melawan kolonialisme.
Dalam tradisi kritik sosial Barat, Karl Marx menegaskan bahwa kesadaran manusia bukanlah sesuatu yang spontan atau murni ideal, tetapi ditentukan oleh “keadaan sosial mereka” — kondisi produksi, distribusi, dan relasi sosial yang sudah ada. Dalam penggalan penting dari karyanya The German Ideology bersama Friedrich Engels, Marx menuliskan bahwa sejarah manusia sejatinya adalah sejarah produksi kehidupan material manusia (Marx & Engels, 1846: 31). Pernyataan ini memiliki implikasi radikal: bahwa ideologi maupun norma seperti dasar negara, seringkali bukan hanya produk dari pemikiran filosofis, melainkan juga refleksi atas kondisi material dan perjuangan sosial yang konkret.
Ketika kita membawa lensa materialisme historis ke dalam pembacaan atas dasar negara Pancasila sebagaimana digagas oleh Sukarno, kita membuka medan analisis yang membongkar lapisan ide dan nilai ke dalam komposisi historis-material bangsa Indonesia. Sukarno tidak hanya merumuskan lima sila sebagai kumpulan nilai normatif; ia memposisikan Pancasila sebagai jawaban atas situasi sosial-ekonomi bangsa yang terjajah, terbelah oleh kelas, dan terikat oleh eksploitasi kolonial. Dalam konteks ini, basis material (mode produksi, relasi sosial) pada masa kolonial menggerakkan munculnya kesadaran nasional yang kemudian dirumuskan ke dalam Pancasila.
Menurut Marx, basis material (economic base) menentukan bentuk suprastruktur — politik, hukum, ideologi — meskipun tidak secara deterministik sempit. Apa yang diajukan Sukarno dalam Pancasila, terutama sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) merefleksikan tuntutan material rakyat Indonesia yang lama terpinggirkan dalam struktur kolonial dan pascakolonial. Kesadaran kerakyatan dan keadilan sosial tidak muncul dalam ruang hampa; ia lahir dari pengalaman konkret rakyat yang berjuang melawan dominasi ekonomi, penghisapan sumber daya, dan ketidaksetaraan kelas yang diwarisi dari sistem kolonial.
Dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka harus menjamin bahwa “tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa … sehormat-menghormati satu sama lain” (Sukarno, 1947: 10). Pernyataan ini tidak hanya menyentuh ranah spiritual, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan diposisikan dalam ruang sosial yang plural dan historis. Nilai Ketuhanan yang Berkebudayaan bagi Sukarno bukan hanya klaim metafisik, melainkan pengakuan terhadap keberagaman dan latar sejarah sosial bangsa. Dengan demikian, ide dasar ketuhanan itu sendiri tidak bebas dari struktur sosial bangsa: ia muncul dalam konteks yang material, yaitu masyarakat plural yang selama penjajahan dan pascakolonial dilukai dan terbagi. Pancasila oleh Sukarno menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual dan kondisi historis bangsa.
Materialisme historis menegaskan bahwa perubahan sosial terjadi melalui kontradiksi antara kekuatan produksi (productive forces) dan hubungan produksi (relations of production). Sukarno dalam pemikirannya menyadari bahwa bangsa Indonesia menghadapi kondisi di mana rakyat kecil – yang ia sebut “Marhaen” – memiliki sedikit alat produksi tetapi tetap tertindas oleh sistem kolonial yang mengontrol distribusi dan relasi sosial (Sukarno, 1964: 134). Dari situ muncul kesadaran bahwa negara merdeka harus berbeda: tidak hanya bebas dari penindasan politik, tetapi juga harus mampu merombak relasi produksi agar rakyat memiliki kesempatan sejajar dalam kesejahteraan sosial. Dengan demikian Pancasila—terutama sila demokrasi dan keadilan sosial—menjadi wujud ideologis perjuangan material rakyat.
Dari sudut pandang materialisme historis, Pancasila dapat dibaca sebagai produk suprastruktural yang memang terkait dengan basis material produksi bangsa. Basis material Indonesia sebelum kemerdekaan dan pada era awal kemerdekaan digambarkan sebagai masyarakat agraris yang dieksploitasi dalam sistem kolonial, serta kelas rakyat kecil yang belum memiliki akses ke kemakmuran. Sukarno mengartikulasikan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan tetapi awal dari transformasi sosial-ekonomi (Sukarno, 1964: 423). Gagasan ini sesuai dengan teori Marx bahwa ideologi berfungsi untuk menggambarkan dan mereproduksi relasi kekuasaan dalam masyarakat—namun juga memiliki kapasitas untuk mengubahnya bila kekuatan material baru muncul.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Pancasila dalam pemikiran Sukarno merangkul kontradiksi struktural sosial sebagai titik awal ideologis. Marx mengingatkan bahwa ide gagasan mengekspresikan hubungan material manusia, bukan sebaliknya. Ketika Sukarno menegaskan bahwa negara merdeka harus menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, ia berhadapan langsung dengan kondisi material bangsa yang masih sangat timpang. Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan moral, melainkan tuntutan sosial-ekonomi yang konkret. Pancasila melalui sila keadilan sosial menjadi penanda ideologis bahwa relasi produksi yang lama harus digantikan dengan relasi yang lebih egaliter.
Untuk menerapkan kerangka materialisme historis terhadap Pancasila Sukarno, kita melihat bahwa negara Indonesia yang dibayangkan bukanlah negara kapitalis liberal yang memprioritaskan akumulasi modal segelintir elite, melainkan negara bangsa yang memprioritaskan rakyat sebagai subjek sejarah. Sukarno memandang bahwa jika rakyat bukan subjek, maka dasar negara hanya akan menjadi instrumen elite, bukan alat pembebasan. Pandangan ini selaras dengan gagasan Marx bahwa proletariat harus menjadi agen pembebasan diri, bukan objek. Pancasila bagi Sukarno kemudian bukan hanya warisan ideal, tapi warisan praxis – yakni warisan yang lahir dari pengalaman dan perjuangan rakyat, dan diarahkan ke pembebasan sosial-ekonomi.
Saat kita menilik kembali sejarah pascakolonial Indonesia, kita bisa memahami bahwa Pancasila muncul sebagai ideologis nasional yang menjawab kebutuhan transformasi sosial material. Dalam hal ini, materialisme historis menyediakan alat konseptual untuk memahami bagaimana dasar negara itu bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari kondisi sosial-ekonomi yang mendesak: rakyat tertindas, sumber daya diekstrapolasi, kelas sosial tersegmentasi. Sukarno menyadari ini dan menempatkan Pancasila sebagai jembatan antara kondisi tersebut, basis material perjuangan dengan orientasi keadilan sosial dan kemanusiaan universal.
Dengan demikian, membaca Pancasila melalui lensa materialisme historis artinya mengakui bahwa nilai-nilai dasar negara itu tidak hanya simbol elegan, tetapi berkorelasi langsung dengan struktur produksi, relasi sosial, dan perjuangan historis. Sukarno mengartikulasikan Pancasila sebagai landasan negara sekaligus ideologi revolusi nasional, yang memadukan kesadaran nasional, keadilan sosial, dan demokrasi kerakyatan dalam satu konstruksi konseptual.
Proses Penggunaan Materialisme Historis dalam Perumusan Ide Pancasila:
Materialisme Historis (Penggunaan Materialisme Historis untuk menganalisa kolonialisme di Indonesia yang berakar dari kapitalisme Eropa).
Marhaenisme (Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi sebagai kontekstualisasi sosialisme ke dalam nasionalisme dan demokrasi Indonesia).
Pancasila (Marhaenisme plus Ketuhanan YME menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia).
Berdasarkan hal diatas, kita bisa memahami proses metodologis perumusan ide Pancasila oleh Sukarno yang ia lakukan melalui metode materialisme historis.
Pada tahap pertama, Sukarno menggunakan materialisme historis Marxian dalam mengkaji kolonialisme di Indonesia yang merupakan “kepanjangan tangan” dari imperialisme dan kapitalisme. Artinya, kolonialisme bukan hanya merupakan penjajahan politik, tetapi suatu kebijakan politik yang lahir dari kapitalisme Eropa. Ini berarti bahwa kolonialisme di Indonesia merupakan bentuk penindasan politik dari ekspansi kapitalisme. Kolonialisme di Indonesia juga merupakan bagian dari imperialisme global penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang kapitalistik tersebut.
Pada tahap kedua, penggunaan materialisme historis untuk menganalisa kolonialisme-kapitalisme di Indonesia ini membuat Sukarno mencetuskan ide Marhaenisme yang berisi dua ide, yakni Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Dua ide ini merupakan kontekstualisasi dari ide sosialisme ke dalam nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Artinya, sosialisme yang merupakan ideologi dasar dari metode materialisme historis, dihadirkan Sukarno ke dalam konteks kolonialisme di Indonesia. Konteks tersebut adalah nasionalisme dan demokrasi yang merupakan ide-ide utama Sukarno dalam membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme.
Pada tahap ketiga, ide Marhaenisme yang dirumuskan Sukarno berdasarkan metode materialisme historis ini kemudian dikembangkan olehnya menjadi Pancasila. Tambahan ide Ketuhanan YME atas Marhaenisme, membuahkan ide baru Sukarno, yakni Pancasila yang ia usulkan pada sidang pertama BPUPK pada 1 Juni 1945. Marhaenisme tercermin dalam empat sila Pancasila, yakni nasionalisme, humanisme, demokrasi dan sosialisme. Ditambah dengan ide ketuhanan, maka ide Marhaenisme bertransformasi menjadi Pancasila.
Dengan demikian, Pancasila memang dirumuskan Sukarno berdasarkan metode materialisme historis tersebut. Sebab Pancasila bukan ide abstrak, melainkan refleksi dari perjuangan Sukarno dan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari kolonialisme dan kapitalisme.
Pancasila Dalam Kerangka Filsafat Ilmu
Pancasila yang dirumuskan Sukarno melalui metode materialisme historis tersebut, bisa dianalisai berdasarkan tradisi filsafat ilmu. Hal ini dibutuhkan agar “teknis filosofis” dari filsafat Pancasila bisa terumuskan.
Filsafat ilmu pada hakikatnya bertugas menguraikan struktur terdalam dari pengetahuan manusia: bagaimana pengetahuan itu ada (ontologi), bagaimana ia diperoleh (epistemologi), dan untuk apa ia digunakan (aksiologi)? Dalam konteks ini, Pancasila sebagai hasil refleksi mendalam Sukarno bukan hanya dokumen ideologis politik, melainkan juga suatu konstruksi pengetahuan yang berakar pada realitas sosial-historis bangsa.
Oleh karena itu, menganalisis Pancasila melalui kerangka filsafat ilmu berarti menempatkan pemikiran Sukarno pada posisi ilmiah: sebagai hasil olah akal budi yang terikat pada pengalaman empiris bangsa, tetapi juga berorientasi normatif menuju cita-cita kemanusiaan universal (Suriasumantri, 1982: 37).
Dimensi Ontologis: Realitas Manusia dan Bangsa
Dalam tataran ontologis, Pancasila yang dirumuskan Sukarno berangkat dari pemahaman tentang realitas manusia Indonesia yang konkret, bukan manusia abstrak seperti dalam liberalisme Barat. Sukarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah “suatu masyarakat gotong-royong” yang hidup dari kerja bersama dan solidaritas sosial (Sukarno, 1964: 156). Ontologi Pancasila berakar pada eksistensi manusia yang hidup di tengah masyarakat dan sejarah, bukan individu terpisah dari komunitasnya.
Pandangan ini beresonansi dengan filsafat realisme-historis yang dikembangkan Karl Marx, yang menyatakan bahwa “esensi manusia bukanlah abstraksi yang inheren pada individu tunggal, melainkan keseluruhan relasi sosialnya” (Marx, 1845: 423).
Sukarno tidak memisahkan manusia dari dunia sosial-ekonominya. Ia memandang manusia Indonesia sebagai makhluk yang memiliki keterikatan pada alam, pada masyarakat, dan pada sejarah perjuangannya. Karena itu, hakikat manusia dalam Pancasila adalah makhluk sosial-historis yang harus merdeka dari penindasan dan kemiskinan. Secara ontologis, Pancasila menjadi sistem nilai yang menjawab realitas objektif bangsa Indonesia—bukan hasil spekulasi metafisik yang melayang di atas sejarah. Hal ini sesuai dengan pandangan Notonagoro, bahwa Pancasila merupakan “dasar filsafat negara yang berdimensi ontologis manusiawi dan sosial” (Notonagoro, 1975: 21).
Dari sudut filsafat ilmu, realitas yang menjadi objek Pancasila bukan hanya realitas empiris, tetapi juga realitas historis yang mengandung nilai. Menurut Karl Popper, ilmu tidak pernah berdiri netral terhadap nilai, karena setiap teori selalu lahir dari masalah sosial tertentu yang ingin diselesaikan (Popper, 1959: 32). Sukarno menyusun Pancasila dalam situasi bangsa yang terjajah, terpecah, dan miskin. Maka ontologi Pancasila bersumber dari problem real bangsa, yakni penderitaan rakyat dan cita-cita kemerdekaan. Nilai Kebangsaan, Kemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial dan Ketuhanan YME, tidak muncul dari langit, tetapi dari bumi Indonesia yang berdebu oleh kolonialisme. Dengan demikian, Pancasila memiliki basis ontologis yang bersifat empiris-historis.
Dimensi Epistemologis: Pengetahuan dari Pengalaman Sejarah
Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan. Dalam pemikiran Sukarno, pengetahuan tentang dasar negara tidak dibangun dari spekulasi rasional semata, melainkan dari pengalaman sejarah rakyat Indonesia. Sukarno belajar dari realitas sosial, dari penderitaan rakyat kecil yang disebutnya “Marhaen”, dan dari pergulatan bangsa-bangsa tertindas di Asia dan Afrika. Ia menyatakan bahwa “pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang timbul dari pengalaman rakyat sendiri” (Sukarno, 1964: 287). Ini menunjukkan bahwa epistemologi Pancasila bersifat induktif-historis, bukan deduktif-idealistis.
Dalam kerangka filsafat ilmu, pendekatan Sukarno sejalan dengan epistemologi materialisme historis Marx yang menegaskan bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosial-ekonominya (Marx & Engels, 1846: 47). Artinya, pengetahuan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Sukarno memandang bahwa Pancasila lahir dari dialektika antara realitas objektif penjajahan dan kesadaran nasional yang tumbuh di dalamnya. Kesadaran ini bersifat kolektif, bukan individual, dan berkembang melalui perjuangan bersama.
Epistemologi Pancasila dengan demikian bersifat praksis. Pengetahuan bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk mengubah kenyataan. Di sini terlihat pengaruh filsafat praksis yang menolak pemisahan antara teori dan tindakan. Sebagaimana Marx menyatakan dalam Theses on Feuerbach, “para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, tetapi yang penting adalah mengubahnya” (Marx, 1845: 15). Sukarno mempraktikkan prinsip ini secara konkret: Pancasila bukan hanya ide teoritis, melainkan alat pembebasan bangsa. Dalam logika filsafat ilmu, inilah epistemologi yang bersifat transformatif—pengetahuan yang melahirkan perubahan sosial.
Sukarno juga menolak positivisme Barat yang menekankan netralitas dan obyektivitas tanpa nilai. Ia menempatkan ilmu dan ideologi sebagai satu kesatuan dalam perjuangan. Menurut Thomas Kuhn, ilmu tidak berkembang secara linier, melainkan melalui revolusi paradigma yang lahir dari krisis dan konflik sosial (Kuhn, 1962: 92). Sukarno beroperasi dalam konteks krisis kolonial dan menemukan paradigma baru pengetahuan kebangsaan melalui Pancasila. Dengan demikian, epistemologi Pancasila berwatak revolusioner: ia lahir dari konflik sosial dan diarahkan untuk membangun tatanan baru.
Dimensi Aksiologis: Nilai dan Tujuan Pengetahuan
Aksiologi membahas tujuan pengetahuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila dalam pemikiran Sukarno memiliki tujuan moral dan sosial yang jelas, yakni membebaskan manusia dari penindasan dan membangun keadilan sosial. Ia menulis bahwa “revolusi kita bukan sekadar mengganti penguasa, tetapi mengubah sistem kehidupan agar manusia Indonesia hidup bahagia dan adil” (Sukarno, 1964: 401). Dalam pengertian filsafat ilmu, nilai Pancasila adalah nilai praksis, bukan hanya kognitif.
Menurut Jujun S. Suriasumantri, aksiologi ilmu menentukan arah penggunaan pengetahuan—apakah untuk kemanusiaan atau untuk kekuasaan (Suriasumantri, 1982: 110). Pancasila menegaskan arah ilmu bagi kemanusiaan. Ia menolak reduksi manusia menjadi instrumen ekonomi atau politik semata. Sila pertama dan kedua (dalam kerangka Pancasila Dasar Negara) menunjukkan bahwa pengetahuan manusia harus selalu diikat oleh nilai moral dan kemanusiaan, sedangkan sila kelima menegaskan fungsi sosial pengetahuan: menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, aksiologi Pancasila menolak rasionalitas instrumental modern yang diperingatkan oleh Max Weber sebagai “rasionalitas tanpa tujuan kemanusiaan” (Weber, 1947: 147).
Dalam kerangka aksiologis ini, Pancasila bukan hanya sistem nilai negara, tetapi etika ilmu bagi bangsa. Ia menempatkan ilmu dan teknologi di bawah kendali moral kemanusiaan. Sukarno memperingatkan bahwa kemajuan tanpa arah moral hanya akan menghasilkan penindasan baru. Pandangan ini sejalan dengan teori kritis Jürgen Habermas yang menyatakan bahwa ilmu harus diarahkan untuk “emansipasi manusia dari dominasi” (Habermas, 1971: 301). Pancasila menjadi wujud emansipasi itu di Indonesia: ia mengarahkan pengetahuan pada pembebasan rakyat dari struktur sosial yang tidak adil.
Aksiologi Pancasila juga menolak dikotomi antara iman dan rasio. Sukarno menegaskan bahwa Ketuhanan dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang aktif, yang menggerakkan manusia untuk berbuat baik dan adil (Sukarno, 1947: 8). Artinya, nilai religius dalam Pancasila tidak bersifat dogmatis, tetapi etis-humanistik. Filsafat ilmu modern, khususnya pandangan Karl Jaspers, menyebut bahwa kebenaran ilmiah dan kebenaran eksistensial saling melengkapi karena manusia adalah makhluk yang mencari makna (Jaspers, 1953: 61). Dalam kerangka itu, Pancasila memberikan arah makna pada pengetahuan bangsa.
Sintesis: Pancasila sebagai Ilmu Sosial Transendental
Jika tiga dimensi filsafat ilmu tadi kita hubungkan secara utuh, maka Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang bersifat sosial-transendental. Ia sosial karena bersumber dari pengalaman kolektif rakyat Indonesia yang konkret, dan ia transendental karena mengandung nilai-nilai universal yang melampaui kepentingan kelas atau kelompok tertentu. Sukarno tidak hanya membangun sistem nilai politik, tetapi juga sistem pengetahuan bangsa yang memadukan rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas.
Dalam filsafat ilmu, posisi seperti ini menempatkan Pancasila sebagai paradigma ilmiah yang khas Indonesia. Ia melampaui dikotomi Barat antara idealisme dan materialisme. Jika Marx menekankan struktur material sebagai basis kesadaran, Sukarno melengkapinya dengan dimensi moral-spiritual bangsa. Ia menolak idealisme murni yang mengabaikan realitas, tetapi juga menolak materialisme reduksionistik yang mengabaikan nilai. Dengan demikian, Pancasila dalam kerangka filsafat ilmu adalah sintesis antara rasionalitas sosial dan kesadaran etis-spiritual manusia.
Pancasila sebagai ilmu sosial transendental berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang tidak hanya menjelaskan realitas sosial Indonesia, tetapi juga memberikan arah moral untuk mengubahnya. Ia menjadi paradigma ilmiah bangsa, yang di satu sisi berpijak pada realitas empiris-historis, dan di sisi lain menuntun pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam logika filsafat ilmu kontemporer, ini dapat disebut sebagai paradigma integratif yang memadukan “empirical knowledge” dengan “value-based reasoning”. Inilah kekhasan pemikiran Sukarno yang menjadikan Pancasila tidak hanya dasar negara, tetapi juga dasar ilmu pengetahuan nasional.
Kesimpulan Teoretis
Setelah menelusuri pemikiran Sukarno tentang Pancasila melalui dua pendekatan besar, yakni materialisme historis dan filsafat ilmu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dalam pandangan Sukarno bukanlah ide yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari proses historis yang panjang dan dialektis. Ia tumbuh dari kenyataan sosial bangsa Indonesia yang terjajah, miskin, dan terpecah, namun memiliki potensi solidaritas dan moralitas kolektif yang kuat. Dalam konteks ini, Sukarno bertindak sebagai seorang “historical synthesizer” (penyintesa sejarah) yang berhasil mengangkat pengalaman material rakyat menjadi kesadaran ideologis yang sistematis.
Melalui perspektif materialisme historis, kita melihat bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki akar sosialnya yang nyata. Kebangsaan muncul sebagai respons terhadap disintegrasi politik akibat sistem ekonomi dualistik yang diwariskan penjajahan. Kemanusiaan universal lahir dari pengalaman dehumanisasi kolonialisme. Kerakyatan dan keadilan sosial mencerminkan aspirasi kelas tertindas yang menginginkan tatanan baru yang setara. Serta Ketuhanan yang menyatukan keragaman religi bangsa Nusantara yang membuat perjuangan kebangsaan tidak bersifat profan, tetapi transendental.
Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya mencerminkan ide moral, tetapi juga struktur material kesadaran bangsa. Sebagaimana Marx menyatakan bahwa “kesadaran manusia bukan yang menentukan keberadaannya, tetapi keberadaannya sosial yang menentukan kesadarannya” (Marx, 1859: 21), maka Sukarno mengindonesiakan prinsip itu dengan cara memanusiakan realitas sosial Indonesia ke dalam sistem nilai nasional (Sukarno, 1947: 28).
Namun, Sukarno tidak berhenti pada determinisme ekonomi sebagaimana dalam Marxisme klasik. Ia menolak ateisme dan reduksi spiritual yang menafikan dimensi transendental manusia. Di sinilah ia melampaui materialisme historis dan menciptakan sintesis yang khas: humanisme revolusioner yang menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek sejarah. Ia menyerap dialektika Marx, tetapi menempatkannya dalam kerangka etika dan moralitas bangsa Timur. Ia menegaskan bahwa revolusi Indonesia bukan semata-mata perjuangan kelas, tetapi perjuangan kemanusiaan universal yang berakar dalam kepribadian nasional (Sukarno, 1963: 112).
Melalui pendekatan filsafat ilmu, kita dapat memahami bahwa Pancasila Sukarno memiliki struktur epistemologis yang kompleks. Secara ontologis, Pancasila berakar pada realitas sosial bangsa yang konkret. Ia tidak bersumber dari ide abstrak, melainkan dari being sosial Indonesia—realitas empiris yang mengalami penindasan dan perjuangan. Secara epistemologis, pengetahuan tentang Pancasila dibangun melalui refleksi dialektis antara realitas dan kesadaran, antara sejarah dan ide. Pengetahuan itu bersifat induktif-deduktif, menggabungkan pengalaman empiris rakyat dengan refleksi rasional seorang pemimpin. Sukarno tidak hanya menyerap fakta, tetapi mentransformasikannya menjadi nilai universal. Dan secara aksiologis, Pancasila memiliki orientasi praksis yang jelas, yaitu pembebasan manusia dan penciptaan keadilan sosial sebagai tujuan etis dari seluruh sistem pengetahuan bangsa (Suriasumantri, 2003: 110; Kaelan, 2013: 55).
Dengan demikian, Pancasila Sukarno dapat dipahami sebagai ilmu sosial transendental—sebuah struktur pengetahuan yang menggabungkan realitas empiris dengan nilai normatif. Ia menolak pemisahan antara ilmu dan moral, antara fakta dan nilai. Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan cara berpikir bangsa Indonesia yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh relasi sosial. Dalam pandangan ini, Pancasila berfungsi sebagai epistemologi praksis yang berorientasi pada pembebasan, bukan hanya sebagai norma legal-formal negara.
Dari sudut pandang filsafat ilmu, konstruksi Sukarno terhadap Pancasila mengandung kesadaran reflektif tentang hakikat ilmu itu sendiri. Ia menyadari bahwa pengetahuan bukan sekadar cerminan realitas, melainkan sarana untuk mengubah realitas. Pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang berfungsi sosial dan bermakna moral. Inilah yang membedakan Pancasila dari sistem pengetahuan Barat modern yang cenderung positivistik dan instrumental. Pancasila memulihkan makna manusia dalam ilmu pengetahuan, menghubungkan antara kebenaran dan kebaikan, antara pengetahuan dan kemanusiaan (Notonagoro, 1975: 33).
Melalui tiga lapisan filsafat ilmu—ontologis, epistemologis, dan aksiologis—Pancasila terbukti memiliki konsistensi ilmiah sekaligus keunggulan moral. Ia menjadi jembatan antara being dan ought to be, antara kenyataan empiris dan cita-cita normatif bangsa. Ia membentuk sistem pengetahuan yang tidak berhenti pada pemahaman, tetapi menuntun tindakan. Dalam kerangka ini, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga metodologi berpikir bangsa Indonesia dalam memahami dan membangun dunianya.
Pada akhirnya, tulisan ini memperlihatkan bahwa Sukarno adalah pemikir filsafat dalam arti sejati. Ia tidak menulis sistem metafisika tertutup, tetapi merumuskan sistem pengetahuan terbuka yang hidup dalam praksis sejarah. Ia menjadikan realitas sosial Indonesia sebagai laboratorium filsafat. Dengan menggabungkan kesadaran material dan kesadaran moral, ia melahirkan pandangan dunia yang khas—bahwa kebebasan manusia tidak hanya dicapai melalui perubahan struktur ekonomi, tetapi juga melalui pencerahan kesadaran kolektif. Itulah hakikat Pancasila: pengetahuan yang berakar pada bumi dan berorientasi pada langit.
Daftar Pustaka
- Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press, 1971.
- Jaspers, Karl. The Origin and Goal of History. New Haven: Yale University Press, 1953.
- Kaelan. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Legge, J.D. Sukarno: A Political Biography. Sydney: Allen & Unwin, 1972.
- Marx, Karl & Engels, Friedrich. The German Ideology. Edited by C. J. Arthur; London: Lawrence & Wishart, 1970 (original manuscripts 1845–46).
- Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Translated by S. W. Ryazanskaya; London: Lawrence & Wishart, 1970 (original 1859).
- Marx, Karl. “Preface” in A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 8-45.
- Marx, Karl; Engels, Friedrich. Marx & Engels Collected Works, Vol. 5. Moscow: Progress Publishers, 1976.
- Notonagoro. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: BP7, 1975.
- Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, 1959.
- Sukarno. Lahirnja Pantjasila: Pidato 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1947.
- Sukarno. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964.
- Sukarno. Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Rakjat, 1947.
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press, 1947.
Penulis: Djarot Saiful Hidayat, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)